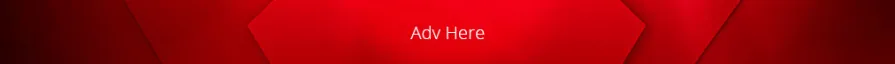Amandemen Yang Membuat Tatanan Menjadi Semrawut

Ilustrasi
Oleh : Gugus Elmo Ra’is
Belajar dari sejarah Orde Baru, kekuasaan eksekutif yang begitu hegemonik (eksekutif heavy) dan dominan yang nyaris tiada kontrol membuat korupsi tumbuh subur. Maka amandemen (perubahan) konstitusi menjadi sebuah keniscayaan. Namun perubahan tanpa dilandasi oleh konsideran yang matang dan komprehensif, hanya akan melahirkan sistem yang semrawut seperti saat ini. Konsep trias politika (pembagian kekusaan) ala Montesque, tidak berjalan sebagai mana mestinya, sehingga terjadi sikap saling ‘sandera’ antara ketiga kekuatan tersebut.
Ada beberapa catatan tentang sistem hasil amandemen, yang memberikan konklusi jika proses perubahan itu telah kebablasan dan menimbulkan komplikasi persoalan. Setelah amandemen UUD 1945 keempat pada tahun 2002, terjadi perubahan yang drastis, bila semula sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi dan dilaksanakan oleh para para wakilnya di DPR/MPR namun pasca amanedemen ketentuan itu dirubah dan dilaksanakan secara langsung. Maka mulai saat itu Pilpres dan Pilkada dilakukan secara langsung, apalagi setelah terbitnya Undang-Undang No 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
Pilpres maupun Pilkada secara langsung terlihat sangat indah untuk mengejawantahkan pomeo demokrasi yang sangat terkenal, vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan), namun sejatinya kita masuk sistem liberalisasi politik yang sangat berbahaya. Pilpres maupun Pilkada memerlukan biaya yang sangat tinggi (high cost politic), baik untuk biaya kampanye maupun biaya penyelenggaraan Pemilu seperti untuk membayar para saksi yang kesemuanya ditanggung oleh para calon. Kondisi inilah yang memberi ruang munculnya para cukong-cukong politik yang sanngup menjadi sponsor, sekaligus pada gilirannya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang oligarkis.
Politik biaya tinggi itulah yang mengakibatkan siapapun pemimpinnya akan tersandera dalam ‘ruang gelap’ politik. Hipotesa ini sekaligus menjawab kenapa korupsi tidak pernah habis dari negeri ini, walau KPK telah berusaha mati-matian memberantas korupsi. Karena dalam hitung-hitungan ekonomi setiap pemimpin itu harus bisa balik modal selama berkuasa. Apabila mereka terbukti tertangkap OTT oleh KPK itu semata-mata karena apes selama berupaya untuk kejar setoran agar minimal bisa balik modal.
Produk amandemen yang kedua yang menimbulkan komplikasi adalah sistem multi partai. Tesis Andrey Heywood (2002) maupun Duverger, memang benar jika partai adalah sarana rakyat untuk berinteraksi dengan pusat kekuasaan dan sistem politik. Duverger mengklasifikasikan menjadi tiga model, partai tunggal, sistem dua partai serta sistem multi partai. Setelah berlaku Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, menggantikan Undang-undang Nomor 31 tahun 2002, maka ada perubahan sistem kepartaian dari sistem dua partai PPP dan PDI serta satu Golongan Karya berubah menjadi sistem multi partai. Alasan penggantian undang-undang lama itu antara lain adalah belum optimalnya UU 31/2002 mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang menuntut peran partai politik (Parpol) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kombinasi antara sistem pemilihan secara langsung dengan sistem multi partai serta Undang-Undang Pemilu menimbulkan persoalan yang semakin rumit dan ruwet. Disatu sisi setiap Capres harus menjalin koalisi untuk memenuhi ketentuan presidential tresshold sebesar 20%, di sisi lain setiap partai harus menawarkan politik identitas untuk menjaring kontituen, disinilah tersemainya bibit-bibit untuk saling mencurigai sesama anak bangsa. Artimya kombinasi sistem itulah yang memberikan kontribusi terbesar potensi terjadinya disintegrasi bangsa.
Karena berbagai factor itulah saya cenderung sepakat dengan tesis Scoot Mainwaring jika sistem multi partai itu tidak cocok dengan Indonesia. Kompleksitas persoalan itu akan semakin rumit dalam proses penentuan kabinet. Di satu sisi presiden memiliki hak prerogatif, untuk menentukan tokoh-tokoh di beberapa pos kementerian, namun di sisi lain presiden juga harus mengakomodir aspirasi partai terutama partai-partai yang telah ‘berjibaku’ untuk memenangkannya sebagai bagian dari ungkapan terima kasih.
Selain dalam penentuan para pembatunya di kabinet, Presiden juga harus mendengarkan suara partai dalam menentukan beberapa jabatan di lembaga tinggi negara seperti, Kapolri, Jaksa Agung, BIN, Ketua KPK, Ketua MA, Ketua MK serta beberapa lembaga tinggi lainnya. Dengan analogi seperti itu, mustahil akan tercipta lembaga negara yang bersih dan independen.***
Belajar dari sejarah Orde Baru, kekuasaan eksekutif yang begitu hegemonik (eksekutif heavy) dan dominan yang nyaris tiada kontrol membuat korupsi tumbuh subur. Maka amandemen (perubahan) konstitusi menjadi sebuah keniscayaan. Namun perubahan tanpa dilandasi oleh konsideran yang matang dan komprehensif, hanya akan melahirkan sistem yang semrawut seperti saat ini. Konsep trias politika (pembagian kekusaan) ala Montesque, tidak berjalan sebagai mana mestinya, sehingga terjadi sikap saling ‘sandera’ antara ketiga kekuatan tersebut.
Ada beberapa catatan tentang sistem hasil amandemen, yang memberikan konklusi jika proses perubahan itu telah kebablasan dan menimbulkan komplikasi persoalan. Setelah amandemen UUD 1945 keempat pada tahun 2002, terjadi perubahan yang drastis, bila semula sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi dan dilaksanakan oleh para para wakilnya di DPR/MPR namun pasca amanedemen ketentuan itu dirubah dan dilaksanakan secara langsung. Maka mulai saat itu Pilpres dan Pilkada dilakukan secara langsung, apalagi setelah terbitnya Undang-Undang No 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
Pilpres maupun Pilkada secara langsung terlihat sangat indah untuk mengejawantahkan pomeo demokrasi yang sangat terkenal, vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan), namun sejatinya kita masuk sistem liberalisasi politik yang sangat berbahaya. Pilpres maupun Pilkada memerlukan biaya yang sangat tinggi (high cost politic), baik untuk biaya kampanye maupun biaya penyelenggaraan Pemilu seperti untuk membayar para saksi yang kesemuanya ditanggung oleh para calon. Kondisi inilah yang memberi ruang munculnya para cukong-cukong politik yang sanngup menjadi sponsor, sekaligus pada gilirannya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang oligarkis.
Politik biaya tinggi itulah yang mengakibatkan siapapun pemimpinnya akan tersandera dalam ‘ruang gelap’ politik. Hipotesa ini sekaligus menjawab kenapa korupsi tidak pernah habis dari negeri ini, walau KPK telah berusaha mati-matian memberantas korupsi. Karena dalam hitung-hitungan ekonomi setiap pemimpin itu harus bisa balik modal selama berkuasa. Apabila mereka terbukti tertangkap OTT oleh KPK itu semata-mata karena apes selama berupaya untuk kejar setoran agar minimal bisa balik modal.
Produk amandemen yang kedua yang menimbulkan komplikasi adalah sistem multi partai. Tesis Andrey Heywood (2002) maupun Duverger, memang benar jika partai adalah sarana rakyat untuk berinteraksi dengan pusat kekuasaan dan sistem politik. Duverger mengklasifikasikan menjadi tiga model, partai tunggal, sistem dua partai serta sistem multi partai. Setelah berlaku Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, menggantikan Undang-undang Nomor 31 tahun 2002, maka ada perubahan sistem kepartaian dari sistem dua partai PPP dan PDI serta satu Golongan Karya berubah menjadi sistem multi partai. Alasan penggantian undang-undang lama itu antara lain adalah belum optimalnya UU 31/2002 mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang menuntut peran partai politik (Parpol) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kombinasi antara sistem pemilihan secara langsung dengan sistem multi partai serta Undang-Undang Pemilu menimbulkan persoalan yang semakin rumit dan ruwet. Disatu sisi setiap Capres harus menjalin koalisi untuk memenuhi ketentuan presidential tresshold sebesar 20%, di sisi lain setiap partai harus menawarkan politik identitas untuk menjaring kontituen, disinilah tersemainya bibit-bibit untuk saling mencurigai sesama anak bangsa. Artimya kombinasi sistem itulah yang memberikan kontribusi terbesar potensi terjadinya disintegrasi bangsa.
Karena berbagai factor itulah saya cenderung sepakat dengan tesis Scoot Mainwaring jika sistem multi partai itu tidak cocok dengan Indonesia. Kompleksitas persoalan itu akan semakin rumit dalam proses penentuan kabinet. Di satu sisi presiden memiliki hak prerogatif, untuk menentukan tokoh-tokoh di beberapa pos kementerian, namun di sisi lain presiden juga harus mengakomodir aspirasi partai terutama partai-partai yang telah ‘berjibaku’ untuk memenangkannya sebagai bagian dari ungkapan terima kasih.
Selain dalam penentuan para pembatunya di kabinet, Presiden juga harus mendengarkan suara partai dalam menentukan beberapa jabatan di lembaga tinggi negara seperti, Kapolri, Jaksa Agung, BIN, Ketua KPK, Ketua MA, Ketua MK serta beberapa lembaga tinggi lainnya. Dengan analogi seperti itu, mustahil akan tercipta lembaga negara yang bersih dan independen.***