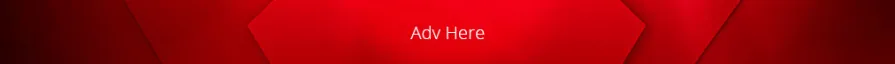Apa Bedanya PKI Dengan ISIS ?

Oleh : Gugus Elmo Ra’is
Karena alasan ideologi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang didirikan oleh Hendricus JFM (Henk) Sneevliet, 9 Mei 1914 di Surabaya telah melakukan upaya kudeta terhadap pemerintahan yang sah setidaknya sebanyak tiga kali. Upaya pemberontakan itu dilakukan untuk mewujudkan revolusi kelas sebagai metode perjuangan untuk mencapai kesetaraan kelas (comunnity) berdasarkan kepemilikan bersama sesuai dengan ajaran Karl Marx.
Pemberontakan pertama PKI terjadi pada tanggal 3 Juli 1946 terhadap pemerintahan Perdana Menteri Soetan Sahrir.Kedua, terjadi pada tanggal 19 September 1948 di Madiun, Jawa Timur yang dipimpin Moeso dan yang terakhir pada tanggal 30 September 1965 yang dikomandoi oleh Letkol Untung.
Berdasarkan literatur sejarah, jumlah korban pemberontakan PKI tahun 1946 itu mencapai ratusan jiwa yang melayang. Sementara pemberontakan PKI tahun 1948 pada era pemerintahan Muhammad Hatta tercatat 17 tokoh yang diculik dan sekitar 1920 jiwa melayang. Puncaknya adalah peristiwa G 30 S PKI, terlepas dari tudingan jika sejarah itu ‘plintiran’ rezim Orde Baru, tetapi faktanya ratusan ribu jiwa melayang. Bahkan banyak literatur yang menyebut jika peristiwa itu telah memakan korban jutaan jiwa seperti revolusi hijau Mao Ze Dong dan revolusi Tsar di Rusia.
Meski telah beberapa kali PKI berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah, tetapi karena alasan strategis untuk membendung kapitalisme dan imperalisme, Bung Karno berusaha untuk membentuk persekutuan ideologi yaitu Nasakom (Nasionalis, Agamis dan Komunis). Eksperimen ideologi yang terilhami oleh Kamarakan Gandhi di India itu akhirnya gagal pasca terjadinya peristiwa G 30 S PKI. Bahkan setelah Bung Karno lengser dan digantikan oleh Soeharto, terbit tap MPR No XXV tahun 1996 yang berisi tentang pembubaran PKI serta menyatakan jika partai berlambang palu arit itu sebagai organisasi terlarang.
Namun karena alasan kemanusiaan, semua elemen bangsa telah sepakat untuk melakukan rekonsiliasi, salah satunya adalah penghapusan kode-kode tertentu di KTP sebagai keluarga eks Tapol maupun anggota PKI. Tidak pernah ada gagasan untuk mengusir mereka agar menjadi warga negara-negara Komunis. Ketika ada orang yang mengklaim bangga menjadi anak eks PKI, publik juga berusaha memaklumi dan berusaha memahami, tidak mungkin dia terpapar faham Komunis, karena saat itu masih berusia Balita.
Saat ini publik tengah dihebohkan dengan wacana repatriasi sekitar 600 jiwa eks combatan ISIS (Islami State of Irak and Syiria). Organisasi teroris ini didirikan oleh Abu Bakr Al Baghdadi, April 2013. Meski memiliki pola perjuangan yang mirip, namun organisasi bentukan arek Samara ini tidak memiliki hubungan ideologis maupun organisatoris dengan Al Qaeda pimpinan Ayman Al Zawahiri. Sehingga beberapa teror seperti peristiwa serangan terhadap WTC 11 September 2001, peristiwa Bom Bali 1 dan 2 tidak ada hubungannya dengan kelompok ini. Dalam kasus terorisme di Indonesia, ada beberapa teror yang diklaim berafilisai terhadap ISIS, seperti Bom Surabaya, Bom Medan serta penyerangan terhadap Menkopolhukam Wiranto.
Uniknya jiwa ‘petualangan’ Al Baghdadi semakin menggelegak setelah keluar dari Camp Bucca, lembaga pemasyarakatan yang dikelola oleh militer AS di Iraq. Bahkan berdasarkan pengakuan Edward Snoden, mantan pegawai Badan Keamanan Amerika (NSA) seperti yang dikutip oleh Gulf Daily News Amerika terlibat dalam proses ‘pembentukan’ ISIS. Pengakuan serupa juga diberikan oleh salah seorang perwira militer AS, Patrick Skyner. Keterangan Snoden maupun Skyner itu membuktikan jika AS yang memiliki perangkat dan teknologi yang canggih itu terbukti gagal dalam mendeteksi sekaligus melakukan proses deradikalisasi terhadap Baghdadi.
Terlepas dari proses pembentukan ISIS itu, organisasi yang berbasis di Syiria inilah yang telah berhasil memperdaya 600 WNI. Bila kita meminjam data Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mayoritas mereka adalah wanita dan anak-anak. Maka bila menggunakan analogi yang sama, kemungkinan mereka (wanita dan anak-anak) itu terpapar radikalisme sangat kecil. Kepergian mereka untuk bergabung dengan ISIS, selain karena iming-iming gaji yang besar yang tidak mungkin diperoleh di Indonesia, mereka juga diperdaya dengan propaganda ideologi yang terbukti tidak sesuai dengan syariah Islam yang sesungguhnya. Hal itu terbukti dari pengakuan beberapa mantan combatan yang berhasil pulang ke Indonesia.
Artinya mereka datang dengan bekal informasi yang sangat minim. Pertanyaaanya kedunguan mereka itu salah siapa ?. Ini adalah kesalahan kolektiv, kesalahan Ormas-ormas agama yang gagal memberikan pengetahuan yang memadai sekaligus adalah kegagalan negara dalam memberikan pendidikan serta memberikan penghidupan yang layak. Maka pantaskah kalau kita saat ini mau cuci tangan terhadap persoalan nasib anak bangsa yang terkatung-katung itu dengan menolak kepulangan mereka.
Bila argumentasinya, mereka itu adalah warga yang memiliki satus hilang kewarga negaraanya (stateless) seperti yang dimaksud Bab IV UU Nomor 12 Tahun 2006, butir A, dan B yang menyatakan jika status kewarga negaraanya hilang karena telah dengan suka rela memilih kewarga negara lain, maka apa bedanya mereka dengan orang-orang yang telah membaiat diri sebagai warga Sunda Empire dan Kerajaan Agung Sejagat ?.
Maka perlu pikiran yang jernih dan fair dalam menyikapi nasib para WNI yang saat ini terkatung-katung karena kedunguan mereka sendiri. Bila Soekarno berniat menggabungkan semua elemen bangsa untuk membendung kapitalisme dan imperialisme, apakah kini karena alasan demi untuk kenyamanan investasi (kapitalisme) kita justru mau mengusir warga yang bodoh itu. Apalagi mayoritas mereka adalah wanita dan anak-anak.
Menerima mereka memang memiliki resiko yang besar, karena berpotensi menumbuh sumburkan radikalisme. Maka disinilah pentingnya proses profiling, terhadap setiap warga negara itu. Apabila ada sosok yang sudah terpapar secara akut, maka orang tersebut layak untuk diisolasi untuk dilakukan proses deradikalisasi atau bila sudah terbukti melakukan sejumlah kejahatan bisa diadili melalui proses peradilan bersama antara pemerintah dengan PBB melalui mekanisme peradilan hybrid. Apalagi kita telah memiliki perangkat yang cukup untuk melakukan deradikalisasi melalui BNPT yang bisa menjalin kerjasama dengan semua stake houlder seperti BIN dan kepolisian.
Penanganan kasus ini bila tidak hati-hati hanya akan melahirkan stigma baru, bahwa pemerintah terasa berat sebelah. ***
Karena alasan ideologi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang didirikan oleh Hendricus JFM (Henk) Sneevliet, 9 Mei 1914 di Surabaya telah melakukan upaya kudeta terhadap pemerintahan yang sah setidaknya sebanyak tiga kali. Upaya pemberontakan itu dilakukan untuk mewujudkan revolusi kelas sebagai metode perjuangan untuk mencapai kesetaraan kelas (comunnity) berdasarkan kepemilikan bersama sesuai dengan ajaran Karl Marx.
Pemberontakan pertama PKI terjadi pada tanggal 3 Juli 1946 terhadap pemerintahan Perdana Menteri Soetan Sahrir.Kedua, terjadi pada tanggal 19 September 1948 di Madiun, Jawa Timur yang dipimpin Moeso dan yang terakhir pada tanggal 30 September 1965 yang dikomandoi oleh Letkol Untung.
Berdasarkan literatur sejarah, jumlah korban pemberontakan PKI tahun 1946 itu mencapai ratusan jiwa yang melayang. Sementara pemberontakan PKI tahun 1948 pada era pemerintahan Muhammad Hatta tercatat 17 tokoh yang diculik dan sekitar 1920 jiwa melayang. Puncaknya adalah peristiwa G 30 S PKI, terlepas dari tudingan jika sejarah itu ‘plintiran’ rezim Orde Baru, tetapi faktanya ratusan ribu jiwa melayang. Bahkan banyak literatur yang menyebut jika peristiwa itu telah memakan korban jutaan jiwa seperti revolusi hijau Mao Ze Dong dan revolusi Tsar di Rusia.
Meski telah beberapa kali PKI berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah, tetapi karena alasan strategis untuk membendung kapitalisme dan imperalisme, Bung Karno berusaha untuk membentuk persekutuan ideologi yaitu Nasakom (Nasionalis, Agamis dan Komunis). Eksperimen ideologi yang terilhami oleh Kamarakan Gandhi di India itu akhirnya gagal pasca terjadinya peristiwa G 30 S PKI. Bahkan setelah Bung Karno lengser dan digantikan oleh Soeharto, terbit tap MPR No XXV tahun 1996 yang berisi tentang pembubaran PKI serta menyatakan jika partai berlambang palu arit itu sebagai organisasi terlarang.
Namun karena alasan kemanusiaan, semua elemen bangsa telah sepakat untuk melakukan rekonsiliasi, salah satunya adalah penghapusan kode-kode tertentu di KTP sebagai keluarga eks Tapol maupun anggota PKI. Tidak pernah ada gagasan untuk mengusir mereka agar menjadi warga negara-negara Komunis. Ketika ada orang yang mengklaim bangga menjadi anak eks PKI, publik juga berusaha memaklumi dan berusaha memahami, tidak mungkin dia terpapar faham Komunis, karena saat itu masih berusia Balita.
Saat ini publik tengah dihebohkan dengan wacana repatriasi sekitar 600 jiwa eks combatan ISIS (Islami State of Irak and Syiria). Organisasi teroris ini didirikan oleh Abu Bakr Al Baghdadi, April 2013. Meski memiliki pola perjuangan yang mirip, namun organisasi bentukan arek Samara ini tidak memiliki hubungan ideologis maupun organisatoris dengan Al Qaeda pimpinan Ayman Al Zawahiri. Sehingga beberapa teror seperti peristiwa serangan terhadap WTC 11 September 2001, peristiwa Bom Bali 1 dan 2 tidak ada hubungannya dengan kelompok ini. Dalam kasus terorisme di Indonesia, ada beberapa teror yang diklaim berafilisai terhadap ISIS, seperti Bom Surabaya, Bom Medan serta penyerangan terhadap Menkopolhukam Wiranto.
Uniknya jiwa ‘petualangan’ Al Baghdadi semakin menggelegak setelah keluar dari Camp Bucca, lembaga pemasyarakatan yang dikelola oleh militer AS di Iraq. Bahkan berdasarkan pengakuan Edward Snoden, mantan pegawai Badan Keamanan Amerika (NSA) seperti yang dikutip oleh Gulf Daily News Amerika terlibat dalam proses ‘pembentukan’ ISIS. Pengakuan serupa juga diberikan oleh salah seorang perwira militer AS, Patrick Skyner. Keterangan Snoden maupun Skyner itu membuktikan jika AS yang memiliki perangkat dan teknologi yang canggih itu terbukti gagal dalam mendeteksi sekaligus melakukan proses deradikalisasi terhadap Baghdadi.
Terlepas dari proses pembentukan ISIS itu, organisasi yang berbasis di Syiria inilah yang telah berhasil memperdaya 600 WNI. Bila kita meminjam data Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mayoritas mereka adalah wanita dan anak-anak. Maka bila menggunakan analogi yang sama, kemungkinan mereka (wanita dan anak-anak) itu terpapar radikalisme sangat kecil. Kepergian mereka untuk bergabung dengan ISIS, selain karena iming-iming gaji yang besar yang tidak mungkin diperoleh di Indonesia, mereka juga diperdaya dengan propaganda ideologi yang terbukti tidak sesuai dengan syariah Islam yang sesungguhnya. Hal itu terbukti dari pengakuan beberapa mantan combatan yang berhasil pulang ke Indonesia.
Artinya mereka datang dengan bekal informasi yang sangat minim. Pertanyaaanya kedunguan mereka itu salah siapa ?. Ini adalah kesalahan kolektiv, kesalahan Ormas-ormas agama yang gagal memberikan pengetahuan yang memadai sekaligus adalah kegagalan negara dalam memberikan pendidikan serta memberikan penghidupan yang layak. Maka pantaskah kalau kita saat ini mau cuci tangan terhadap persoalan nasib anak bangsa yang terkatung-katung itu dengan menolak kepulangan mereka.
Bila argumentasinya, mereka itu adalah warga yang memiliki satus hilang kewarga negaraanya (stateless) seperti yang dimaksud Bab IV UU Nomor 12 Tahun 2006, butir A, dan B yang menyatakan jika status kewarga negaraanya hilang karena telah dengan suka rela memilih kewarga negara lain, maka apa bedanya mereka dengan orang-orang yang telah membaiat diri sebagai warga Sunda Empire dan Kerajaan Agung Sejagat ?.
Maka perlu pikiran yang jernih dan fair dalam menyikapi nasib para WNI yang saat ini terkatung-katung karena kedunguan mereka sendiri. Bila Soekarno berniat menggabungkan semua elemen bangsa untuk membendung kapitalisme dan imperialisme, apakah kini karena alasan demi untuk kenyamanan investasi (kapitalisme) kita justru mau mengusir warga yang bodoh itu. Apalagi mayoritas mereka adalah wanita dan anak-anak.
Menerima mereka memang memiliki resiko yang besar, karena berpotensi menumbuh sumburkan radikalisme. Maka disinilah pentingnya proses profiling, terhadap setiap warga negara itu. Apabila ada sosok yang sudah terpapar secara akut, maka orang tersebut layak untuk diisolasi untuk dilakukan proses deradikalisasi atau bila sudah terbukti melakukan sejumlah kejahatan bisa diadili melalui proses peradilan bersama antara pemerintah dengan PBB melalui mekanisme peradilan hybrid. Apalagi kita telah memiliki perangkat yang cukup untuk melakukan deradikalisasi melalui BNPT yang bisa menjalin kerjasama dengan semua stake houlder seperti BIN dan kepolisian.
Penanganan kasus ini bila tidak hati-hati hanya akan melahirkan stigma baru, bahwa pemerintah terasa berat sebelah. ***