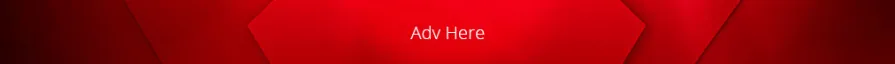Demokrasi Yang Bikin Otak Butek

Oleh : Gugus Elmo Ra’is
Menurut Plato dan Aristoteles, demokrasi adalah bentuk negara yang paling ideal. Secara etimologis, demokrasi berasal dari terminologi bahasa Yunani, demokratia yang terdiri dari suku kata demos (rakyat) serta cratos (kekuatan). Sehingga Karl Raymond Propper dan Mc Ivir memberikan deskripsi, jika demokrasi adalah bentuk negara yang mengikut sertakan (memberi kekuatan) rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Ketika era kerajaan Yunani, rakyat terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan negara, kondisi saat itu masih memungkinkan karena jumlah penduduk yang relatif sedikit. Sebuah negara hanya merupakan sebuah koloni (negara kota) yang tidak terlalu besar.
Demokrasi yang sehat sangat ditentukan oleh civil society yang kuat. Masyarakat madani atau civil society, adalah masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan serta penguasaan informasi yang memadai sebagai bahan referensi dalam menentukan sikap dan pilihan. Seperti halnya tesis, filsuf Francis Bacon yang menyatakan jika knowledge is power (pengetahuan adalah sumber kekuatan), pengetahuan itulah yang menjadi guiden (panduan) dalam menentukan sikap dan pilihan. Penentuan sikap dan pilihan itu bukan didasari oleh sikap latah (ikut-ikutan) dan gumunan (gampang heran).
Bila struktur masyarakat masih didominasi oleh masyarakat awam dengan low basic education (pendidikan yang rendah), tak akan mengherankan bila demokrasi akan menghasilkan pemimpin yang tidak visioner. Karena ketidak mampuan masyarakat dalam mengintreprestasikan misi, visi calon pemimpinnya selama masa kampanye. Referensi utama yang digunakan oleh masyarakat awam biasanya hanya ditentukan oleh isu-isu sektarian atau sikap gumunan terhadap popularitas dan proses pencitraan yang dilakukan oleh sang calon. Atau dalam bahasa sederhana, dalam demokrasi, orang bodoh bisa mengalahkan orang pintar bila jumlah orang bodohnya jauh lebih banyak. Maka tak mengherankan bila Soekarno cenderung menghindari pemilihan langsung yang menjadi ciri dari demokrasi liberal.
Maka disinilah peran sentral sekaligus tanggung jawab moral dari para politisi untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, minimal terhadap para konstituennya untuk menciptakan demokrasi yang beradab dan bermartabat. Karena secara empiris, kita yang baru menjalankan demokrasi selama 22 tahun ini masih pada tingkat yang sangat memperihatinkan. Demokrasi diintreprestasi dengan cara yang salah dan sering menciptakan kegaduhan yang tidak subtansial.
Kebebasan berbicara yang merupakan qonditio sine qua non (prasyarat utama demokrasi), dan dijamin oleh konstitusi sesuai pasal 28 UUD 1945 serta Pasal 19 Konvenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), faktanya masih dipergunakan secara serampangan dan ugal-ugalan. Atas nama demokrasi masih banyak orang yang bersikap waton bedo (asal beda) dan pating pecotot (asal bicara dan asal serang) yang pada gilirannya justru hanya menciptakan kegaduhan. Tidak banyak orang yang mampu berpendapat secara argumentatif, sebagai bagian untuk mengkritisi kebijakan sekaligus memberikan konklusi, seperti halnya tesis Karl Raymond Proppers (properian) jika kritik merupakan bagian dari tentatif solutions.
Lebih tragis lagi, demokrasi baru dimaknai sebatas sebagai sarana struggle of power (alat untuk mencapai pusat kekuasaan). Kondisi inilah yang membuat banyak pihak melakukan segala cara untuk memenangkan kompetisi untuk menuju pusat kekuasaan. Mulai dari melakukan black campaign (kampanye hitam) hingga menyebar hoaxs yang dimaksudkan untuk mendiskreditkan lawan sekaligus melakukan character assasination (pembunuhan karakter lawan), dengan harapan untuk menghancurkan elektabilitas lawan. Seakan para pihak lupa dengan seloka Jawa yang agung dalam menjalani kompetisi politik, ngalahake tanpo ngasorake (mengalahkan tanpa mempermalukan lawan).
Fase ini tanpa sadar merupakan fase yang krusial dalam proses menanam dendam politik terhadap para pihak. Karena para konstituen seringkali bersikap Baper, terhadap isu-isu yang dilontarkan oleh pihak lawan. Dan tanaman dendam itu akan dituai pasca pemilihan. Banyak pihak yang galon alias gagal move on, setelah jagoannya kalah dalam palagan dan pertarungan politik. Di sinilah, biasanya mereka terjangkit butek otaknya atau tidak mampu berpikir jernih setiap menyikapi dinamika sosial dan politik yang terjadi di masyarakat.
Dampaknya adalah muncul sikap apatis dan nyinyir terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin yang terpilih, baik di level Piplres, Pileg hingga Pilkada. Maka tak mengherankan bila saat ini muncul fenomena nyinyirisme, semua yang dilakukan oleh Presiden, Gubernur atau Bupati selalu dianggap ga bener oleh massa pendukung calon yang pernah kalah. Sehingga esensi demokrasi sebagai sarana untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan sekaligus untuk melakukan kritik terhadap kebijakan, justru menjadi ajang untuk saling ejek terhadap lawan politiknya.
Mereka seakan lupa jika sesuai dengan mekanisme demokrasi setiap kebijakan seperti APBN/APBD dan RJPM dst itu secara garis besar merupakan hasil keputusan bersama (kolektif) saat proses pembahasan baik di DPR maupun DPRD, dengan melibatkan wakil-wakil mereka di parlemen. Mungkin yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah mengawasi dan memberikan masukan. Dan bukan mengatakan pemimpinnya bodoh, hal-hal yang seperti itulah merupakan bentuk demokrasi yang tidak beradab. Sementara dia sendiri tidak bisa memberikan solusi alternatif yang memadai.***
Menurut Plato dan Aristoteles, demokrasi adalah bentuk negara yang paling ideal. Secara etimologis, demokrasi berasal dari terminologi bahasa Yunani, demokratia yang terdiri dari suku kata demos (rakyat) serta cratos (kekuatan). Sehingga Karl Raymond Propper dan Mc Ivir memberikan deskripsi, jika demokrasi adalah bentuk negara yang mengikut sertakan (memberi kekuatan) rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Ketika era kerajaan Yunani, rakyat terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan negara, kondisi saat itu masih memungkinkan karena jumlah penduduk yang relatif sedikit. Sebuah negara hanya merupakan sebuah koloni (negara kota) yang tidak terlalu besar.
Demokrasi yang sehat sangat ditentukan oleh civil society yang kuat. Masyarakat madani atau civil society, adalah masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan serta penguasaan informasi yang memadai sebagai bahan referensi dalam menentukan sikap dan pilihan. Seperti halnya tesis, filsuf Francis Bacon yang menyatakan jika knowledge is power (pengetahuan adalah sumber kekuatan), pengetahuan itulah yang menjadi guiden (panduan) dalam menentukan sikap dan pilihan. Penentuan sikap dan pilihan itu bukan didasari oleh sikap latah (ikut-ikutan) dan gumunan (gampang heran).
Bila struktur masyarakat masih didominasi oleh masyarakat awam dengan low basic education (pendidikan yang rendah), tak akan mengherankan bila demokrasi akan menghasilkan pemimpin yang tidak visioner. Karena ketidak mampuan masyarakat dalam mengintreprestasikan misi, visi calon pemimpinnya selama masa kampanye. Referensi utama yang digunakan oleh masyarakat awam biasanya hanya ditentukan oleh isu-isu sektarian atau sikap gumunan terhadap popularitas dan proses pencitraan yang dilakukan oleh sang calon. Atau dalam bahasa sederhana, dalam demokrasi, orang bodoh bisa mengalahkan orang pintar bila jumlah orang bodohnya jauh lebih banyak. Maka tak mengherankan bila Soekarno cenderung menghindari pemilihan langsung yang menjadi ciri dari demokrasi liberal.
Maka disinilah peran sentral sekaligus tanggung jawab moral dari para politisi untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, minimal terhadap para konstituennya untuk menciptakan demokrasi yang beradab dan bermartabat. Karena secara empiris, kita yang baru menjalankan demokrasi selama 22 tahun ini masih pada tingkat yang sangat memperihatinkan. Demokrasi diintreprestasi dengan cara yang salah dan sering menciptakan kegaduhan yang tidak subtansial.
Kebebasan berbicara yang merupakan qonditio sine qua non (prasyarat utama demokrasi), dan dijamin oleh konstitusi sesuai pasal 28 UUD 1945 serta Pasal 19 Konvenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), faktanya masih dipergunakan secara serampangan dan ugal-ugalan. Atas nama demokrasi masih banyak orang yang bersikap waton bedo (asal beda) dan pating pecotot (asal bicara dan asal serang) yang pada gilirannya justru hanya menciptakan kegaduhan. Tidak banyak orang yang mampu berpendapat secara argumentatif, sebagai bagian untuk mengkritisi kebijakan sekaligus memberikan konklusi, seperti halnya tesis Karl Raymond Proppers (properian) jika kritik merupakan bagian dari tentatif solutions.
Lebih tragis lagi, demokrasi baru dimaknai sebatas sebagai sarana struggle of power (alat untuk mencapai pusat kekuasaan). Kondisi inilah yang membuat banyak pihak melakukan segala cara untuk memenangkan kompetisi untuk menuju pusat kekuasaan. Mulai dari melakukan black campaign (kampanye hitam) hingga menyebar hoaxs yang dimaksudkan untuk mendiskreditkan lawan sekaligus melakukan character assasination (pembunuhan karakter lawan), dengan harapan untuk menghancurkan elektabilitas lawan. Seakan para pihak lupa dengan seloka Jawa yang agung dalam menjalani kompetisi politik, ngalahake tanpo ngasorake (mengalahkan tanpa mempermalukan lawan).
Fase ini tanpa sadar merupakan fase yang krusial dalam proses menanam dendam politik terhadap para pihak. Karena para konstituen seringkali bersikap Baper, terhadap isu-isu yang dilontarkan oleh pihak lawan. Dan tanaman dendam itu akan dituai pasca pemilihan. Banyak pihak yang galon alias gagal move on, setelah jagoannya kalah dalam palagan dan pertarungan politik. Di sinilah, biasanya mereka terjangkit butek otaknya atau tidak mampu berpikir jernih setiap menyikapi dinamika sosial dan politik yang terjadi di masyarakat.
Dampaknya adalah muncul sikap apatis dan nyinyir terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin yang terpilih, baik di level Piplres, Pileg hingga Pilkada. Maka tak mengherankan bila saat ini muncul fenomena nyinyirisme, semua yang dilakukan oleh Presiden, Gubernur atau Bupati selalu dianggap ga bener oleh massa pendukung calon yang pernah kalah. Sehingga esensi demokrasi sebagai sarana untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan sekaligus untuk melakukan kritik terhadap kebijakan, justru menjadi ajang untuk saling ejek terhadap lawan politiknya.
Mereka seakan lupa jika sesuai dengan mekanisme demokrasi setiap kebijakan seperti APBN/APBD dan RJPM dst itu secara garis besar merupakan hasil keputusan bersama (kolektif) saat proses pembahasan baik di DPR maupun DPRD, dengan melibatkan wakil-wakil mereka di parlemen. Mungkin yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah mengawasi dan memberikan masukan. Dan bukan mengatakan pemimpinnya bodoh, hal-hal yang seperti itulah merupakan bentuk demokrasi yang tidak beradab. Sementara dia sendiri tidak bisa memberikan solusi alternatif yang memadai.***