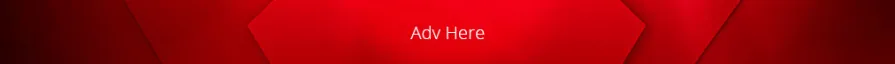Hukum Bukan Perangkat Jebakan

Oleh : Gugus Elmo Ra’is
Manusia sebagai makhluk social (zoon politicon) menurut Aristoteles memerlukan ruang untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan manusia lainnya.
Sebagai makhluk sosial, maka eksistensi manusia sangat tergantung dari manusia lain atau lingkungannya seperti tesis PJ Bouman. Maka di situlah diperlukan norma untuk mengatur pola relasi (muamalah) antara satu individu dengan individu lainnya.
Sehingga menurut John Austin diperlukan norma hukum sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban sekaligus memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi semua elemen masyarakat.
Norma hukum itu menurut filsuf asal Austria, Hans Klesen bersifat mengikat dan seharusnya dilakukan (das solen) terhadap setiap individu yang merupakan antithesis dari teori David Hume, das sein (pada kenyataannya).
Dengan hipotesa seperti itu maka setiap individu atau elemen yang ada di masyarakat harus mengetahui norma-norma yang berasal dari konvensi di masyarakat sebagai norma hukum yang harus ditaati.
Norma itu berupa larangan-larangan serta berbagai ancaman sanksi bagi setiap individu atau kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan itu dalam bentuk peraturan yang tertulis (lex serta, lex scripta) dalam KUHP maupun KUHPer.
Sehingga ketertiban itu muncul sebagai ekspresi kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang dimilikinya. Setiap upaya penengakkan supremasi merupakan
tindakan aparat hukum terhadap individu yang sengaja (dolus) maupun lalai (culpa) berbuat sesuatu yang melanggar hukum.
Bukan karena terjebak oleh ketidak tahuan tentang norma hukum yang ada. Maka pengetahuan dan pemahaman setiap individu terhadap norma - norma hukum itu menjadi sangat penting, sehingga tercipta kesadaran hukum dari setiap individu yang mencerminkan tingkat peradaban suatu bangsa. Dengan konsideran itulah, maka fiksi hukum yang menganggap semua orangtahu hukum (persumptio iures de iure) menjadi kurang relevan.
Sehingga permis dalam bahasa Latin yang menyatakan jika ketidak tahuan hukum adalah hal yang tidak termaafkan (ignorantia jurist non excusat), adalah permis yang represif. Karena negara mendapat mandat untuk menghukum individu yang berbuat kesalahan tanpa tahu bahwa yang dilakukan adalah sebuah perbuatan yang melanggar hukum.
Sehingga rezim apapun tidak bisa sembunyi dibalik fiksi hukum itu. Bagaimanapun setiap muncul norma hukum baru, maka setiap rezim memiliki tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, sehingga tidak mengalami gagal paham.
Munculnya aksi demo massif yang menolak proses revisi UU KPK dan revisi UU KUHP beberapa waktu lalu adalah bukti empiris jika minimnya sosialisasi membuat publik banyak yang gagal paham tentang proses pembahasan norma hukum baru dalam bentuk RUU KPK serta RUU KUHP. Dan terbukti jika social cost yang ditimbulkan sangat mahal.
Bahkan social cost itu sempat mengakibatkan kegiatan ekonomi mengalami stag yang jika dikalkulasi (breakdown) biayanya jauh lebih besar dari pada biaya untuk sosialisasi.
Dan yang terpenting adalah, masyarakat seharusnya tahu setiap UU yang berlaku (ius costitutum) dan yang akan berlaku (ius costituendum) yang bisa dijadikan sebagai guiden (panduan) dalam menjalani hidup berbangsa dan bernegara sekaligus sebagai upaya untuk patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku.
Karena sebagai negara hukum (rechstaats), norma hukum itu bisa menjadi standar moral bangsa. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum itu bisa menjadi realitas yang paradoks, bagaimana bangsa ini bisa taat hukum bila pengetahuan hukumnya masih sangat minim. Jangankan untuk bisa memahami sekitar 600 UU yang dimiliki bangsa ini, untuk tahu dan paham tentang satu UU seperti UU KPK dan
UU KUHP saja masih banyak yang tidak paham.
Sebagai catatan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), DPR setiap tahun memasang target sekitar 200 UU, maka bisa dibayangkan jika hukum di Indonesia baru bisa dimaknai sebagai perangkat jebakan ketimbang sebagai nilai-nilai yang harus dipahami sekaligus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.***
Manusia sebagai makhluk social (zoon politicon) menurut Aristoteles memerlukan ruang untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan manusia lainnya.
Sebagai makhluk sosial, maka eksistensi manusia sangat tergantung dari manusia lain atau lingkungannya seperti tesis PJ Bouman. Maka di situlah diperlukan norma untuk mengatur pola relasi (muamalah) antara satu individu dengan individu lainnya.
Sehingga menurut John Austin diperlukan norma hukum sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban sekaligus memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi semua elemen masyarakat.
Norma hukum itu menurut filsuf asal Austria, Hans Klesen bersifat mengikat dan seharusnya dilakukan (das solen) terhadap setiap individu yang merupakan antithesis dari teori David Hume, das sein (pada kenyataannya).
Dengan hipotesa seperti itu maka setiap individu atau elemen yang ada di masyarakat harus mengetahui norma-norma yang berasal dari konvensi di masyarakat sebagai norma hukum yang harus ditaati.
Norma itu berupa larangan-larangan serta berbagai ancaman sanksi bagi setiap individu atau kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan itu dalam bentuk peraturan yang tertulis (lex serta, lex scripta) dalam KUHP maupun KUHPer.
Sehingga ketertiban itu muncul sebagai ekspresi kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang dimilikinya. Setiap upaya penengakkan supremasi merupakan
tindakan aparat hukum terhadap individu yang sengaja (dolus) maupun lalai (culpa) berbuat sesuatu yang melanggar hukum.
Bukan karena terjebak oleh ketidak tahuan tentang norma hukum yang ada. Maka pengetahuan dan pemahaman setiap individu terhadap norma - norma hukum itu menjadi sangat penting, sehingga tercipta kesadaran hukum dari setiap individu yang mencerminkan tingkat peradaban suatu bangsa. Dengan konsideran itulah, maka fiksi hukum yang menganggap semua orangtahu hukum (persumptio iures de iure) menjadi kurang relevan.
Sehingga permis dalam bahasa Latin yang menyatakan jika ketidak tahuan hukum adalah hal yang tidak termaafkan (ignorantia jurist non excusat), adalah permis yang represif. Karena negara mendapat mandat untuk menghukum individu yang berbuat kesalahan tanpa tahu bahwa yang dilakukan adalah sebuah perbuatan yang melanggar hukum.
Sehingga rezim apapun tidak bisa sembunyi dibalik fiksi hukum itu. Bagaimanapun setiap muncul norma hukum baru, maka setiap rezim memiliki tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, sehingga tidak mengalami gagal paham.
Munculnya aksi demo massif yang menolak proses revisi UU KPK dan revisi UU KUHP beberapa waktu lalu adalah bukti empiris jika minimnya sosialisasi membuat publik banyak yang gagal paham tentang proses pembahasan norma hukum baru dalam bentuk RUU KPK serta RUU KUHP. Dan terbukti jika social cost yang ditimbulkan sangat mahal.
Bahkan social cost itu sempat mengakibatkan kegiatan ekonomi mengalami stag yang jika dikalkulasi (breakdown) biayanya jauh lebih besar dari pada biaya untuk sosialisasi.
Dan yang terpenting adalah, masyarakat seharusnya tahu setiap UU yang berlaku (ius costitutum) dan yang akan berlaku (ius costituendum) yang bisa dijadikan sebagai guiden (panduan) dalam menjalani hidup berbangsa dan bernegara sekaligus sebagai upaya untuk patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku.
Karena sebagai negara hukum (rechstaats), norma hukum itu bisa menjadi standar moral bangsa. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum itu bisa menjadi realitas yang paradoks, bagaimana bangsa ini bisa taat hukum bila pengetahuan hukumnya masih sangat minim. Jangankan untuk bisa memahami sekitar 600 UU yang dimiliki bangsa ini, untuk tahu dan paham tentang satu UU seperti UU KPK dan
UU KUHP saja masih banyak yang tidak paham.
Sebagai catatan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), DPR setiap tahun memasang target sekitar 200 UU, maka bisa dibayangkan jika hukum di Indonesia baru bisa dimaknai sebagai perangkat jebakan ketimbang sebagai nilai-nilai yang harus dipahami sekaligus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.***