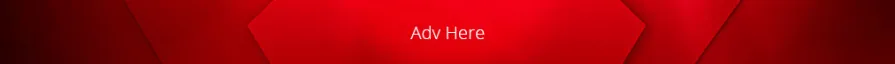Inkonsistensi Kebijakan Menghancurkan Budaya Hukum

Oleh : Gugus Elmo Ra’is
Sudah menjadi pengetahuan umum jika Bangsa Indonesia dikenal memiliki budaya adiluhung, berupa sikap sopan dan ramah tamah. Sikap sopan itu bisa dilihat misalnya dari struktur bahasa yang memiliki tiga tingkatan terutama untuk budaya Jawa yakni, ngoko, kromo, kromo inggil. Struktur bahasa itu digunakan sebagai bentuk penghormatan terhadap status sosial lawan bicara. Budaya bertutur itulah yang menunjukkan jika bangsa ini memiliki perilaku yang sangat sopan. Tetapi juga sudah menjadi rahasia umum jika bangsa ini memiliki tabiat buruk yakni cenderung susah tertib untuk menghormati sekaligus melaksanakan norma-norma hukum yang berdasarkan konsesus yang belum maupun sudah tertulis (lex srta, lex scripta).
Tabiat buruk itu muncul setidaknya ada beberapa faktor diantaranya adalah perilaku buruk dari elit politik yang berkuasa. Dari zaman Kerajaan Majapahit hingga saat ini, setiap terjadi proses suksesi kepemimpinan selalu diikuti dengan budaya tumpas kelor atau kalau kita meminjam tesis professor ekonomi dari Massachusets, Lester C Thurow yang menulis dalam bukunyaThe Zero Society Distribution and Possibility for Economy Change, dengan memberikan terminologi zero zum game, yang mendeskripsikan setiap perubahan kepemimpinan selalu diikuti oleh perubahan kebijakan, perubahan struktur organisasi secara total. Menurut tesis Thurow perilaku ini cenderung menciptakan instabilitas dan inkonsistensi kebijakan.
Maka setiap ada perubahan kepemimpinan ada perubahan kebijakan dan peraturan yang drastis. Contoh paling ekstrem adalah pasca tumbangnya rezim Orde Baru, nyaris semua norma-norma hukum dirombak secara total. Perombakan itu diintrodusir dengan proses amandemen UUD 1945. Tujuan perombakan itu jelas sebagai antitesis terhadap system Orde Baru yang tertutup dan korup, seakan tidak ada warisan Orde Baru yang masih bisa disisakan dan diselamatkan. Namun kini terbukti proses amandemen yang mengakibatkan perubahan norma itu justru melahirkan kompleksitas persoalan. Sehingga menimbulkan kesan jika amandemen itu kebablasan.
Perubahan norma secara drastis dan radikal itulah yang seringkali membuat bangsa ini tidak memiliki norma yang ajeg (tetap dan konsisten) yang membuat bangsa ini menjadi gagap sekaligus mengalami gegar budaya (shock culture). Contoh konkrit adalah tumbuhnya budaya demokrasi yang memiliki prasyarat utama (qonditio sin qua non) dalam bentuk kebebasan berpendapat. Faktanya bangsa Indonesia saat ini mengalami gegar budaya dalam bentuk kebebasan berpendapat yang cenderung kebablasan yang seringkali memincu kontroversi sekaligus menguras energi bangsa ini. Ekspresi kebebasan justru cenderung digunakan untuk melawan pemerintah atau lawan politiknya secara frontal, meski kritik adalah bagian tak terpisahkan dari demokrasi seperti tesisnya Karl Raymond Propper yang lebih kita kenal dengan teori propperian.
Bukti teraktual adanya kebijakan yang flip-flop (berubah-rubah) adalah kebijakan pemerintah, baik pusat dan daerah dalam menangani bencana Covid 19. Antara instansi/departemen maupun antara pemerintah pusat dan daerah tidak pernah seirama. Meski semua pihak itu memiliki konsideran yang sangat rasional dan bisa dipahami sebelum membuat kebijakan, terutama untuk menyikapi perubahan situasi yang sangat dinamis. Tetapi kebijakan yang berubah dan tidak seirama antara instansi itu tetap akan membuat masyarakat bingung, untuk memahami kebijakan itu sebagai guiden (panduan) dalam bersikap.
Kondisi itu yang menunjukkan jika koordinasi dan cara komunikasi pemerintahan ini cukup buruk. Presiden setiap hari mencoba untuk serius menangani berbagai persoalan yang muncul, tetapi para pembantunya tidak bisa menterjemahkan dengan cara bekoordinasi serta berkomunikasi yang baik. Kebijakan yang baik dan terukur itu tidak cukup hanya berbekal niat baik, tetapi harus dibarengi metodologi sekaligus cara menyampaikannya ke masyarakat yang baik pula.
Jadi mustahil, berharap masyarakat itu akan tunduk dan patuh bila peraturan dan kebijakan itu tidak pernah konsisten. Kondisi inilah yang mengakibatkan munculnya kondisi das sein, das sollen (kenyataan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku). Maka tujuan mencipatakan budaya hukum untuk memberi menfaat serta menghadirkan kenyamanan seperti tesisnya Jeremy Bentham tidak akan pernah tercapai. Yang muncul justru kebingunan di masyarakat, dalam skala tertentu bila kondisi tidak segera dirubah justru akan memunculkan fenomena civil disobediens (pembangkangan sipil) dalam bentuk apatisme masyarakat terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah. Meski kebijakan itu berasal dari niat baik untuk menyelematkan jiwa mereka sendiri, (salus populi supreme lex esto).
Maka untuk menyiasati kesenjangan pemahamam antara kebijakan pemerintah dengan rakyat sebagai obyek kebijakan itu, perlu adanya information leadershif yang memiliki fungsi untuk memberikan narasi dari setiap kebijakan pemerintah, sehingga masyarakat bisa paham sekaligus mematuhi kebijakan itu. Dan yang terpenting kebijakan yang baik itu selain berfungsi untuk mengatasi pokok persoalannya seperti adanya bencana, tetapi juga berfungsi untuk mendidik masyarakat menghormati budaya hukum dengan tertib sekaligus menjalankannya.***
Sudah menjadi pengetahuan umum jika Bangsa Indonesia dikenal memiliki budaya adiluhung, berupa sikap sopan dan ramah tamah. Sikap sopan itu bisa dilihat misalnya dari struktur bahasa yang memiliki tiga tingkatan terutama untuk budaya Jawa yakni, ngoko, kromo, kromo inggil. Struktur bahasa itu digunakan sebagai bentuk penghormatan terhadap status sosial lawan bicara. Budaya bertutur itulah yang menunjukkan jika bangsa ini memiliki perilaku yang sangat sopan. Tetapi juga sudah menjadi rahasia umum jika bangsa ini memiliki tabiat buruk yakni cenderung susah tertib untuk menghormati sekaligus melaksanakan norma-norma hukum yang berdasarkan konsesus yang belum maupun sudah tertulis (lex srta, lex scripta).
Tabiat buruk itu muncul setidaknya ada beberapa faktor diantaranya adalah perilaku buruk dari elit politik yang berkuasa. Dari zaman Kerajaan Majapahit hingga saat ini, setiap terjadi proses suksesi kepemimpinan selalu diikuti dengan budaya tumpas kelor atau kalau kita meminjam tesis professor ekonomi dari Massachusets, Lester C Thurow yang menulis dalam bukunyaThe Zero Society Distribution and Possibility for Economy Change, dengan memberikan terminologi zero zum game, yang mendeskripsikan setiap perubahan kepemimpinan selalu diikuti oleh perubahan kebijakan, perubahan struktur organisasi secara total. Menurut tesis Thurow perilaku ini cenderung menciptakan instabilitas dan inkonsistensi kebijakan.
Maka setiap ada perubahan kepemimpinan ada perubahan kebijakan dan peraturan yang drastis. Contoh paling ekstrem adalah pasca tumbangnya rezim Orde Baru, nyaris semua norma-norma hukum dirombak secara total. Perombakan itu diintrodusir dengan proses amandemen UUD 1945. Tujuan perombakan itu jelas sebagai antitesis terhadap system Orde Baru yang tertutup dan korup, seakan tidak ada warisan Orde Baru yang masih bisa disisakan dan diselamatkan. Namun kini terbukti proses amandemen yang mengakibatkan perubahan norma itu justru melahirkan kompleksitas persoalan. Sehingga menimbulkan kesan jika amandemen itu kebablasan.
Perubahan norma secara drastis dan radikal itulah yang seringkali membuat bangsa ini tidak memiliki norma yang ajeg (tetap dan konsisten) yang membuat bangsa ini menjadi gagap sekaligus mengalami gegar budaya (shock culture). Contoh konkrit adalah tumbuhnya budaya demokrasi yang memiliki prasyarat utama (qonditio sin qua non) dalam bentuk kebebasan berpendapat. Faktanya bangsa Indonesia saat ini mengalami gegar budaya dalam bentuk kebebasan berpendapat yang cenderung kebablasan yang seringkali memincu kontroversi sekaligus menguras energi bangsa ini. Ekspresi kebebasan justru cenderung digunakan untuk melawan pemerintah atau lawan politiknya secara frontal, meski kritik adalah bagian tak terpisahkan dari demokrasi seperti tesisnya Karl Raymond Propper yang lebih kita kenal dengan teori propperian.
Bukti teraktual adanya kebijakan yang flip-flop (berubah-rubah) adalah kebijakan pemerintah, baik pusat dan daerah dalam menangani bencana Covid 19. Antara instansi/departemen maupun antara pemerintah pusat dan daerah tidak pernah seirama. Meski semua pihak itu memiliki konsideran yang sangat rasional dan bisa dipahami sebelum membuat kebijakan, terutama untuk menyikapi perubahan situasi yang sangat dinamis. Tetapi kebijakan yang berubah dan tidak seirama antara instansi itu tetap akan membuat masyarakat bingung, untuk memahami kebijakan itu sebagai guiden (panduan) dalam bersikap.
Kondisi itu yang menunjukkan jika koordinasi dan cara komunikasi pemerintahan ini cukup buruk. Presiden setiap hari mencoba untuk serius menangani berbagai persoalan yang muncul, tetapi para pembantunya tidak bisa menterjemahkan dengan cara bekoordinasi serta berkomunikasi yang baik. Kebijakan yang baik dan terukur itu tidak cukup hanya berbekal niat baik, tetapi harus dibarengi metodologi sekaligus cara menyampaikannya ke masyarakat yang baik pula.
Jadi mustahil, berharap masyarakat itu akan tunduk dan patuh bila peraturan dan kebijakan itu tidak pernah konsisten. Kondisi inilah yang mengakibatkan munculnya kondisi das sein, das sollen (kenyataan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku). Maka tujuan mencipatakan budaya hukum untuk memberi menfaat serta menghadirkan kenyamanan seperti tesisnya Jeremy Bentham tidak akan pernah tercapai. Yang muncul justru kebingunan di masyarakat, dalam skala tertentu bila kondisi tidak segera dirubah justru akan memunculkan fenomena civil disobediens (pembangkangan sipil) dalam bentuk apatisme masyarakat terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah. Meski kebijakan itu berasal dari niat baik untuk menyelematkan jiwa mereka sendiri, (salus populi supreme lex esto).
Maka untuk menyiasati kesenjangan pemahamam antara kebijakan pemerintah dengan rakyat sebagai obyek kebijakan itu, perlu adanya information leadershif yang memiliki fungsi untuk memberikan narasi dari setiap kebijakan pemerintah, sehingga masyarakat bisa paham sekaligus mematuhi kebijakan itu. Dan yang terpenting kebijakan yang baik itu selain berfungsi untuk mengatasi pokok persoalannya seperti adanya bencana, tetapi juga berfungsi untuk mendidik masyarakat menghormati budaya hukum dengan tertib sekaligus menjalankannya.***