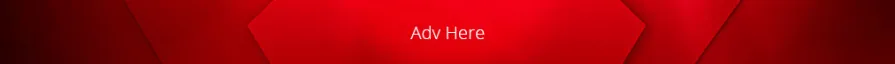Kejujuran Yang Menimbulkan Sinyal Bahaya

Oleh : Gugus Elmo Ra’is
Beberapa waktu lalu, mantan Wagub DKI Jakarta sekaligus mantan Cawapres, dalam Pilpres 2019, Sandiaga Salahudin Uno memberikan pengakuan yang mengejutkan. Dalam dua event politik, Pilkada DKI serta Pilpres 2019 lalu, putra Mien Uno itu telah merogoh kocek yang sangat dalam yakni sekitar Rp 1 triliun. Kejujuran Sandiaga itu harus diapresiasi, dan publik pasti mafhum jika pernyataan itu semata-mata bukan untuk cari sensasi. Karena semua telah tahu dan percaya jika Sandiaga mampu memberikan semua itu karena dia adalah seorang pengusaha yang sukses pemilik emporium bisnis, Saratoga Group.
Tapi kejujuran Sandi itu telah menerbitkan sebait ironi serta memberikan sinyal yang sangat berbahaya terhadap sendi-sendi kehidupan bernegara kita, pasca amandemen UUD 1945. Bahkan kejujuran Sandi itu bisa menjadi bahan perenungan bagi para pakar hukum tata negara dan kita semua untuk merumuskan ulang sistem yang ideal dan kredibel dalam menciptakan good and cleans governance. Karena sistem yang ada justru akan membuat siapapun calonnya tidak akan bisa independen dan terjerat oleh kompromi-kompromi politik yang harus dilakukan. Meski kompromi politik itu tidak semuanya berkonotasi negatif.
Seperti diketahui, setelah beberapa kali amandemen terhadap UUD 1945 telah terjadi proses ‘pemugaran’ bangunan ketata-negaraan secara konsitusional. Salah satunya adalah Pasal 6A UUD 1945, tentang pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Amandemen pasal ini telah ‘menyerobot’ hak konstitusi MPR untuk memilih Capres dan Cawapres seperti yang tersurat Pasal 1 ayat 2 naskah asli UUD 1945. Disaat yang nyaris bersamaan terjadi perubahan sistem kepartaian dari partai dominan (dominant party) menjadi partai majemuk (multy party).
Perubahan sistem itu menjadi pintu gerbang liberalisasi politik yang memberikan dampak high cost politic (politik biaya tinggi) bagi siapapun yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Bila dibreakdown, biaya yang dikeluarkan oleh Sandi dan Prabowo itu pasti merupakan komponen biaya untuk kepentingan teknis Pilpres. Karena hingga saat ini tidak terbukti adanya money politic yang dilakukan oleh pasangan itu atau pasangan lawannya.
Selain biaya kampanye dan mobilisasi massa yang nyaris tak terukur, ada beberapa variable cost (komponen biaya) yang tidak murah. Misalnya untuk memastikan perolehan suara, ada komponen biaya saksi dari sekitar 813.350 TPS yang ada di seluruh Indonesia dalam Pilpres 2019 lalu, dan itu pasti tidak sedikit. Karena hingga saat ini pemerintah belum menyetujui usulan biaya saksi sebesar Rp 3,9 triliun. Artinya, selain persiapan visi, misi, dan ideologi siapapun calon harus memiliki bekal materi yang cukup untuk mendukung pencalonannya. Karena semua biaya itu ditanggung para pihak.
Dengan kriteria yang teramat berat itu tidak semua orang bisa menjadi calon presiden di republik ini, sesuai dengan ketentuan pasal 24 UUD 1945 tentang hak dipilih dan memilih. Kecuali jika para pendukungnya membuat gerakan donasi seperti one man one dollar yang dilakukan oleh timnya Barrack Obama. Atau dia didukung oleh sekelompok orang atau partai yang memiliki dana yang kuat.
Yang menjadi pertanyaan, seandainya Pasangan Prabowo-Sandi terpilih, mungkinkan Sandi yang seorang pengusaha itu bisa berubah total menjadi sosok yang berjiwa filantropis. Dan menganggap apa yang telah dikeluarkan itu sebagai amal belaka. Walau banyak orang yang tahu jika Sandi memiliki jiwa kedermawanan yang tinggi sekaligus memiliki integritas yang tinggi. Atau sebaliknya, bila dia menggunakan paradigma sebagai seorang pengusaha dan menggunakan hukum ekonomi, bagaimana dia akan mengembalikan semua nilai investasi politiknya. Apalagi sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden mereka punya otoritas untuk mengendalikan anggaran negara setidaknya sekitar Rp 2400 triliun/tahun selama lima tahun kepemimpinan mereka.
Persoalan yang tak kalah krusial, adalah terjadinya perubahan sistem kepartaian dari dominan partai menjadi multi partai. Karena sesuai dengan wejangan dari Scot Mainwaring, Jose Chaebub, Adam Przeworzki dan Sebastian M Saiegh, sistem multi partai akan melahirkan minority governance (pemerintahan minoritas) karena perolehan suara yang relatif berimbang. Hal inilah yang akan melahirkan kompleksitas persoalan, terutama dalam proses koalisi untuk membentuk pemerintahan. Karena sesuai dengan tesis Huang Wa, koalisi partai cenderung mengesampingkan kesamaan platform dan memilih demi kepentingan politik praktis semata.
Maka siapapun yang terpilih, akan terjerat dalam kompromi-kompromi politik ketika proses pembentukan koalisi. Dengan konstelasi politik seperti itu ‘hak prerogatif presiden’, selalu terikat tali konsesus bersama selama proses pencalonan. Setidaknya pemimpin yang terpilih akan banyak ‘diganggu’ oleh para pemilik saham politik. Maka tak mengherankan partai selalu cawe-cawe dalam kebijakan meski itu masuk dalam ranah hak prerogative presiden. Walaupun selalu dibungkus dengan bahasa semua dikembalikan ke presiden. Kesimpulannya sistem yang ada sekarang cenderung akan melahirkan pemimpin yang terkesan oligarkis. Maka mengharapkan adanya pemimpin yang kuat seperti tesisnya Shang Yang pasti sulit terwujud.***
Beberapa waktu lalu, mantan Wagub DKI Jakarta sekaligus mantan Cawapres, dalam Pilpres 2019, Sandiaga Salahudin Uno memberikan pengakuan yang mengejutkan. Dalam dua event politik, Pilkada DKI serta Pilpres 2019 lalu, putra Mien Uno itu telah merogoh kocek yang sangat dalam yakni sekitar Rp 1 triliun. Kejujuran Sandiaga itu harus diapresiasi, dan publik pasti mafhum jika pernyataan itu semata-mata bukan untuk cari sensasi. Karena semua telah tahu dan percaya jika Sandiaga mampu memberikan semua itu karena dia adalah seorang pengusaha yang sukses pemilik emporium bisnis, Saratoga Group.
Tapi kejujuran Sandi itu telah menerbitkan sebait ironi serta memberikan sinyal yang sangat berbahaya terhadap sendi-sendi kehidupan bernegara kita, pasca amandemen UUD 1945. Bahkan kejujuran Sandi itu bisa menjadi bahan perenungan bagi para pakar hukum tata negara dan kita semua untuk merumuskan ulang sistem yang ideal dan kredibel dalam menciptakan good and cleans governance. Karena sistem yang ada justru akan membuat siapapun calonnya tidak akan bisa independen dan terjerat oleh kompromi-kompromi politik yang harus dilakukan. Meski kompromi politik itu tidak semuanya berkonotasi negatif.
Seperti diketahui, setelah beberapa kali amandemen terhadap UUD 1945 telah terjadi proses ‘pemugaran’ bangunan ketata-negaraan secara konsitusional. Salah satunya adalah Pasal 6A UUD 1945, tentang pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Amandemen pasal ini telah ‘menyerobot’ hak konstitusi MPR untuk memilih Capres dan Cawapres seperti yang tersurat Pasal 1 ayat 2 naskah asli UUD 1945. Disaat yang nyaris bersamaan terjadi perubahan sistem kepartaian dari partai dominan (dominant party) menjadi partai majemuk (multy party).
Perubahan sistem itu menjadi pintu gerbang liberalisasi politik yang memberikan dampak high cost politic (politik biaya tinggi) bagi siapapun yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Bila dibreakdown, biaya yang dikeluarkan oleh Sandi dan Prabowo itu pasti merupakan komponen biaya untuk kepentingan teknis Pilpres. Karena hingga saat ini tidak terbukti adanya money politic yang dilakukan oleh pasangan itu atau pasangan lawannya.
Selain biaya kampanye dan mobilisasi massa yang nyaris tak terukur, ada beberapa variable cost (komponen biaya) yang tidak murah. Misalnya untuk memastikan perolehan suara, ada komponen biaya saksi dari sekitar 813.350 TPS yang ada di seluruh Indonesia dalam Pilpres 2019 lalu, dan itu pasti tidak sedikit. Karena hingga saat ini pemerintah belum menyetujui usulan biaya saksi sebesar Rp 3,9 triliun. Artinya, selain persiapan visi, misi, dan ideologi siapapun calon harus memiliki bekal materi yang cukup untuk mendukung pencalonannya. Karena semua biaya itu ditanggung para pihak.
Dengan kriteria yang teramat berat itu tidak semua orang bisa menjadi calon presiden di republik ini, sesuai dengan ketentuan pasal 24 UUD 1945 tentang hak dipilih dan memilih. Kecuali jika para pendukungnya membuat gerakan donasi seperti one man one dollar yang dilakukan oleh timnya Barrack Obama. Atau dia didukung oleh sekelompok orang atau partai yang memiliki dana yang kuat.
Yang menjadi pertanyaan, seandainya Pasangan Prabowo-Sandi terpilih, mungkinkan Sandi yang seorang pengusaha itu bisa berubah total menjadi sosok yang berjiwa filantropis. Dan menganggap apa yang telah dikeluarkan itu sebagai amal belaka. Walau banyak orang yang tahu jika Sandi memiliki jiwa kedermawanan yang tinggi sekaligus memiliki integritas yang tinggi. Atau sebaliknya, bila dia menggunakan paradigma sebagai seorang pengusaha dan menggunakan hukum ekonomi, bagaimana dia akan mengembalikan semua nilai investasi politiknya. Apalagi sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden mereka punya otoritas untuk mengendalikan anggaran negara setidaknya sekitar Rp 2400 triliun/tahun selama lima tahun kepemimpinan mereka.
Persoalan yang tak kalah krusial, adalah terjadinya perubahan sistem kepartaian dari dominan partai menjadi multi partai. Karena sesuai dengan wejangan dari Scot Mainwaring, Jose Chaebub, Adam Przeworzki dan Sebastian M Saiegh, sistem multi partai akan melahirkan minority governance (pemerintahan minoritas) karena perolehan suara yang relatif berimbang. Hal inilah yang akan melahirkan kompleksitas persoalan, terutama dalam proses koalisi untuk membentuk pemerintahan. Karena sesuai dengan tesis Huang Wa, koalisi partai cenderung mengesampingkan kesamaan platform dan memilih demi kepentingan politik praktis semata.
Maka siapapun yang terpilih, akan terjerat dalam kompromi-kompromi politik ketika proses pembentukan koalisi. Dengan konstelasi politik seperti itu ‘hak prerogatif presiden’, selalu terikat tali konsesus bersama selama proses pencalonan. Setidaknya pemimpin yang terpilih akan banyak ‘diganggu’ oleh para pemilik saham politik. Maka tak mengherankan partai selalu cawe-cawe dalam kebijakan meski itu masuk dalam ranah hak prerogative presiden. Walaupun selalu dibungkus dengan bahasa semua dikembalikan ke presiden. Kesimpulannya sistem yang ada sekarang cenderung akan melahirkan pemimpin yang terkesan oligarkis. Maka mengharapkan adanya pemimpin yang kuat seperti tesisnya Shang Yang pasti sulit terwujud.***