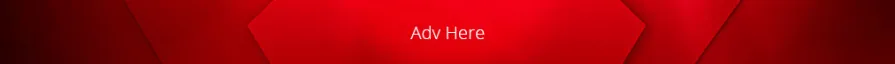Kembali Ke UUD 1945

Ilustrasi
Oleh : Gugus Elmo Ra’is
Dinamika politik yang meningkat secara drastis selama periode (1998-2019) atau yang lebih kita kenal sebagai Orde Reformasi membuat bangsa ini dilanda kegalauan tingkat dewa. Pemerintahan yang sentralistik, totaliter dan tertutup selama Orde Baru memunculkan gagasan amandemen (perubahan UUD 1945) untuk membatasi kekuasaan presiden. Selain pembatasan masa jabatan presiden terjadi perubahan ke tata negaraan yang melahirkan kompleksitas persoalan tersendiri, sehingga menimbulkan persepsi jika proses amandemen yang dilakukan telah kebablasan, sehingga menjerumuskan bangsa ini ke dalam system demokrasi liberal, yang sangat ditakutkan oleh Soekarno.
Pasca amandemen terjadi perubahan pendulum politik yang sangat fundamental dan krusial. Selain pembatasan masa jabatan presiden yang hanya sampai dua periode, kekuasaan bikameral DPR/MPR juga ikut diamputasi. Kedaulatan rakyat yang diagregasikan dalam system parlementer ala John Locke, kini semakin tak berfungsi. Dan fungsi keterwakilan yang diperankan DPR/MPR telah diamputasi secara langsung, karena saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung. Frase bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang, telah ’merampas’ hak DPR/MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Meski konsideran amandemen itu juga tidak terlepas adanya manipulasi kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh para anggota DPR/MPR pada masa lalu yang sering memposisikan diri sebagai sub ordinat kekuasaan, sehingga memunculkan bahasa satire sebagai lembaga ‘tukang stempel’.
Tetapi secara empirik sistem Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung itu telah membelah masyarakat menjadi dua kelompok yang saling berhadapan. Dua kelompok itu terlibat pertikaian secara verbal dan fisik, yang sangat sengit sehingga menimbulkan luka hati yang cukup dalam. Hingga saat ini ‘garis demarkasi’ itu belum benar-benar hilang. Maka bila kondisi itu dibiarkan, wawasan kebangsaan berupa kehendak bersatu masing-masing kelompok seperti yang dideklarkan oleh para pemuda dalam Soempah Pemuda 1928 itu akan menjadi hambar dan akan tergantikan oleh keinginan untuk jalan sendiri-sendiri (disimtegrasi).
Secara filosofis problema yang saat ini dihadapi sebenarnya adalah persoalan yang klasik yang menjadi materi perdebatan antara Soekarno yang memang gandrung dengan konsep manunggaling kawula lan gusti yang bisa diinteprestasi menyatunya antara rakyat jelata dengan pemimpin dengan konsep kebangsaan yang lebih mengedepankan dan menghormati hak-hak individu yang diusung oleh Muh Hatta. Konsep integralistik Soekarno itu dipengaruhi oleh pemikir-pemikir besar seperti Mazzini, Glad Stone, Kamarakand Gandi, Otto Bauer, sehingga memunculkan terminology jika bangsa itu dibangun oleh kehendak bersatu diantara semua elemen yang ada di wilayah itu, (Karl Renan).
Kehendak bersatu diantara semua elemen inilah yang melahirkan semangat nasionalisme sebagai sebuah gagasan imaginer ala Andrew Ernest Gelner, yang bisa disublimasikan dalam bentuk militansi untuk menjaga keutuhan bangsa, kesadaran untuk mengharagai perbedaan. Setiap individu yang memiliki jiwa nasionalisme, akan mampu mengendalikan nafsunya dengan meletakkan kepentingan dan kejayaan bangsa diatas segala-galanya. Bila kita meminjam filsafat Ronggo Warsito lebih dikenal dengan terminology, suro diro jayadiningrat lebur dening pangestuti (setiap individu harus mampu menahan diri demi tercapainya kejayaan bangsa).
Falsafah yang meletakkan kepentingan bangsa diatas segala-galanya itulah yang seharusnya dijaga oleh konstitusi kita. Sehingga sistem ketata negaraan yang ada mampu menciptakan harmoni hubungan antara sesama elemen bangsa dengan jalinan wawasan kebangsaan yang sama. Setidaknya kita bisa belajar dari Turki yang telah memiliki doktrin nasionalisme yang diberikan oleh Mustapa Kemal Attaturk, betapa bangganya ketika disebutkan sebagai Bangsa Turki. Ironisnya, nasionalisme seperti itulah yang kini jarang kita memiliki karena para pemimpin kita cenderung lebih mementingkan diri dan kelompoknya masing-masing.
Sementara, proses amandemen UUD 1945 yang telah dijalankan saat ini cenderung memberi ruang penguatan terhadap hak-hak individu yang sering dikapitalisasi oleh kekuatan-kekuatan korporasi demi untuk kepentingan kelompoknya masing-masing. Dengan mengabaikan potensi terjadinya bencana kebangsaan berupa disintegrasi dan perpecahan. Maka momentum terjadinya perubahan pemerintahan serta pergantian parlemen ini bisa dijadikan bahan renungan, apakah perlu pemimpin yang baru mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD 1945, atau melanjutkan proses amandemen dengan berbagai catatan kritis, sebagai bagian dari upaya antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kehancuran bangsa.***
Dinamika politik yang meningkat secara drastis selama periode (1998-2019) atau yang lebih kita kenal sebagai Orde Reformasi membuat bangsa ini dilanda kegalauan tingkat dewa. Pemerintahan yang sentralistik, totaliter dan tertutup selama Orde Baru memunculkan gagasan amandemen (perubahan UUD 1945) untuk membatasi kekuasaan presiden. Selain pembatasan masa jabatan presiden terjadi perubahan ke tata negaraan yang melahirkan kompleksitas persoalan tersendiri, sehingga menimbulkan persepsi jika proses amandemen yang dilakukan telah kebablasan, sehingga menjerumuskan bangsa ini ke dalam system demokrasi liberal, yang sangat ditakutkan oleh Soekarno.
Pasca amandemen terjadi perubahan pendulum politik yang sangat fundamental dan krusial. Selain pembatasan masa jabatan presiden yang hanya sampai dua periode, kekuasaan bikameral DPR/MPR juga ikut diamputasi. Kedaulatan rakyat yang diagregasikan dalam system parlementer ala John Locke, kini semakin tak berfungsi. Dan fungsi keterwakilan yang diperankan DPR/MPR telah diamputasi secara langsung, karena saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung. Frase bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang, telah ’merampas’ hak DPR/MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Meski konsideran amandemen itu juga tidak terlepas adanya manipulasi kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh para anggota DPR/MPR pada masa lalu yang sering memposisikan diri sebagai sub ordinat kekuasaan, sehingga memunculkan bahasa satire sebagai lembaga ‘tukang stempel’.
Tetapi secara empirik sistem Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung itu telah membelah masyarakat menjadi dua kelompok yang saling berhadapan. Dua kelompok itu terlibat pertikaian secara verbal dan fisik, yang sangat sengit sehingga menimbulkan luka hati yang cukup dalam. Hingga saat ini ‘garis demarkasi’ itu belum benar-benar hilang. Maka bila kondisi itu dibiarkan, wawasan kebangsaan berupa kehendak bersatu masing-masing kelompok seperti yang dideklarkan oleh para pemuda dalam Soempah Pemuda 1928 itu akan menjadi hambar dan akan tergantikan oleh keinginan untuk jalan sendiri-sendiri (disimtegrasi).
Secara filosofis problema yang saat ini dihadapi sebenarnya adalah persoalan yang klasik yang menjadi materi perdebatan antara Soekarno yang memang gandrung dengan konsep manunggaling kawula lan gusti yang bisa diinteprestasi menyatunya antara rakyat jelata dengan pemimpin dengan konsep kebangsaan yang lebih mengedepankan dan menghormati hak-hak individu yang diusung oleh Muh Hatta. Konsep integralistik Soekarno itu dipengaruhi oleh pemikir-pemikir besar seperti Mazzini, Glad Stone, Kamarakand Gandi, Otto Bauer, sehingga memunculkan terminology jika bangsa itu dibangun oleh kehendak bersatu diantara semua elemen yang ada di wilayah itu, (Karl Renan).
Kehendak bersatu diantara semua elemen inilah yang melahirkan semangat nasionalisme sebagai sebuah gagasan imaginer ala Andrew Ernest Gelner, yang bisa disublimasikan dalam bentuk militansi untuk menjaga keutuhan bangsa, kesadaran untuk mengharagai perbedaan. Setiap individu yang memiliki jiwa nasionalisme, akan mampu mengendalikan nafsunya dengan meletakkan kepentingan dan kejayaan bangsa diatas segala-galanya. Bila kita meminjam filsafat Ronggo Warsito lebih dikenal dengan terminology, suro diro jayadiningrat lebur dening pangestuti (setiap individu harus mampu menahan diri demi tercapainya kejayaan bangsa).
Falsafah yang meletakkan kepentingan bangsa diatas segala-galanya itulah yang seharusnya dijaga oleh konstitusi kita. Sehingga sistem ketata negaraan yang ada mampu menciptakan harmoni hubungan antara sesama elemen bangsa dengan jalinan wawasan kebangsaan yang sama. Setidaknya kita bisa belajar dari Turki yang telah memiliki doktrin nasionalisme yang diberikan oleh Mustapa Kemal Attaturk, betapa bangganya ketika disebutkan sebagai Bangsa Turki. Ironisnya, nasionalisme seperti itulah yang kini jarang kita memiliki karena para pemimpin kita cenderung lebih mementingkan diri dan kelompoknya masing-masing.
Sementara, proses amandemen UUD 1945 yang telah dijalankan saat ini cenderung memberi ruang penguatan terhadap hak-hak individu yang sering dikapitalisasi oleh kekuatan-kekuatan korporasi demi untuk kepentingan kelompoknya masing-masing. Dengan mengabaikan potensi terjadinya bencana kebangsaan berupa disintegrasi dan perpecahan. Maka momentum terjadinya perubahan pemerintahan serta pergantian parlemen ini bisa dijadikan bahan renungan, apakah perlu pemimpin yang baru mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD 1945, atau melanjutkan proses amandemen dengan berbagai catatan kritis, sebagai bagian dari upaya antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kehancuran bangsa.***