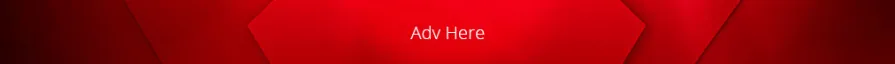Ketika KPK Berada Dalam Pusaran Rasa Cinta Dan Benci

Oleh : Gugus Elmo Ra’is
Selama Orde Baru, Bangsa Indonesia ini pernah menyandang gelar nista sebagai negara paling korup di kolong langit. Gelar itu disematkan oleh lembaga Transparancy Internasional (TI). Maka gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa pada tahun 1998 menempatkan upaya pemberantasan korupsi dan penegakkan supremasi hukum (law enforcement) sebagai agenda utama. Amanah suci itulah yang selalu menjadi tugas utama setiap pemerintahan. Maka, setelah terbitnya UU No 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemerintahan Megawati Soekarnoputri membentuk badan ad hoc yang diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terilhami oleh lembaga-lembaga serupa seperti Independen Comission Againts Corruptions (ICAC), di Hongkong serta Singapura, lembaga anti rasuah ini melakukan berbagai gebrakan. Tidak ada lagi imunnitas dalam bidang hukum, nyaris setiap hari ada tokoh yang ditangkap melalui OTT KPK mulai dari menteri, gubernur, politisi, hingga bupati. Pendeknya, keberadaan KPK telah mampu menyuguhkan asas persamaan hukum di mata masyarakat (equality before the law). Tak mengherankan bila banyak pihak yang merasa ‘panas dingin’ dengan keberadaan KPK.
Dengan berbagai kewenangan yang dimiliki, mulai dari penyadapan, penyidikan yang tidak bisa dihentikan kecuali melaui mekanisme pra peradilan, hingga independensi KPK telah menjelma menjadi lembaga yang superbody. Pertanyaanya, kenapa dengan segala sepak terjang KPK yang telah powerfull itu, belum ada tanda-tanda repblik ini segera bersih dari korupsi. Bagaimana bila dilihat dari aspek hukum pidana, upaya pemberian sanksi hukuman badan dan financial itu sebagai upaya ultimum remedium ternyata belum bisa memberikan efek jera (detterent effeck) yang maksimal seperti tesis Jeremy Bentam.
Padahal esensi pemberian sanksi pidana itu adalah untuk menimbulkan efek jera, karena adanya kesenjangan antara hukum yang seharusnya dengan hukum dalam kenyataannya (das sollen dan das sein) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahkan dari segi sejarah, pemberian efek jera itu sebagai bentuk pembinaan sekaligus menghindari aspek pembalasan dikemudian hari seperti tesisnya Immanuel Kant (1724-1804) dan George Wihelm Friedrich Hegel (1770-1831).
Kenapa sanksi itu belum bisa menimbulkan efek jera ?, pertama, belum ada sanksi hukuman yang maksimal yang diberikan oleh para hakim Tipikor seperti misalnya penerapan hukuman mati. Padahal, penerapan hukuman mati itu telah diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Hukuman tersebut menjadi bagian dari Pasal 2 ayat 1 yang mengatur tentang perbuatan memperkaya diri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara.
Yang kedua sanksi finansial yang menggunakan terminologi, pemiskinan juga belum diterapkan sacara konsisten dan konsekuen. Faktanya, banyak narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin yang masih hidup mewah, dan bisa plesiran ke berbagai tempat. Bahkan sempat diberitakan, masih ada yang bias menggunakan jasa artis untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Padahal, dalam tindak pidana korupsi, sanksi financial berupa pemiskinan terhadap koruptor telah diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penerapan hukum hukum secara ambivalen itulah yang mengakibatkan tujuan efek jera tidak maksimal.
Disisi lain, ada pertanyaan besar yang belum terjawab, yakni bagaimana dengan tugas supervisi yang diemban KPK terhadap aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejakasaan. Seperti diketahui, pembentukan KPK sebagai lembaga ad hoc (sementara) salah satunya untuk melakukan supervisi dan penguatan lembaga lain yang kredibilitasnya pada masa Orde Baru sangat buruk baik secara kemampuan teknis maupun moralitas. Fungsi kelembagaan inilah yang kini menjadi sumber pertanyaan.
Yang terjadi kini justru tekesan semua ditake over oleh KPK hingga kasus dengan nilai dibawah Rp 1 M yang dinilai melanggar ketentuan sesuai dengan UU tentang KPK. Apalagi dengan bekal kewenangan yang mewah membuat lembaga lain menjadi ‘iri’ seperti bebas melakukan penyadapan. Itupun belum terhitung dengan fasilitas gaji yang sangat besar yakni minimal Rp 25 juta atau sekitar 4 kali dari Perwira Tinggi Polri. Namun tenyata hasil pengembalian uang Negara yang dilakukan oleh KPK dinilai masih kalah dibandingkan dengan Kejaksaan.
Sehingga tak mengherankan bila banyak pihak yang mengusulkan adanya revisi terhadap UU KPK terutama terkait penyadapan. Dengan berbagai argumentasi mereka ingin melakukan revisi terhadap KPK tentu dengan judul untuk membenahi KPK. Persoalnnya, banyak tidak yang menyadari jika ada ‘penumpang gelap’ yang ingin membantu membenahi tetapi sejatinya ingin memperlemah bahkan bila perlu melumpuhkan KPK. Disinilah perlunya pemikiran yang jernih dalam menata KPK.
Selama Orde Baru, Bangsa Indonesia ini pernah menyandang gelar nista sebagai negara paling korup di kolong langit. Gelar itu disematkan oleh lembaga Transparancy Internasional (TI). Maka gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa pada tahun 1998 menempatkan upaya pemberantasan korupsi dan penegakkan supremasi hukum (law enforcement) sebagai agenda utama. Amanah suci itulah yang selalu menjadi tugas utama setiap pemerintahan. Maka, setelah terbitnya UU No 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemerintahan Megawati Soekarnoputri membentuk badan ad hoc yang diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terilhami oleh lembaga-lembaga serupa seperti Independen Comission Againts Corruptions (ICAC), di Hongkong serta Singapura, lembaga anti rasuah ini melakukan berbagai gebrakan. Tidak ada lagi imunnitas dalam bidang hukum, nyaris setiap hari ada tokoh yang ditangkap melalui OTT KPK mulai dari menteri, gubernur, politisi, hingga bupati. Pendeknya, keberadaan KPK telah mampu menyuguhkan asas persamaan hukum di mata masyarakat (equality before the law). Tak mengherankan bila banyak pihak yang merasa ‘panas dingin’ dengan keberadaan KPK.
Dengan berbagai kewenangan yang dimiliki, mulai dari penyadapan, penyidikan yang tidak bisa dihentikan kecuali melaui mekanisme pra peradilan, hingga independensi KPK telah menjelma menjadi lembaga yang superbody. Pertanyaanya, kenapa dengan segala sepak terjang KPK yang telah powerfull itu, belum ada tanda-tanda repblik ini segera bersih dari korupsi. Bagaimana bila dilihat dari aspek hukum pidana, upaya pemberian sanksi hukuman badan dan financial itu sebagai upaya ultimum remedium ternyata belum bisa memberikan efek jera (detterent effeck) yang maksimal seperti tesis Jeremy Bentam.
Padahal esensi pemberian sanksi pidana itu adalah untuk menimbulkan efek jera, karena adanya kesenjangan antara hukum yang seharusnya dengan hukum dalam kenyataannya (das sollen dan das sein) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahkan dari segi sejarah, pemberian efek jera itu sebagai bentuk pembinaan sekaligus menghindari aspek pembalasan dikemudian hari seperti tesisnya Immanuel Kant (1724-1804) dan George Wihelm Friedrich Hegel (1770-1831).
Kenapa sanksi itu belum bisa menimbulkan efek jera ?, pertama, belum ada sanksi hukuman yang maksimal yang diberikan oleh para hakim Tipikor seperti misalnya penerapan hukuman mati. Padahal, penerapan hukuman mati itu telah diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Hukuman tersebut menjadi bagian dari Pasal 2 ayat 1 yang mengatur tentang perbuatan memperkaya diri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara.
Yang kedua sanksi finansial yang menggunakan terminologi, pemiskinan juga belum diterapkan sacara konsisten dan konsekuen. Faktanya, banyak narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin yang masih hidup mewah, dan bisa plesiran ke berbagai tempat. Bahkan sempat diberitakan, masih ada yang bias menggunakan jasa artis untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Padahal, dalam tindak pidana korupsi, sanksi financial berupa pemiskinan terhadap koruptor telah diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penerapan hukum hukum secara ambivalen itulah yang mengakibatkan tujuan efek jera tidak maksimal.
Disisi lain, ada pertanyaan besar yang belum terjawab, yakni bagaimana dengan tugas supervisi yang diemban KPK terhadap aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejakasaan. Seperti diketahui, pembentukan KPK sebagai lembaga ad hoc (sementara) salah satunya untuk melakukan supervisi dan penguatan lembaga lain yang kredibilitasnya pada masa Orde Baru sangat buruk baik secara kemampuan teknis maupun moralitas. Fungsi kelembagaan inilah yang kini menjadi sumber pertanyaan.
Yang terjadi kini justru tekesan semua ditake over oleh KPK hingga kasus dengan nilai dibawah Rp 1 M yang dinilai melanggar ketentuan sesuai dengan UU tentang KPK. Apalagi dengan bekal kewenangan yang mewah membuat lembaga lain menjadi ‘iri’ seperti bebas melakukan penyadapan. Itupun belum terhitung dengan fasilitas gaji yang sangat besar yakni minimal Rp 25 juta atau sekitar 4 kali dari Perwira Tinggi Polri. Namun tenyata hasil pengembalian uang Negara yang dilakukan oleh KPK dinilai masih kalah dibandingkan dengan Kejaksaan.
Sehingga tak mengherankan bila banyak pihak yang mengusulkan adanya revisi terhadap UU KPK terutama terkait penyadapan. Dengan berbagai argumentasi mereka ingin melakukan revisi terhadap KPK tentu dengan judul untuk membenahi KPK. Persoalnnya, banyak tidak yang menyadari jika ada ‘penumpang gelap’ yang ingin membantu membenahi tetapi sejatinya ingin memperlemah bahkan bila perlu melumpuhkan KPK. Disinilah perlunya pemikiran yang jernih dalam menata KPK.