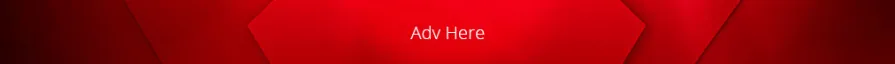Maksimalisasi Sanksi Pidana Sebagai Terapi

Oleh : Gugus Elmo Ra’is
Adanya sanksi dalam hukum pidana bisa memperlihatkan eksistensi hukum dalam suatu masyarakat (ibi societas ibi ius). Karena hukum itu adalah seperangkat norma yang dijadikan acuan sekaligus harus ditaati oleh setiap elemen masyarakat.
Barister (advokad) sekaligus filusuf asal Inggris, John Austin dalam bukunya The Province of Jurisprudance Determined (1832) pernah mengeluarkan permise yang sangat terkenal the law are command (hukum adalah komando), maka hukum adalah sebuah instrument yang bersifat afirmatif dan memaksa setiap individu yang menjadi warga negara.
Maka norma hukum yang termakthub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berisi tentang larangan-larangan sekaligus sanksi bagi yang melanggar berbagai ketentuan itu. Tetapi penerapan sanksi itu juga harus mempertimbangkan berbagai aspek. Sekondan Austin yang juga berasal dari Inggris, Jeremy Bentham melalui teori utilitarianisme memberikan premis jika penerapan sanksi itu harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti, konkrit, mendasar dan memberikan manfaat untuk menghadirkan keamanan dan kebahagiaan.
Berdasarkan persepektif itu maka setiap sanksi pidana itu harus memberikan pengaruh yang mendasar serta memberikan manfaat terhadap pelaku kejahatan maupun masyarakat di sekitranya. Dalam konteks pribadi pelaku kejahatan sanksi itu harus bisa memberikan shock terapy (terapi kejut) serta detterent effect (efekjera) untuk tidak mengulangi perbuatan serupa dikemudian hari.
Sekaligus juga memberikan pembelajaran bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan hal yang sama sehingga pada gilirannya memberikan rasa aman di masyarakat serta menciptakan kebahagiaan sebagai tujuan utama adanya hukum.
Dengan konsideran seperti itu maka setiap pasal dalam KUHP harus dijadikan dasar bagi para praktisi hukum kita dalam proses pengambilan putusan secara maksimal.
Ironisnya kita masih sering mendengar jika pasal-pasal itu justru menjadi ‘komoditas’ bagi para praktisi hukum kita, semua tergantung dengan permis ‘wani piro’ untuk menentukan bahkan mengurangi sanksi pidana. Sehingga penerapan sanksi hukum pidana itu tidak pernah maksimal.
Tragisnya, sanksi yang tidak maksimal itu justru terjadi terhadap kasus kasus yang masuk kategori extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) seperti korupsi yang menjadi atensi bersama serta menjadi amanah suci reformasi.
Padahal kita telah sepakat untuk memberlakukan secara khusus terhadap kasus korupsi dengan membuat Undang-Undang tersendiri (lex specialist), namun faktanya hanya sekedar macan kertas. Hingga saat ini belum ada satu pun terpidana kasus korupsi yang dihukum maksimal (mati).
Padahal hukuman maksimal (mati) dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meski baru sebatas pada korupsi dana bantuan bencana alam.
Rencana pemberian sanksi financial secara maksimal dengan menggunakan terminology pemiskinan baru sebatas wacana. Dengan pemberian sanksi pidana yang tidak maksimal itu (ringan) tujuan memberikan efek jera terhadap pelaku serta masyarakat umum tidak akan tercapai.
Karena setiap koruptor bisa melakukan kalkulasi (breakdown), dengan dana hasil korupsi yang mereka peroleh setelah dipotong biaya proses hukum serta menjalani hukuman masih terdapat sisa yang signifikan untuk hidup tenang dan makmur setelah keluar dari penjara.
Subtansi-subtansi inilah yang seharusnya menjadi materi utama dalam proses revisi Undang-Undang di DPR. Tetapi faktanya masih luput dari sentuhan para pakar hukum maupun kalangan DPR. Bahkan terkesan mereka berusaha mengamankan kepentingan masing-masing. Tanpa mau memikirkan pondasi yang mendasar dalam upaya untuk membangun bangsa dan negara yang bersih dari korupsi.
Semestinya kita malu dan mau belajar ke Negeri China. Berdasarkan manifesto tentang hukuman mati yang diberikan oleh Presiden Zhu Rongji, negeri komunis itu secara tegas telah menerapkan hukuman mati sebagai bagian untuk memerangi korupsi.
Pada tahun 2018 lalu misalnya, telah dilaksanakan setidaknya 680 hukuman mati. Kebijakan itu ternyata cukup efektif untuk menekan angka korupsi di negeri tirai bamboo itu.
Sebaliknya sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan memiliki 5 agama besar, ternyata korupsi masih tetap meraja lela. Nyaris seperti bergantian, partai-partai ikut menyumbang koruptor yang menjadi terpidana, tetapi tetap tidak memberikan efek jera, karena sanksi pidananya tidak pernah maksimal.***
Adanya sanksi dalam hukum pidana bisa memperlihatkan eksistensi hukum dalam suatu masyarakat (ibi societas ibi ius). Karena hukum itu adalah seperangkat norma yang dijadikan acuan sekaligus harus ditaati oleh setiap elemen masyarakat.
Barister (advokad) sekaligus filusuf asal Inggris, John Austin dalam bukunya The Province of Jurisprudance Determined (1832) pernah mengeluarkan permise yang sangat terkenal the law are command (hukum adalah komando), maka hukum adalah sebuah instrument yang bersifat afirmatif dan memaksa setiap individu yang menjadi warga negara.
Maka norma hukum yang termakthub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berisi tentang larangan-larangan sekaligus sanksi bagi yang melanggar berbagai ketentuan itu. Tetapi penerapan sanksi itu juga harus mempertimbangkan berbagai aspek. Sekondan Austin yang juga berasal dari Inggris, Jeremy Bentham melalui teori utilitarianisme memberikan premis jika penerapan sanksi itu harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti, konkrit, mendasar dan memberikan manfaat untuk menghadirkan keamanan dan kebahagiaan.
Berdasarkan persepektif itu maka setiap sanksi pidana itu harus memberikan pengaruh yang mendasar serta memberikan manfaat terhadap pelaku kejahatan maupun masyarakat di sekitranya. Dalam konteks pribadi pelaku kejahatan sanksi itu harus bisa memberikan shock terapy (terapi kejut) serta detterent effect (efekjera) untuk tidak mengulangi perbuatan serupa dikemudian hari.
Sekaligus juga memberikan pembelajaran bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan hal yang sama sehingga pada gilirannya memberikan rasa aman di masyarakat serta menciptakan kebahagiaan sebagai tujuan utama adanya hukum.
Dengan konsideran seperti itu maka setiap pasal dalam KUHP harus dijadikan dasar bagi para praktisi hukum kita dalam proses pengambilan putusan secara maksimal.
Ironisnya kita masih sering mendengar jika pasal-pasal itu justru menjadi ‘komoditas’ bagi para praktisi hukum kita, semua tergantung dengan permis ‘wani piro’ untuk menentukan bahkan mengurangi sanksi pidana. Sehingga penerapan sanksi hukum pidana itu tidak pernah maksimal.
Tragisnya, sanksi yang tidak maksimal itu justru terjadi terhadap kasus kasus yang masuk kategori extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) seperti korupsi yang menjadi atensi bersama serta menjadi amanah suci reformasi.
Padahal kita telah sepakat untuk memberlakukan secara khusus terhadap kasus korupsi dengan membuat Undang-Undang tersendiri (lex specialist), namun faktanya hanya sekedar macan kertas. Hingga saat ini belum ada satu pun terpidana kasus korupsi yang dihukum maksimal (mati).
Padahal hukuman maksimal (mati) dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meski baru sebatas pada korupsi dana bantuan bencana alam.
Rencana pemberian sanksi financial secara maksimal dengan menggunakan terminology pemiskinan baru sebatas wacana. Dengan pemberian sanksi pidana yang tidak maksimal itu (ringan) tujuan memberikan efek jera terhadap pelaku serta masyarakat umum tidak akan tercapai.
Karena setiap koruptor bisa melakukan kalkulasi (breakdown), dengan dana hasil korupsi yang mereka peroleh setelah dipotong biaya proses hukum serta menjalani hukuman masih terdapat sisa yang signifikan untuk hidup tenang dan makmur setelah keluar dari penjara.
Subtansi-subtansi inilah yang seharusnya menjadi materi utama dalam proses revisi Undang-Undang di DPR. Tetapi faktanya masih luput dari sentuhan para pakar hukum maupun kalangan DPR. Bahkan terkesan mereka berusaha mengamankan kepentingan masing-masing. Tanpa mau memikirkan pondasi yang mendasar dalam upaya untuk membangun bangsa dan negara yang bersih dari korupsi.
Semestinya kita malu dan mau belajar ke Negeri China. Berdasarkan manifesto tentang hukuman mati yang diberikan oleh Presiden Zhu Rongji, negeri komunis itu secara tegas telah menerapkan hukuman mati sebagai bagian untuk memerangi korupsi.
Pada tahun 2018 lalu misalnya, telah dilaksanakan setidaknya 680 hukuman mati. Kebijakan itu ternyata cukup efektif untuk menekan angka korupsi di negeri tirai bamboo itu.
Sebaliknya sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan memiliki 5 agama besar, ternyata korupsi masih tetap meraja lela. Nyaris seperti bergantian, partai-partai ikut menyumbang koruptor yang menjadi terpidana, tetapi tetap tidak memberikan efek jera, karena sanksi pidananya tidak pernah maksimal.***