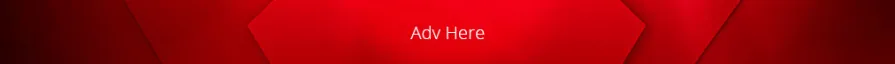Menghapus Jejak Kolonialisme Dengan Revisi KUHP

KUHP merupakan bentuk kolonialisme hukum yang seharusnya segera dihapuskan
Oleh : Gugus Elmo Ra’is
Dalam preambule (pembukaan) UUD 1945 yang merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia secara eksplisit termakthub deklarasi anti penjajahan. “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Maka sangat ironis, sebagai bangsa berdaulat dan merdeka yang merupakan hasil perjuangan para pahlawan dengan penghorbanan darah dan air mata, kini kita masih membiarkan kolonialisme meninggalkan warisan yang menguasai sendi kehidupan kita yang paling vital yakni hukum dalam bentuk KUHP.
Kodifikasi (penghimpunan) hukum-hukum warisan kolonial menjadi kaidah hukum tertulis (ler certa/lex scripta) dalam bentuk Kitab Umum Hukum Pidana (KUHP) merupakan bentuk kolonialisme hukum yang seharusnya segera dihapuskan. Strafrecht yang sekarang kita gunakan ini adalah warisan dari Belanda yang pernah menjajah kita selama 350 tahun, itupun juga merupakan produk kolinialisme yang sebelumnya yakni Code Penal. Seperti diketahui, Belanda meski menjajah Indonesia sempat menjadi koloni dari Parnacis (1825-1830).
Sehingga gagasan dilakukan revisi terhadap KUHP itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak sedikit pakar hukum pidana yang kita miliki saat ini. Mereka pasti bisa membuat rumusan kaidah hukum yang secara sosiologis cocok dengan sosio cultural Bangsa Indonesia. Proses perumusan Ius costituendum (hukum yang akan diberlakukan) dalam bentuk Rancangan KUHP itu harus melibatkan banyak elemen, sehingga akan dapat diperoleh rumusan hukum yang komprehensif dan bisa memenuhi rasa keadilan serta tidak berbenturan dengan asas-asas hukum yang telah ada sebagai jantungnya hukum di Indonesia.
Dalam proses pembahasan ini harus melibatkan pakar-pakar hukum serta bila perlu melibatkan pakar-pakar dalam bidang lain. Dalam hemat saya, proses pembahasannya tidak perlu diserahkan ke DPR untuk menghindari framing politik dalam merumuskan pasal-pasal tertentu seperti misalnya dalam hal pasal tentang, penghinaan presiden. Semua harus menggunakan standar moralitas bangsa, (quid leges sine moribus) dalam merumuskan hukum negara dan bukan demi kepentingan kelompok politik tertentu. Fungsi legislasi DPR itu bisa digunakan dalam proses penetapannya saja, setelah mendapatkan usul dari eksekutif (pemerintah).
Ada memori kelam dalam proses revisi UU yang digunakan untuk perebutan kepentingan politik jangka pendek. Masih segar dalam ingatan kita dalam proses revisi UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Saat itu terjadi perdebatan sengit antara kubu partai yang memiliki Ketum berlatar pendidikan SMA dengan kubu lain yang menghendaki agar Capres harus berlatar belakang pendidikan S1. Para pihak dalam hal ini para anggota DPR itu hanya memikirkan kepentingan politik jangkap pendek kelompoknya untuk menjegal calon lawan yang hanya lulusan SMA sebaliknya kubu lawan berusaha keras untuk meloloskan Ketumnya dalam ajang Pilpres periode selanjutnya. Artinya para politisi itu hanya memikirkan kepentingan politik kelompoknya ketimbang menggunakan konsideran untuk kepentingan bangsa yang lebih luas.
Dari draft RUU KUHP yang sempat beredar nampak beberapa pasal yang kontroversial yang harus dibahas ulang sehingga tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Terutama tentang pasal-pasal yang mengatur hubungan antara suami istri yang cenderung bisa dimanipulasi oleh pihak tertentu untuk menjerat pasangannya, apabila sudah tidak ada kesesuaian dintara keduanya.
Dalam KUHP yang sebelumnya sudah sangat jelas frasa tentang makar yang diatur dalam 23 pasal yang ada di KUHP termasuk ancaman dan penghinaan Presiden yang sudah diatur secara jelas. Sehingga usulan revisi tentang pasal penghinaan presiden itu harus dikaji secara mendalam.Bersikap kritis terhadap lembaga kepresidenan adalah konsekuensi logis kita memilih demokrasi sebagai system pilihan kita. Apalagi kebebasan berpendapat adalah prasyarat utama demokrasi (conditio sin qua non). Maka harus ada pembatasan yang jelas antara kritis terhadap kebijakan dengan penyerangan/penghinaan terhadap presiden secara kelembagaan, individu/personal.
Pasal yang interpertatif hanya akan menjadi pasal karet yang bisa digunakan oleh penguasa untuk menjerat lawan-lawan politiknya. Padahal kita telah sepakat untuk menghapus UU Subversif yang pernah digunakan oleh penguasa Orde Baru untuk menjerat tokoh-tokoh yang kritis terhadap pusat kekuasaan.***
Dalam preambule (pembukaan) UUD 1945 yang merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia secara eksplisit termakthub deklarasi anti penjajahan. “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Maka sangat ironis, sebagai bangsa berdaulat dan merdeka yang merupakan hasil perjuangan para pahlawan dengan penghorbanan darah dan air mata, kini kita masih membiarkan kolonialisme meninggalkan warisan yang menguasai sendi kehidupan kita yang paling vital yakni hukum dalam bentuk KUHP.
Kodifikasi (penghimpunan) hukum-hukum warisan kolonial menjadi kaidah hukum tertulis (ler certa/lex scripta) dalam bentuk Kitab Umum Hukum Pidana (KUHP) merupakan bentuk kolonialisme hukum yang seharusnya segera dihapuskan. Strafrecht yang sekarang kita gunakan ini adalah warisan dari Belanda yang pernah menjajah kita selama 350 tahun, itupun juga merupakan produk kolinialisme yang sebelumnya yakni Code Penal. Seperti diketahui, Belanda meski menjajah Indonesia sempat menjadi koloni dari Parnacis (1825-1830).
Sehingga gagasan dilakukan revisi terhadap KUHP itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak sedikit pakar hukum pidana yang kita miliki saat ini. Mereka pasti bisa membuat rumusan kaidah hukum yang secara sosiologis cocok dengan sosio cultural Bangsa Indonesia. Proses perumusan Ius costituendum (hukum yang akan diberlakukan) dalam bentuk Rancangan KUHP itu harus melibatkan banyak elemen, sehingga akan dapat diperoleh rumusan hukum yang komprehensif dan bisa memenuhi rasa keadilan serta tidak berbenturan dengan asas-asas hukum yang telah ada sebagai jantungnya hukum di Indonesia.
Dalam proses pembahasan ini harus melibatkan pakar-pakar hukum serta bila perlu melibatkan pakar-pakar dalam bidang lain. Dalam hemat saya, proses pembahasannya tidak perlu diserahkan ke DPR untuk menghindari framing politik dalam merumuskan pasal-pasal tertentu seperti misalnya dalam hal pasal tentang, penghinaan presiden. Semua harus menggunakan standar moralitas bangsa, (quid leges sine moribus) dalam merumuskan hukum negara dan bukan demi kepentingan kelompok politik tertentu. Fungsi legislasi DPR itu bisa digunakan dalam proses penetapannya saja, setelah mendapatkan usul dari eksekutif (pemerintah).
Ada memori kelam dalam proses revisi UU yang digunakan untuk perebutan kepentingan politik jangka pendek. Masih segar dalam ingatan kita dalam proses revisi UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Saat itu terjadi perdebatan sengit antara kubu partai yang memiliki Ketum berlatar pendidikan SMA dengan kubu lain yang menghendaki agar Capres harus berlatar belakang pendidikan S1. Para pihak dalam hal ini para anggota DPR itu hanya memikirkan kepentingan politik jangkap pendek kelompoknya untuk menjegal calon lawan yang hanya lulusan SMA sebaliknya kubu lawan berusaha keras untuk meloloskan Ketumnya dalam ajang Pilpres periode selanjutnya. Artinya para politisi itu hanya memikirkan kepentingan politik kelompoknya ketimbang menggunakan konsideran untuk kepentingan bangsa yang lebih luas.
Dari draft RUU KUHP yang sempat beredar nampak beberapa pasal yang kontroversial yang harus dibahas ulang sehingga tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Terutama tentang pasal-pasal yang mengatur hubungan antara suami istri yang cenderung bisa dimanipulasi oleh pihak tertentu untuk menjerat pasangannya, apabila sudah tidak ada kesesuaian dintara keduanya.
Dalam KUHP yang sebelumnya sudah sangat jelas frasa tentang makar yang diatur dalam 23 pasal yang ada di KUHP termasuk ancaman dan penghinaan Presiden yang sudah diatur secara jelas. Sehingga usulan revisi tentang pasal penghinaan presiden itu harus dikaji secara mendalam.Bersikap kritis terhadap lembaga kepresidenan adalah konsekuensi logis kita memilih demokrasi sebagai system pilihan kita. Apalagi kebebasan berpendapat adalah prasyarat utama demokrasi (conditio sin qua non). Maka harus ada pembatasan yang jelas antara kritis terhadap kebijakan dengan penyerangan/penghinaan terhadap presiden secara kelembagaan, individu/personal.
Pasal yang interpertatif hanya akan menjadi pasal karet yang bisa digunakan oleh penguasa untuk menjerat lawan-lawan politiknya. Padahal kita telah sepakat untuk menghapus UU Subversif yang pernah digunakan oleh penguasa Orde Baru untuk menjerat tokoh-tokoh yang kritis terhadap pusat kekuasaan.***