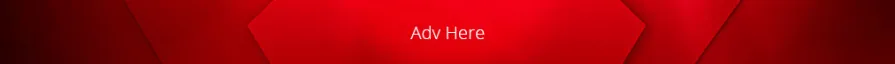Meredam Krisis Dengan Soekarnoisme

Oleh : Gugus Elmo Ra’is
Proses reformasi tahun 1998 yang dilakukan oleh para mahasiswa tak ubahnya seperti memberi ‘cek kosong’ kepada para elit politik saat itu. Cek itu berisi mandat untuk menyusun ulang sistem pemerintahan yang baru, sebagai antitesis dari sistem Orde Baru yang cenderung tertutup dan korup. Dan hasilnya seperti yang saat ini kita rasakan, mesti kita harus tetap apresiasi dengan adanya beberapa perubahan yang positif. Seperti demokratisasi yang berjalan dengan adanya kebebasan untuk berbicara dan berpendapat sebagai conditio sin qua non (prasyarat utama) demokrasi.
Namun reformasi itu juga yang menjadi pintu gerbang masuknya liberalisasi politik di Indonesia. Seperti misalnya sistem politik multi partai, sistem Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung, hingga sistem desentralisasi pemerintahan melalui otonomi daerah. Proses perubahan itu diintrodusir melalui proses amandemen terhadap UUD 1945. Sistem politik multi partai yang menurut Scott Mainwaring kurang cocok buat Indonesia, dan sistem Pilpres secara langsung serta desentralisasi inilah yang menciptakan kompleksitas persoalan. Apalagi disaat bangsa sedang mengalami krisis seperti saat ini.
Hipotesanya, dengan sistem multipartai serta Pilpres secara langsung, maka proses penyusunan pemerintahan selalu berbasis proses trading horse (dagang sapi) baik secara terbuka atau tertutup. Proses dagang sapi itu dilakukan oleh para pemilik ‘saham politik’ yakni para elit partai yang terlibat dalam proses penyusunan kekuatan melalui koalisi, untuk memenuhi ketentuan presidential threshold sebesar 20% sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
Karena dengan sistem multi partai mustahil ada rolling partay (partai pemenang) yang bisa memenuhi kuota hingga 20%, sehingga koalisi merupakan sebuah keniscayaan. Proses pendekatan untuk melakukan koalisi inilah yang melahirkan terminologi, wani piro, sebagai tawar menawar bila partai pemenang mengajak partai lain untuk bergabung dalam gerbong koalisi. Sementara rakyat yang berdasarkan konstitusi adalah pemilik tertinggi kedaulatan, dalam sistem ini rakyat hanya sekedar pemegang 'saham portofolio’.
Dengan konfigurasi politik seperti itu, maka produk dari Pilpres itu akan menghasilkan pimimpin yang tidak bisa memiliki strong leadership, karena telah terjerat sedemikian rupa oleh sistem. Karena terlalu banyak kepentingan yang beredar di lingkar dalam (inner circle) kekuasaan. Hal itu bisa terlihat dengan banyaknya kebijakan yang saling bertabrakan antara departemen, dengan menggunakan dasar hukum masing-masing.
Tesis itulah yang menjelaskan kenapa pemerintah cenderung lamban dalam menyikapi adanya krisis. Apalagi bila berhadapan dengan sistem desentralisasi yang memberikan ruang terjadinya perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga menimbulkan kesan saling berebut kewenangan antara pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan. Bahkan terjadi sikap saling tuduh, kelompok satu menuduh kepala daerah overlapping, sebaliknya kelompok lain menuduh pemerintah pusat lelet dan lamban. Contoh konkritnya adalah ketika muncul bencana banjir di Jabodetabek dan wabah Covid 19. Padahal sesungguhnya problem itu muncul dari sistem pemerintahan.
Sebagai komparasi yang aktual, kenapa jumlah korban Covid 19 di Amerika Serikat kini melambung tinggi mencapai angka sekitar 1,1 juta jiwa terpapar Covid 19 dengan angka kematian mencapai 70 ribu jiwa. Hal itu tidak terlepas dari sistem pemerintahan yang mereka anut yakni federalisme. Angka terus melonjak karena antara pemerintah pusat dan negara bagian tidak memiliki kebijakan yang seragam. Donald Trump cenderung ‘mengharamkan’ lockdown, demi alasan ekonomi tetapi sebaliknya 10 negara bagian di wilayah timur Amerika justru menerapkan lockdown. Tidak seragamnya kebijakan itulah yang mengakibatkan lockdown yang mereka lakukan tidak efektif.
Pola relasi antara pemerintah pusat dan daerah yang selegence (amburadul), itulah yang menjadi bukti bahwa konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah diwariskan oleh Soekarno jauh lebih efektif dalam menggerakan dan menyatukan langkah bangsa dalam menghadapi musuh bersama. Bahkan konsep demokrasi liberal yang saat ini kita anut justru berpotensi memecah belah bangsa ini ketimbang menyatukan langkah untuk menuju cita-cita bersama yakni tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Karena dengan sistem multi partai dan Pilpres secara langsung hanya membuat masyarakat terfragmentasi menjadi dua kelompok yang saling berhadap-hadapan. Dan sisa perseteruan selama Pilpres itu terbukti masih sangat kentara, dengan munculnya sikap saling hujat terhadap masing-masing kelompok terutama dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah terutama dalam menghadapi krisis kesehatan yang menjalar ke krisis ekonomi seperti saat ini.
Konsep Soekarno melalui Manipol USDEK yang mengajak bangsa ini kembali ke UUD 1945 menjelang dekrit presiden 5 Juli 1959, bisa menjadi solusi alternative yang efektif untuk menghadapi krisis multidimensi seperti saat ini. Revitalisasi GBHN di satu sisi, serta mengembalikan demokrasi liberal menjadi demokrasi yang terpimpin, serta liberalisasi menjadi ekonomi yang terpimpin di sisi lain akan mampu meredam perebutan pengaruh dan kewenangan di lingkar dalam kekuasaan. Kondisi itu akan membuat langkah pemerintah bisa lebih sigap dalam menghadapi situasi.***
Proses reformasi tahun 1998 yang dilakukan oleh para mahasiswa tak ubahnya seperti memberi ‘cek kosong’ kepada para elit politik saat itu. Cek itu berisi mandat untuk menyusun ulang sistem pemerintahan yang baru, sebagai antitesis dari sistem Orde Baru yang cenderung tertutup dan korup. Dan hasilnya seperti yang saat ini kita rasakan, mesti kita harus tetap apresiasi dengan adanya beberapa perubahan yang positif. Seperti demokratisasi yang berjalan dengan adanya kebebasan untuk berbicara dan berpendapat sebagai conditio sin qua non (prasyarat utama) demokrasi.
Namun reformasi itu juga yang menjadi pintu gerbang masuknya liberalisasi politik di Indonesia. Seperti misalnya sistem politik multi partai, sistem Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung, hingga sistem desentralisasi pemerintahan melalui otonomi daerah. Proses perubahan itu diintrodusir melalui proses amandemen terhadap UUD 1945. Sistem politik multi partai yang menurut Scott Mainwaring kurang cocok buat Indonesia, dan sistem Pilpres secara langsung serta desentralisasi inilah yang menciptakan kompleksitas persoalan. Apalagi disaat bangsa sedang mengalami krisis seperti saat ini.
Hipotesanya, dengan sistem multipartai serta Pilpres secara langsung, maka proses penyusunan pemerintahan selalu berbasis proses trading horse (dagang sapi) baik secara terbuka atau tertutup. Proses dagang sapi itu dilakukan oleh para pemilik ‘saham politik’ yakni para elit partai yang terlibat dalam proses penyusunan kekuatan melalui koalisi, untuk memenuhi ketentuan presidential threshold sebesar 20% sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
Karena dengan sistem multi partai mustahil ada rolling partay (partai pemenang) yang bisa memenuhi kuota hingga 20%, sehingga koalisi merupakan sebuah keniscayaan. Proses pendekatan untuk melakukan koalisi inilah yang melahirkan terminologi, wani piro, sebagai tawar menawar bila partai pemenang mengajak partai lain untuk bergabung dalam gerbong koalisi. Sementara rakyat yang berdasarkan konstitusi adalah pemilik tertinggi kedaulatan, dalam sistem ini rakyat hanya sekedar pemegang 'saham portofolio’.
Dengan konfigurasi politik seperti itu, maka produk dari Pilpres itu akan menghasilkan pimimpin yang tidak bisa memiliki strong leadership, karena telah terjerat sedemikian rupa oleh sistem. Karena terlalu banyak kepentingan yang beredar di lingkar dalam (inner circle) kekuasaan. Hal itu bisa terlihat dengan banyaknya kebijakan yang saling bertabrakan antara departemen, dengan menggunakan dasar hukum masing-masing.
Tesis itulah yang menjelaskan kenapa pemerintah cenderung lamban dalam menyikapi adanya krisis. Apalagi bila berhadapan dengan sistem desentralisasi yang memberikan ruang terjadinya perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga menimbulkan kesan saling berebut kewenangan antara pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan. Bahkan terjadi sikap saling tuduh, kelompok satu menuduh kepala daerah overlapping, sebaliknya kelompok lain menuduh pemerintah pusat lelet dan lamban. Contoh konkritnya adalah ketika muncul bencana banjir di Jabodetabek dan wabah Covid 19. Padahal sesungguhnya problem itu muncul dari sistem pemerintahan.
Sebagai komparasi yang aktual, kenapa jumlah korban Covid 19 di Amerika Serikat kini melambung tinggi mencapai angka sekitar 1,1 juta jiwa terpapar Covid 19 dengan angka kematian mencapai 70 ribu jiwa. Hal itu tidak terlepas dari sistem pemerintahan yang mereka anut yakni federalisme. Angka terus melonjak karena antara pemerintah pusat dan negara bagian tidak memiliki kebijakan yang seragam. Donald Trump cenderung ‘mengharamkan’ lockdown, demi alasan ekonomi tetapi sebaliknya 10 negara bagian di wilayah timur Amerika justru menerapkan lockdown. Tidak seragamnya kebijakan itulah yang mengakibatkan lockdown yang mereka lakukan tidak efektif.
Pola relasi antara pemerintah pusat dan daerah yang selegence (amburadul), itulah yang menjadi bukti bahwa konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah diwariskan oleh Soekarno jauh lebih efektif dalam menggerakan dan menyatukan langkah bangsa dalam menghadapi musuh bersama. Bahkan konsep demokrasi liberal yang saat ini kita anut justru berpotensi memecah belah bangsa ini ketimbang menyatukan langkah untuk menuju cita-cita bersama yakni tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Karena dengan sistem multi partai dan Pilpres secara langsung hanya membuat masyarakat terfragmentasi menjadi dua kelompok yang saling berhadap-hadapan. Dan sisa perseteruan selama Pilpres itu terbukti masih sangat kentara, dengan munculnya sikap saling hujat terhadap masing-masing kelompok terutama dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah terutama dalam menghadapi krisis kesehatan yang menjalar ke krisis ekonomi seperti saat ini.
Konsep Soekarno melalui Manipol USDEK yang mengajak bangsa ini kembali ke UUD 1945 menjelang dekrit presiden 5 Juli 1959, bisa menjadi solusi alternative yang efektif untuk menghadapi krisis multidimensi seperti saat ini. Revitalisasi GBHN di satu sisi, serta mengembalikan demokrasi liberal menjadi demokrasi yang terpimpin, serta liberalisasi menjadi ekonomi yang terpimpin di sisi lain akan mampu meredam perebutan pengaruh dan kewenangan di lingkar dalam kekuasaan. Kondisi itu akan membuat langkah pemerintah bisa lebih sigap dalam menghadapi situasi.***