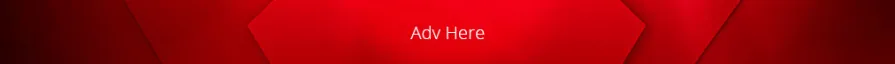Negara Yang Melupakan Sejarah (Naga Merah)

Oleh : Gugus Elmo Ra’is
Pancasila dan UUD 1945 adalah intisari peradaban Bangsa Nusantara. Karena falsafah dan dasar negara itu merupakan produk sinkertisme budaya dari bangsa yang multikultur yakni Indonesia. Proses dialektif budaya itu muncul mulai dari jaman kerajaan Salakanegara pada abad 2 hingga berujung pada proklamasi kemerdekaan 14 Agustus 1945. Setidaknya ada tiga fase perjuangan bangsa ini dalam menyatukan berbagai perbedaan itu menjadi satu kesatuan NKRI dalam balutan filosofi Bhineka Tunggal Ika yakni, national guest, (kesadaran nasional) national will (keinginan nasional) hingga national daad (perjuangan nasional).
Nasionalisme yang tumbuh sebagai lem perekat bangunan kebangsaan itu tidak terlepas dari peran Soekarno, yang memang lahir dan besar dari kultur sinkretisme. Arek Blitar ini memang dikenal gandrung persatuan dengan filosofi, manunggaling kawulo lan gusti apalagi setelah ngasu kaweruh (belajar) dari pemikir-pemikir dunia seperti Jean Jores, Karl Renan, Karl Kaustky, Otto Bauer, Otto Radek, Kamarakan Gandhi hingga Karl Mark atau yang lebih dikenal sebagai wall of mind. Semangat persatuan itulah yang mengilhami Soekarno bersama para founding father’s membentuk bangunan kebangsaan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasakan Pancasila dan UUD 1945.
Tetapi bangunan kebangsaan itu telah dipugar oleh semangat zero zum game atau tumpas kelor, saat era reformasi sebagai bentuk kemarahan bangsa ini terhadap rezim Orde Baru dibawah komando Soeharto sebagai pemerintahan yang tertutup dan korup. Tak ubahnya seperti membakar sarang karena ada tikus di dalamnya. Semua bangunan ketata negaraan itu dipugar dengan menggunakan cara konstitusional dalam bentuk amandemen UUD 1945. Pasca amandemen itulah, bermunculan UU, seperti UU No 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, UU tentang No 7 tahun 2017 tentqng Pemilu, serta UU No 2 tahun 2011 tentang Parpol.
Proses amandemen itulah yang memaksa kita memasuki bangunan kebangsaan baru dengan konsep yang baru yakni demokrasi liberal. Serta meninggalkan konsep lama yakni demokrasi terpimpin. Perubahan konsep inilah yang memberi ruang kebebasan terhadap siapapun untuk berorganisasi dan berpendapat sebagai qonditio sine qua non (prasyarat utama) demokrasi. Apalagi kebebasan berpendapat itu telah dijamin dalam Pasal 28E UUD 1945. Maka masyarakat punya hak untuk berpendapat apapun terhadap negara karena konstitusi telah memberi ruang untuk itu.
Tetapi munculnya bencana banjir dan wabah Corona telah menguak tabir atau bisa dimaknai sebagai blessing in this guise (baca : hikmah) untuk membenahi bangunan kebangsaan. Semangat otonomi daerah yang diintrodusir menggunakan UU No 32 tahun 2004 itu telah membuat pemerintah pusat kehilangan kendali terhadap pemerintah daerah, sehingga setiap daerah tidak bisa seirama dengan pemerintah pusat dalam menghadapi bencana. Hal itu berakibat langkah pemerintah menjadi lamban untuk menentukan sikap. Karena energi yang dimiliki terkuras hanya untuk berpolemik. Sementara bencana itu memerlukan penanganan yang cepat, terukur dan efektif. Semua elemen bangsa juga ikut berpolemik menggunakan partai sebagai saluran politik masing-masing. Sehingga kondisinya menjadi semakin gaduh, tanpa aksi yang nyata.
Karena polemik itulah negara seakan tidak bisa menterjemahkan sila ke dua Pancasila yakni kemanusiaan yang beradab, saat menghadapi bencana karena terbukti masih banyak elemen masyarakat yang luput dari perhatian negara saat wabah Corona terjadi. Apalagi keinginan untuk mewujudkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka wabah ini menjadi momentum kita untuk melakukan perbaikan susunan bangunan ketata-negaraan yang ideal terutama yang mengatur pola relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam UUD 1945 terutama alenia ke 4 juga mengatur tentang politik luar negari yang bebas dan aktif. Dengan kemampuan retorika yang hebat serta gaya politik yang flamboyan, Soekarno bisa menterjemahkan politik itu secara elegan, dengan memainkan ‘perasaan’ John F Kennedy, Khruscev maupun Peking (Tiongkok) demi untuk kepentingan bangsa Indonesia serta bangsa-bangsa dunia ketiga yang dihimpun dalam kelompok non blok. Periode itulah Indonesia bisa disegani dunia meski kondisi perokomiannya masih morat-marit.
Namun kini kita terjebak dalam kepentingan ekonomi jangka pendek, dengan menjalin ‘kemesraan’ dengan Tiongkok. Bahkan kita juga ikut menikmati program Tiongkok, belt and road iniative, dalam bentuk pinjaman/investasi untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dengan pinjaman itu negeri Tirai Bambu itu berhak ‘mendikte’ Naga Merah untuk menerima tenaga kerja mereka. Meski di dalam negeri sendiri masih banyak pengangguran. Maka untuk menjadikan negeri ini tetap berdaulat, kita harus tetap mengingat pondasi kenegaraan yang telah diwariskan oleh para founding father’s***
Pancasila dan UUD 1945 adalah intisari peradaban Bangsa Nusantara. Karena falsafah dan dasar negara itu merupakan produk sinkertisme budaya dari bangsa yang multikultur yakni Indonesia. Proses dialektif budaya itu muncul mulai dari jaman kerajaan Salakanegara pada abad 2 hingga berujung pada proklamasi kemerdekaan 14 Agustus 1945. Setidaknya ada tiga fase perjuangan bangsa ini dalam menyatukan berbagai perbedaan itu menjadi satu kesatuan NKRI dalam balutan filosofi Bhineka Tunggal Ika yakni, national guest, (kesadaran nasional) national will (keinginan nasional) hingga national daad (perjuangan nasional).
Nasionalisme yang tumbuh sebagai lem perekat bangunan kebangsaan itu tidak terlepas dari peran Soekarno, yang memang lahir dan besar dari kultur sinkretisme. Arek Blitar ini memang dikenal gandrung persatuan dengan filosofi, manunggaling kawulo lan gusti apalagi setelah ngasu kaweruh (belajar) dari pemikir-pemikir dunia seperti Jean Jores, Karl Renan, Karl Kaustky, Otto Bauer, Otto Radek, Kamarakan Gandhi hingga Karl Mark atau yang lebih dikenal sebagai wall of mind. Semangat persatuan itulah yang mengilhami Soekarno bersama para founding father’s membentuk bangunan kebangsaan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasakan Pancasila dan UUD 1945.
Tetapi bangunan kebangsaan itu telah dipugar oleh semangat zero zum game atau tumpas kelor, saat era reformasi sebagai bentuk kemarahan bangsa ini terhadap rezim Orde Baru dibawah komando Soeharto sebagai pemerintahan yang tertutup dan korup. Tak ubahnya seperti membakar sarang karena ada tikus di dalamnya. Semua bangunan ketata negaraan itu dipugar dengan menggunakan cara konstitusional dalam bentuk amandemen UUD 1945. Pasca amandemen itulah, bermunculan UU, seperti UU No 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, UU tentang No 7 tahun 2017 tentqng Pemilu, serta UU No 2 tahun 2011 tentang Parpol.
Proses amandemen itulah yang memaksa kita memasuki bangunan kebangsaan baru dengan konsep yang baru yakni demokrasi liberal. Serta meninggalkan konsep lama yakni demokrasi terpimpin. Perubahan konsep inilah yang memberi ruang kebebasan terhadap siapapun untuk berorganisasi dan berpendapat sebagai qonditio sine qua non (prasyarat utama) demokrasi. Apalagi kebebasan berpendapat itu telah dijamin dalam Pasal 28E UUD 1945. Maka masyarakat punya hak untuk berpendapat apapun terhadap negara karena konstitusi telah memberi ruang untuk itu.
Tetapi munculnya bencana banjir dan wabah Corona telah menguak tabir atau bisa dimaknai sebagai blessing in this guise (baca : hikmah) untuk membenahi bangunan kebangsaan. Semangat otonomi daerah yang diintrodusir menggunakan UU No 32 tahun 2004 itu telah membuat pemerintah pusat kehilangan kendali terhadap pemerintah daerah, sehingga setiap daerah tidak bisa seirama dengan pemerintah pusat dalam menghadapi bencana. Hal itu berakibat langkah pemerintah menjadi lamban untuk menentukan sikap. Karena energi yang dimiliki terkuras hanya untuk berpolemik. Sementara bencana itu memerlukan penanganan yang cepat, terukur dan efektif. Semua elemen bangsa juga ikut berpolemik menggunakan partai sebagai saluran politik masing-masing. Sehingga kondisinya menjadi semakin gaduh, tanpa aksi yang nyata.
Karena polemik itulah negara seakan tidak bisa menterjemahkan sila ke dua Pancasila yakni kemanusiaan yang beradab, saat menghadapi bencana karena terbukti masih banyak elemen masyarakat yang luput dari perhatian negara saat wabah Corona terjadi. Apalagi keinginan untuk mewujudkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka wabah ini menjadi momentum kita untuk melakukan perbaikan susunan bangunan ketata-negaraan yang ideal terutama yang mengatur pola relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam UUD 1945 terutama alenia ke 4 juga mengatur tentang politik luar negari yang bebas dan aktif. Dengan kemampuan retorika yang hebat serta gaya politik yang flamboyan, Soekarno bisa menterjemahkan politik itu secara elegan, dengan memainkan ‘perasaan’ John F Kennedy, Khruscev maupun Peking (Tiongkok) demi untuk kepentingan bangsa Indonesia serta bangsa-bangsa dunia ketiga yang dihimpun dalam kelompok non blok. Periode itulah Indonesia bisa disegani dunia meski kondisi perokomiannya masih morat-marit.
Namun kini kita terjebak dalam kepentingan ekonomi jangka pendek, dengan menjalin ‘kemesraan’ dengan Tiongkok. Bahkan kita juga ikut menikmati program Tiongkok, belt and road iniative, dalam bentuk pinjaman/investasi untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dengan pinjaman itu negeri Tirai Bambu itu berhak ‘mendikte’ Naga Merah untuk menerima tenaga kerja mereka. Meski di dalam negeri sendiri masih banyak pengangguran. Maka untuk menjadikan negeri ini tetap berdaulat, kita harus tetap mengingat pondasi kenegaraan yang telah diwariskan oleh para founding father’s***