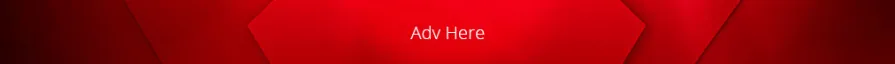Sabodo Teuing HAM

Umat Islam di Rohingya
Oleh : Gugus Elmo Ra’is
Hingga saat ini tindakan barbar yang dilakukan oleh pemerintah junta militer Myanmar terhadap suku Arakan atau yang lebih popular dengan sebutan Rakhine atau Rohingya masih tetap dilakukan. Etnic cleansing (pembersihan etnis) tetap dilakukan secara massif meski telah menelan korban hingga ratusan ribu jiwa.
Berdasarkan catatan lembaga social, Medecines Sans Frontierers (MSF), pada periode Agustus 2017 lalu terhitung sekitar 6.700 jiwa melayang hanya dalam waktu satu bulan. Tindakan barbar yang dilakukan oleh pemerintah yang mayoritas adalah suku Simo-Tibet itu menjadi teror yang menakutkan bagi sekitar 1,3 juta penduduk muslim Rohingnya.
Sikap komunitas internasional dalam menyikapi isu Rohingnya juga terkesan timbul tenggelam. Padahal aksi barbar yang masuk kategori genosida dan etnic cleansing (pembersihan etnis) itu dilakukan secara massif dan sistematis. Karena dilakukan oleh masyarakat serta ada unsure militer yang terlibat. Meski dari persepektif historis mereka adalah bagian dari warga Negara Myanmar karena mereka telah bermigrasi dari Bengal puluhan tahun silam.
Ironisnya, Myanmar saat ini justru sedang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi tokoh yang pernah memperoleh pengharagaan Nobel Perdamaian 1991. Tetapi karena kepentingan politik Suu Kyi justru membiarkan aksi pembantaian itu.
Dinginnya reaksi dunia internasional terhadap isu Rohingnya itu secara otomatis akan memperpanjang kontrak penderitaan Suku Arakan. Mereka akan selalu diintai bahaya dalam bentuk, penyiksaan, pemerkosaan dan pembunuhan, Padahal upaya penegakkan hukum itu bisa dilakukan minimal menggunakan yurisprudensi kasus Slobodan Milosemic yang telah melakukan kejahatan serupa terhadap Muslim Bosnia dan Kosovo. Hingga akhirnya, menggunakan instrument Jus Cogan, International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia, di Den Haag mengadili Slobodan Milosevic, Februari 2002, dengan tuduhan telah melakukan kejahatan perang. Hingga akhirnya Slobodan menemui ajalnya di sana.
Pertanyaannya kenapa komunitas internasional tidak mau mendorong untuk melakukan upaya penegakan HAM menggunakan mekanisme yang sama. Sehingga menimbulkan kesan adanya standar ganda dalam menegakkan HAM di dunia internasional. Harapan yang sama sebenarnya bisa ditunjukkan kepada komunitas ASEAN dimana Myanmar menjadi salah satu anggotanya.
Sebagai state party (negara anggota) Burma atau Myanmar harus tunduk dan patuh terhadap norma-norma yang telah disepakati (treaty making law) dalam perjanjian bilateral sesama Bangsa ASEAN. Apalagi kawasan ini dianggap sebagai kawasan dengan tingkat kerja sama paling kohesif di dunia. Maka sebagai bangsa yang ‘dituakan’ dan dianggap sebagai pemimpin karena luas wilayah dan jumlah penduduk yang paling besar, Indonesia harus bisa menginisiasi upaya - upaya penyelesaian konflik itu secara damai maupun paksa dan tidak bisa tutup mata.
Pertanyannya, komunitas yang telah diikat dalam perjanjian bilateral antara Bangsa ASEAN ini apakah menyangkut terhadap isu-isu HAM. Apalagi kawasan ini telah memiliki lembaga HAM yang bernama Asean Intergovermental Comission On Human Right (AICHR). Sayangnya lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk investigasi dan eksekusi, karena telah terjerat oleh Term of Reference (TOR) deklarasi ASEAN terutama dalam pasal 20 F seyang menyatakan, tidak boleh ada saling intervensi antara sesama anggota ASEAN. Praktis berdasarkan ketentuan ini AICHR, tak ubahnya seperti lembaga ‘arisan’ karena pimpinannya dilakukan secara bergilir tanpa bisa berbuat lebih. Hanya sekedar menyamakan persepsi serta meningkatkan pemahaman tentang HAM antar sesama anggota ASEAN.
Dengan kondisi yang seperti itu maka bisa dipahami jika sikap pemerintah Indonesia terkesan ‘minggrang minggring’ (baca : ambivalen) dalam menghadapi isu Rohingnya. Jadi jangan harap pemerintah Indonesia akan mengambil langkah radikal dengan memutuskan hubungan diplomatik terhadap Myanmnar apabila aksi pelanggaran HAM itu akan terus berlanjut. Meski upaya diplomatik hingga saat ini belum membuahkan hasil. Karena Indonesia telah terjerat perjanjian dengan para anggota ASEAN untuk tidak saling melakukan intervensi, meski telah terjadi pelanggaran HAM di mana-mana.
Artinya, isu penegakkan HAM belum menjadi skala prioritas bagi Bangsa ASEAN, meski secara ekonomi Bangsa ASEAN mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kerjasama bilateral yang dilakukan baru sebetas kerjasama, ekonomi dan budaya sementara HAM memiliki posisi kumaha engke wae. Inilah yang menjadi salah satu PR terbesar Bangsa ASEAN.***
Hingga saat ini tindakan barbar yang dilakukan oleh pemerintah junta militer Myanmar terhadap suku Arakan atau yang lebih popular dengan sebutan Rakhine atau Rohingya masih tetap dilakukan. Etnic cleansing (pembersihan etnis) tetap dilakukan secara massif meski telah menelan korban hingga ratusan ribu jiwa.
Berdasarkan catatan lembaga social, Medecines Sans Frontierers (MSF), pada periode Agustus 2017 lalu terhitung sekitar 6.700 jiwa melayang hanya dalam waktu satu bulan. Tindakan barbar yang dilakukan oleh pemerintah yang mayoritas adalah suku Simo-Tibet itu menjadi teror yang menakutkan bagi sekitar 1,3 juta penduduk muslim Rohingnya.
Sikap komunitas internasional dalam menyikapi isu Rohingnya juga terkesan timbul tenggelam. Padahal aksi barbar yang masuk kategori genosida dan etnic cleansing (pembersihan etnis) itu dilakukan secara massif dan sistematis. Karena dilakukan oleh masyarakat serta ada unsure militer yang terlibat. Meski dari persepektif historis mereka adalah bagian dari warga Negara Myanmar karena mereka telah bermigrasi dari Bengal puluhan tahun silam.
Ironisnya, Myanmar saat ini justru sedang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi tokoh yang pernah memperoleh pengharagaan Nobel Perdamaian 1991. Tetapi karena kepentingan politik Suu Kyi justru membiarkan aksi pembantaian itu.
Dinginnya reaksi dunia internasional terhadap isu Rohingnya itu secara otomatis akan memperpanjang kontrak penderitaan Suku Arakan. Mereka akan selalu diintai bahaya dalam bentuk, penyiksaan, pemerkosaan dan pembunuhan, Padahal upaya penegakkan hukum itu bisa dilakukan minimal menggunakan yurisprudensi kasus Slobodan Milosemic yang telah melakukan kejahatan serupa terhadap Muslim Bosnia dan Kosovo. Hingga akhirnya, menggunakan instrument Jus Cogan, International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia, di Den Haag mengadili Slobodan Milosevic, Februari 2002, dengan tuduhan telah melakukan kejahatan perang. Hingga akhirnya Slobodan menemui ajalnya di sana.
Pertanyaannya kenapa komunitas internasional tidak mau mendorong untuk melakukan upaya penegakan HAM menggunakan mekanisme yang sama. Sehingga menimbulkan kesan adanya standar ganda dalam menegakkan HAM di dunia internasional. Harapan yang sama sebenarnya bisa ditunjukkan kepada komunitas ASEAN dimana Myanmar menjadi salah satu anggotanya.
Sebagai state party (negara anggota) Burma atau Myanmar harus tunduk dan patuh terhadap norma-norma yang telah disepakati (treaty making law) dalam perjanjian bilateral sesama Bangsa ASEAN. Apalagi kawasan ini dianggap sebagai kawasan dengan tingkat kerja sama paling kohesif di dunia. Maka sebagai bangsa yang ‘dituakan’ dan dianggap sebagai pemimpin karena luas wilayah dan jumlah penduduk yang paling besar, Indonesia harus bisa menginisiasi upaya - upaya penyelesaian konflik itu secara damai maupun paksa dan tidak bisa tutup mata.
Pertanyannya, komunitas yang telah diikat dalam perjanjian bilateral antara Bangsa ASEAN ini apakah menyangkut terhadap isu-isu HAM. Apalagi kawasan ini telah memiliki lembaga HAM yang bernama Asean Intergovermental Comission On Human Right (AICHR). Sayangnya lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk investigasi dan eksekusi, karena telah terjerat oleh Term of Reference (TOR) deklarasi ASEAN terutama dalam pasal 20 F seyang menyatakan, tidak boleh ada saling intervensi antara sesama anggota ASEAN. Praktis berdasarkan ketentuan ini AICHR, tak ubahnya seperti lembaga ‘arisan’ karena pimpinannya dilakukan secara bergilir tanpa bisa berbuat lebih. Hanya sekedar menyamakan persepsi serta meningkatkan pemahaman tentang HAM antar sesama anggota ASEAN.
Dengan kondisi yang seperti itu maka bisa dipahami jika sikap pemerintah Indonesia terkesan ‘minggrang minggring’ (baca : ambivalen) dalam menghadapi isu Rohingnya. Jadi jangan harap pemerintah Indonesia akan mengambil langkah radikal dengan memutuskan hubungan diplomatik terhadap Myanmnar apabila aksi pelanggaran HAM itu akan terus berlanjut. Meski upaya diplomatik hingga saat ini belum membuahkan hasil. Karena Indonesia telah terjerat perjanjian dengan para anggota ASEAN untuk tidak saling melakukan intervensi, meski telah terjadi pelanggaran HAM di mana-mana.
Artinya, isu penegakkan HAM belum menjadi skala prioritas bagi Bangsa ASEAN, meski secara ekonomi Bangsa ASEAN mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kerjasama bilateral yang dilakukan baru sebetas kerjasama, ekonomi dan budaya sementara HAM memiliki posisi kumaha engke wae. Inilah yang menjadi salah satu PR terbesar Bangsa ASEAN.***