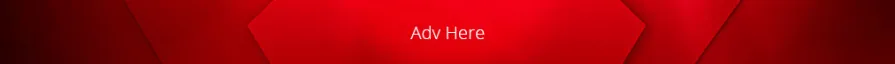Songong dan Kemlinthi Menjadi Faktor Kekalahan Trump

Oleh : Gugus Elmo Ra’is
Hingga artikel ini ditulis secara definitive belum keluar siapa pemenang Pilpres Amerika Serikat 2020. Tetapi Capres dari Partai Demokrat, Joe Biden sementara unggul jauh 264 suara electoral dibanding dengan perolehan Capres Partai Republik, Donald Trump yang baru memungut 214 suara electoral. Kemenangan Joe Biden di beberapa kantong pendukung Trump seperti Wisconsin dan Michigan menjadi sinyal bahaya sekaligus memberikan aura kemenangan bagi Biden untuk menduduki kursi Presiden Amerika yang ke 46. Praktis, Biden tinggal memerlukan 6 angka lagi untuk menjadi ‘USA One’ dengan perolehan suara tertinggi dalam sejarah Amerika.
Lonceng kekalahan bagi Trump kini mulai berdentang, seiring dengan langkahnya yang selalu kontroversial, songong dan kemlinthi (baca : adabnya kurang). Setidaknya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kekalahan Trump. Seperti diketahui, dalam Pilpres 2016 lalu Trump bisa menundukan Hillary Clinton meski mendapat perlawanan yang sengit. Bahkan hingga saat ini kemenangan Trump masih kontroversial serta menimbulkan spekulasi adanya keterlibatan Rusia dalam proses pemenangan itu.
Untuk meraih kemenangan itu Trump mengusung dan menyajikan jargon usang, ‘American first’ yang diupgrade menjadi ‘American first policy’. Tema kampanye nasionalisme ala Trump itu merupakan antithesis dari kebajikan Barrack Obama yang telah melakukan internasionalisme ekonomi dan politik. Dan terbukti menjelang masa berakhirnya kekuasaan Obama, Amerika terlilit krisis karena beban anggaran untuk pengerahan tentara Amerika di beberapa negara seperti Irak dan Afghanistan.
Di sisi lain, Amerika juga diterjang krisis bubble gum, karena dampak dari krisis kredit perumahan (subprime mortgage) serta bangkrutnya lembaga sekuritas Lehman Brothers, 2008 lalu Amerika berubah dari super power menjadi super losser (pecundang). Bahkan Amerika harus ngutang ke China untuk menambal defisit anggarannya, Tidak tanggung-tanggung utang Amerika ke China dalam bentuk US treasury itu segede gunung hingga mencapai US $ 1,12 triliun.
Maka tema kampanye Trump itu memperoleh momentum, dan menjanjikan angin segar bagi kepentingan ekonomi dan politik domestik. Karena Amerika memiliki ruang untuk membenahi perekonomiannya sendiri, sementara bagi negara-negara lain, Amerika seperti akan melakukan ‘pertobatan’ dari sikapnya yang suka kepo dan tengil dengan mau turut campur urusan negara lain. Dan itikad baik itu secara eksplisit diperlihatkan oleh Trump dengan menjalin komunikasi politik dengan Presiden Korea Utara, Kim Jong Un. Padahal sebelumnya Trump sempat menjuluki Korut dan Iran sebagai negara ‘poros setan’.
Tetapi konsistensi Trump dipertanyakan oleh masyarakat internasional setelah Amerika ditengarai terlibat dalam serangan terhadap Jenderal Iran, Qaseem Sulaimani. Hubungan Amerika dan China pun seperti Tom & Jerry, terutama setelah munculnya wabah Covid 19, bahkan ketika isu pemindahan Capitol, Ibu Kota Israel dari Tel Aviv ke Jerusaleem Timur, masyarakat internasionalpun bingung membaca gaya politik Trump. Ketika Indonesia menentang rencana itu, Trump justru menghardik Indonesia sebagai negara yang tidak tahu terima kasih dan mengancam akan membalasnya.
Gaya komunikasi politik Trump seperti ‘dewa mabuk’ itulah yang membuat banyak negara menjaga jarak. Tidak hanya dengan negara-negara dengan berbagai lembaga dunia seperti WHO dan PBB hubungan Amerika juga memburuk, apalagi Amerika sempat melakukan suspend terhadap bantuan keuangan PBB. Sikap itulah yang secara perlahan justru melunturkan hegemoni Amerika di mata dunia internasional. Sehingga banyak negara merasa tidak ‘happy’ dengan sikap Trump dan mereka lebih menginginkan Trump untuk tidak terpilih lagi.
Sementara kebijakan Trump dalam negeri juga memunculkan kontraksi yang hebat. Profesor ilmu politik dari Georgia State University, Charles Hankla mengkritik keras sepuluh langkah yang telah dilakukan oleh Trump seusai dilantik diantaranya adalah Amerika keluar dari Trans Pasific Patnershif (TPP) yang nota bene sudah tergabung dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), hanya karena dilandasi oleh sikap anti Beijing, ternyata justru berdampang negative terhadap perekonomian Amerika sendiri. Trump pun semakin kemlinthi (bertindak semaunya) dengan mengenakan tarif pajak 20% terhadap negara-negara yang telah menikmati surplus perdagangan dengan Amerika, kebijakan ini lagi-lagi justru membuat banyak negara ogah berurusan dengan Trump.
Untuk menterjemahkan ‘American first policy’ lagi-lagi Trump membuat blunder. Trump melakukan pembatasan imigrasi secara ketat, dan melarang orang dari banyak negara untuk masuk ke Amerika. Bahkan Trump sempat berniat untuk membangun tembok dan menutup perbatasan dengan Meksiko yang menjadi lubang keluar masuk imigran. Bahkan Trump membuat pernyataan yang membuat tersinggung banyak pihak dengan mengatakan ‘pengemismu, tetanggamu’. Sikap Trump yang songong dan kontroversial inilah yang membuat kalangan imigran menjadi dongkol terhadap Trump. Perlu diingat dari 328 juta jumlah penduduk Amerika, 51 juta diantaranya adalah kalangan imigran yang berasal dari negara-negara yang dilecehkan oleh Amerika seperti Meksiko, China, India, Kuba dll. Tentu mereka masih memiliki ikatan batin dengan negeri leluhurnya yang telah dilecehkan oleh Trump.
Isu rasisme selama pemerintahan Trump juga menguat dan meningkat tajam, apalagi pasca terbunuhnya George Floyd, Mei 2020 lalu semakin melekatkan tuduhan politik rasis yang dikembangkan oleh Trump. Terbunuhnya Floyd memancing aksi kerusuhan diberbagai tempat serta memancing solidaritas bagi Floyd terutama bagi masyarakat Afro- Amerika yang telah masuk Amerika sejak tahun 1600. Trump seakan lupa jika kelompok masyarakat ini jumlahnya signifikan sekitar 34,6 juta orang atau sekitar 12,3% dari jumlah total penduduk Amerika.
Kemenangan Joe Biden di Wisconsin, Georgia dan Nort Carolina menjadi bukti terjadinya proses delegitimasi terhadap Trump sebagai dampak dari berbagai kebijakan Trump yang membuat masyarakat bingung dan frustasi. Terbukti dengan serangkaian demo yang dinilai terbesar sepanjang sejarah Amerika. Berbagai fakta itulah yang telah menggerus kepercayaan publik. Alih-alih jargon American first policy itu bias membenahi perekonomian dalam negeri tetapi justru tak ubahnya sebagai manifesto politik rasis.***
Hingga artikel ini ditulis secara definitive belum keluar siapa pemenang Pilpres Amerika Serikat 2020. Tetapi Capres dari Partai Demokrat, Joe Biden sementara unggul jauh 264 suara electoral dibanding dengan perolehan Capres Partai Republik, Donald Trump yang baru memungut 214 suara electoral. Kemenangan Joe Biden di beberapa kantong pendukung Trump seperti Wisconsin dan Michigan menjadi sinyal bahaya sekaligus memberikan aura kemenangan bagi Biden untuk menduduki kursi Presiden Amerika yang ke 46. Praktis, Biden tinggal memerlukan 6 angka lagi untuk menjadi ‘USA One’ dengan perolehan suara tertinggi dalam sejarah Amerika.
Lonceng kekalahan bagi Trump kini mulai berdentang, seiring dengan langkahnya yang selalu kontroversial, songong dan kemlinthi (baca : adabnya kurang). Setidaknya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kekalahan Trump. Seperti diketahui, dalam Pilpres 2016 lalu Trump bisa menundukan Hillary Clinton meski mendapat perlawanan yang sengit. Bahkan hingga saat ini kemenangan Trump masih kontroversial serta menimbulkan spekulasi adanya keterlibatan Rusia dalam proses pemenangan itu.
Untuk meraih kemenangan itu Trump mengusung dan menyajikan jargon usang, ‘American first’ yang diupgrade menjadi ‘American first policy’. Tema kampanye nasionalisme ala Trump itu merupakan antithesis dari kebajikan Barrack Obama yang telah melakukan internasionalisme ekonomi dan politik. Dan terbukti menjelang masa berakhirnya kekuasaan Obama, Amerika terlilit krisis karena beban anggaran untuk pengerahan tentara Amerika di beberapa negara seperti Irak dan Afghanistan.
Di sisi lain, Amerika juga diterjang krisis bubble gum, karena dampak dari krisis kredit perumahan (subprime mortgage) serta bangkrutnya lembaga sekuritas Lehman Brothers, 2008 lalu Amerika berubah dari super power menjadi super losser (pecundang). Bahkan Amerika harus ngutang ke China untuk menambal defisit anggarannya, Tidak tanggung-tanggung utang Amerika ke China dalam bentuk US treasury itu segede gunung hingga mencapai US $ 1,12 triliun.
Maka tema kampanye Trump itu memperoleh momentum, dan menjanjikan angin segar bagi kepentingan ekonomi dan politik domestik. Karena Amerika memiliki ruang untuk membenahi perekonomiannya sendiri, sementara bagi negara-negara lain, Amerika seperti akan melakukan ‘pertobatan’ dari sikapnya yang suka kepo dan tengil dengan mau turut campur urusan negara lain. Dan itikad baik itu secara eksplisit diperlihatkan oleh Trump dengan menjalin komunikasi politik dengan Presiden Korea Utara, Kim Jong Un. Padahal sebelumnya Trump sempat menjuluki Korut dan Iran sebagai negara ‘poros setan’.
Tetapi konsistensi Trump dipertanyakan oleh masyarakat internasional setelah Amerika ditengarai terlibat dalam serangan terhadap Jenderal Iran, Qaseem Sulaimani. Hubungan Amerika dan China pun seperti Tom & Jerry, terutama setelah munculnya wabah Covid 19, bahkan ketika isu pemindahan Capitol, Ibu Kota Israel dari Tel Aviv ke Jerusaleem Timur, masyarakat internasionalpun bingung membaca gaya politik Trump. Ketika Indonesia menentang rencana itu, Trump justru menghardik Indonesia sebagai negara yang tidak tahu terima kasih dan mengancam akan membalasnya.
Gaya komunikasi politik Trump seperti ‘dewa mabuk’ itulah yang membuat banyak negara menjaga jarak. Tidak hanya dengan negara-negara dengan berbagai lembaga dunia seperti WHO dan PBB hubungan Amerika juga memburuk, apalagi Amerika sempat melakukan suspend terhadap bantuan keuangan PBB. Sikap itulah yang secara perlahan justru melunturkan hegemoni Amerika di mata dunia internasional. Sehingga banyak negara merasa tidak ‘happy’ dengan sikap Trump dan mereka lebih menginginkan Trump untuk tidak terpilih lagi.
Sementara kebijakan Trump dalam negeri juga memunculkan kontraksi yang hebat. Profesor ilmu politik dari Georgia State University, Charles Hankla mengkritik keras sepuluh langkah yang telah dilakukan oleh Trump seusai dilantik diantaranya adalah Amerika keluar dari Trans Pasific Patnershif (TPP) yang nota bene sudah tergabung dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), hanya karena dilandasi oleh sikap anti Beijing, ternyata justru berdampang negative terhadap perekonomian Amerika sendiri. Trump pun semakin kemlinthi (bertindak semaunya) dengan mengenakan tarif pajak 20% terhadap negara-negara yang telah menikmati surplus perdagangan dengan Amerika, kebijakan ini lagi-lagi justru membuat banyak negara ogah berurusan dengan Trump.
Untuk menterjemahkan ‘American first policy’ lagi-lagi Trump membuat blunder. Trump melakukan pembatasan imigrasi secara ketat, dan melarang orang dari banyak negara untuk masuk ke Amerika. Bahkan Trump sempat berniat untuk membangun tembok dan menutup perbatasan dengan Meksiko yang menjadi lubang keluar masuk imigran. Bahkan Trump membuat pernyataan yang membuat tersinggung banyak pihak dengan mengatakan ‘pengemismu, tetanggamu’. Sikap Trump yang songong dan kontroversial inilah yang membuat kalangan imigran menjadi dongkol terhadap Trump. Perlu diingat dari 328 juta jumlah penduduk Amerika, 51 juta diantaranya adalah kalangan imigran yang berasal dari negara-negara yang dilecehkan oleh Amerika seperti Meksiko, China, India, Kuba dll. Tentu mereka masih memiliki ikatan batin dengan negeri leluhurnya yang telah dilecehkan oleh Trump.
Isu rasisme selama pemerintahan Trump juga menguat dan meningkat tajam, apalagi pasca terbunuhnya George Floyd, Mei 2020 lalu semakin melekatkan tuduhan politik rasis yang dikembangkan oleh Trump. Terbunuhnya Floyd memancing aksi kerusuhan diberbagai tempat serta memancing solidaritas bagi Floyd terutama bagi masyarakat Afro- Amerika yang telah masuk Amerika sejak tahun 1600. Trump seakan lupa jika kelompok masyarakat ini jumlahnya signifikan sekitar 34,6 juta orang atau sekitar 12,3% dari jumlah total penduduk Amerika.
Kemenangan Joe Biden di Wisconsin, Georgia dan Nort Carolina menjadi bukti terjadinya proses delegitimasi terhadap Trump sebagai dampak dari berbagai kebijakan Trump yang membuat masyarakat bingung dan frustasi. Terbukti dengan serangkaian demo yang dinilai terbesar sepanjang sejarah Amerika. Berbagai fakta itulah yang telah menggerus kepercayaan publik. Alih-alih jargon American first policy itu bias membenahi perekonomian dalam negeri tetapi justru tak ubahnya sebagai manifesto politik rasis.***