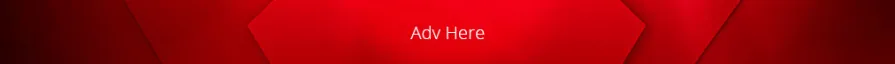Speechless
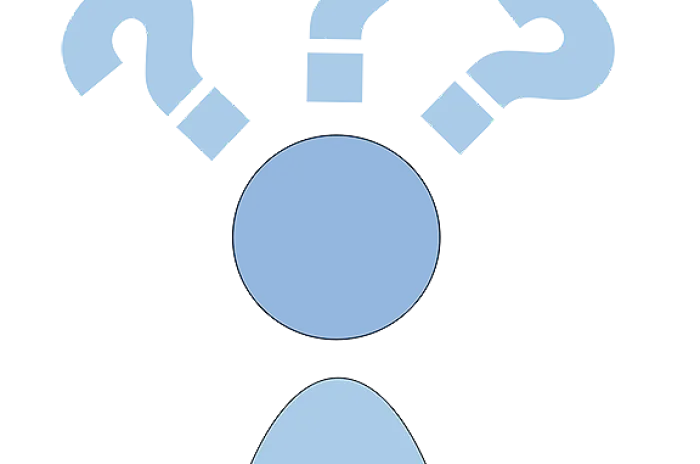
Oleh : Gugus Elmo Ra’is
Hari ini, tanggal 19 Mei, 22 tahun yang lalu, merupakan hari yang sangat krusial dan merupakan kulminasi terjadinya goro-goroyang berujung dengan lengser keprabon-nya salah satu diktator terlama yang ada di kolong langit yakni Soeharto. Gerakan penurunan penguasa Orde Baru yang dimotori oleh mahasiswa itu mengemban tiga amanah suci yakni turunkan Soeharto, berantas korupsi serta penegakkan supremasi hukum (law enforcement). Perjuangan yang kemudian dikenal sebagai gerakan reformasi itu merupakan akumulasi kemarahan masyarakat terhadap pusat kekuasaan yang cenderung korup dan tertutup.
Selama 32 tahun berkuasa, kekuasaan eksekutif cenderung hegemonik, (eksekutiv heavy), kondisi tanpa kontrol yang menabrak konsep pemisahan kekuasaan ala John Locke, trias politica. Nyaris tidak ada kontrol terhadap pusat kekuasaan, oleh legislatif maupun masyarakat. Begitu juga pers yang sesuai dengan premis Thomas Jefferson dan Samuel Huntington sebagai pilar demokrasi keempat telah lumpuh karena dibungkam sedemikian oleh rezim Orde Baru. Sehingga setelah Soeharto tumbang, untuk mengeliminir peluang terjadinya berbagai penyimpangan yang sama, perubahan sistem pemerintahan dianggap menjadi sebuah keniscayaan.
Namun pasca terjadinya berbagai perubahan yang diintrodusir melalui proses amandemen terhadap UUD 1945 itu justru melahirkan kompleksitas persoalan. Bangsa yang tengah mengalami genit-genit demokrasi ini justru sibuk ‘bertikai’ dalam setiap menyikapi persoalan dengan dalih kebebasan untuk berpendapat serta bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Seakan menegaskan jika bangsa ini saat ini tengah jalan di tempat karena terlalu asik cakar-cakaran, justru ketika bangsa lain sudah tuntas dalam menghadapi persoalan yang sama.
Bukti teraktual, kompleksitas persoalan yang berhulu dari perubahan sistem pemerintahan yang justru memperumit hierarki birokrasi adalah sistem otonomi daerah yang menghambat langkah pemerintah dalam penanganan bencana nasional seperti dalam menangani wabah Covid 19 serta bencana banjir. Pemerintah pusat tidak memiliki kendali terhadap pemerintah daerah, apalagi ketika pemerintah daerah merasa memiliki protokol penanganan bencana yang lebih baik ketimbang pemerintah pusat. Perebutan kewenangan itu memperoleh justifikasi dari beberapa UU yang memberikan proteksi terhadap para pihak. Seharusnya dalam kondisi bencana nasional itu ada regulasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan.
‘Perselisihan’ antara Menkeu dan Gubernur DKI dalam pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial/social safety net terhadap warga yang terdampak Covid 19, membuktikan adanya problema yang serius dalam sistem ketata-negaraan kita. Sehingga dengan sistem yang ada sekarang, memberi ruang kepada para pihak terutama yang berbeda afiliasi politiknya untuk ‘saling jegal’ dan saling mempermalukan yang pada akhirnya justru masyarakat terdampak bencana yang menjadi korban.
Selain munculnya kesan terjadinya perebutan kewenangan itu setiap instansi merasa berhak untuk membuat kebijakan sendiri-sendiri dalam menangani bencana. Apalagi dengan lemahnya koordinasi serta komunikasi membuat setiap kebijakan justru membuat masyarakat bingung. Sehingga masyarakat cenderung tidak patuh terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Entah itu karena minimnya sosialisasi kebijakan atau justru karena lemahnya leadership.
Kondisi ini menunjukan jika agenda reformasi itu yang menampakkan hasil baru sebatas penurunan Soeharto. Sementara dua agenda lainnya, pemberantasan korupsi dan penengakkan supremasi masih jauh panggang dari api. Kasus korupsi yang masuk kategori mega skandal masih tetap bermunculan. Sebutlah jaman SBY muncul kasus Century, Wisma Atlit dll, kini era Jokowi ini masih muncul kasus-kasus baru seperti Jiwasraya, kasus Asabri, kasus korupsi kondesat TPPI yang mulai mencuat tahun 2016 hingga saat ini belum juga tuntas.
Dalam penegakkan supremasi hukum juga banyak ironi yang terjadi. Ketika pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemerintah melarang masyarakat melanggar ketentuan itu dengan berbagai ancaman seperti sanksi denda maupun sanksi pidana, misalnya aparat memberikan denda terhadap panitia penutupan gerai makanan cepat saji di Sarinah, Jakarta Pusat. Aparat kembali menangkap Habib Bahar Smith yang terindikasi melakukan pelanggaran ketentuan asimilasi dengan memberikan pengajian. Bahkan MUI dengan susah payah membujuk umat Islam dengan mengeluarkan fatwa agar umat Islam tidak melakukan sholat ied di masjid, cukup di rumah saja.
Tetapi di kesempatan lain pemerintah justru menggelar konser untuk menggalang dana bantuan buat korban Covid 19. Meski konser itu bertujuan mulia, tetapi tetap saja memunculkan kesan adanya diskriminasi sekaligus standar ganda kebijakan. Berbagai realitas itulah yang membuat kita susah ngomong, (speechles).***
Hari ini, tanggal 19 Mei, 22 tahun yang lalu, merupakan hari yang sangat krusial dan merupakan kulminasi terjadinya goro-goroyang berujung dengan lengser keprabon-nya salah satu diktator terlama yang ada di kolong langit yakni Soeharto. Gerakan penurunan penguasa Orde Baru yang dimotori oleh mahasiswa itu mengemban tiga amanah suci yakni turunkan Soeharto, berantas korupsi serta penegakkan supremasi hukum (law enforcement). Perjuangan yang kemudian dikenal sebagai gerakan reformasi itu merupakan akumulasi kemarahan masyarakat terhadap pusat kekuasaan yang cenderung korup dan tertutup.
Selama 32 tahun berkuasa, kekuasaan eksekutif cenderung hegemonik, (eksekutiv heavy), kondisi tanpa kontrol yang menabrak konsep pemisahan kekuasaan ala John Locke, trias politica. Nyaris tidak ada kontrol terhadap pusat kekuasaan, oleh legislatif maupun masyarakat. Begitu juga pers yang sesuai dengan premis Thomas Jefferson dan Samuel Huntington sebagai pilar demokrasi keempat telah lumpuh karena dibungkam sedemikian oleh rezim Orde Baru. Sehingga setelah Soeharto tumbang, untuk mengeliminir peluang terjadinya berbagai penyimpangan yang sama, perubahan sistem pemerintahan dianggap menjadi sebuah keniscayaan.
Namun pasca terjadinya berbagai perubahan yang diintrodusir melalui proses amandemen terhadap UUD 1945 itu justru melahirkan kompleksitas persoalan. Bangsa yang tengah mengalami genit-genit demokrasi ini justru sibuk ‘bertikai’ dalam setiap menyikapi persoalan dengan dalih kebebasan untuk berpendapat serta bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Seakan menegaskan jika bangsa ini saat ini tengah jalan di tempat karena terlalu asik cakar-cakaran, justru ketika bangsa lain sudah tuntas dalam menghadapi persoalan yang sama.
Bukti teraktual, kompleksitas persoalan yang berhulu dari perubahan sistem pemerintahan yang justru memperumit hierarki birokrasi adalah sistem otonomi daerah yang menghambat langkah pemerintah dalam penanganan bencana nasional seperti dalam menangani wabah Covid 19 serta bencana banjir. Pemerintah pusat tidak memiliki kendali terhadap pemerintah daerah, apalagi ketika pemerintah daerah merasa memiliki protokol penanganan bencana yang lebih baik ketimbang pemerintah pusat. Perebutan kewenangan itu memperoleh justifikasi dari beberapa UU yang memberikan proteksi terhadap para pihak. Seharusnya dalam kondisi bencana nasional itu ada regulasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan.
‘Perselisihan’ antara Menkeu dan Gubernur DKI dalam pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial/social safety net terhadap warga yang terdampak Covid 19, membuktikan adanya problema yang serius dalam sistem ketata-negaraan kita. Sehingga dengan sistem yang ada sekarang, memberi ruang kepada para pihak terutama yang berbeda afiliasi politiknya untuk ‘saling jegal’ dan saling mempermalukan yang pada akhirnya justru masyarakat terdampak bencana yang menjadi korban.
Selain munculnya kesan terjadinya perebutan kewenangan itu setiap instansi merasa berhak untuk membuat kebijakan sendiri-sendiri dalam menangani bencana. Apalagi dengan lemahnya koordinasi serta komunikasi membuat setiap kebijakan justru membuat masyarakat bingung. Sehingga masyarakat cenderung tidak patuh terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Entah itu karena minimnya sosialisasi kebijakan atau justru karena lemahnya leadership.
Kondisi ini menunjukan jika agenda reformasi itu yang menampakkan hasil baru sebatas penurunan Soeharto. Sementara dua agenda lainnya, pemberantasan korupsi dan penengakkan supremasi masih jauh panggang dari api. Kasus korupsi yang masuk kategori mega skandal masih tetap bermunculan. Sebutlah jaman SBY muncul kasus Century, Wisma Atlit dll, kini era Jokowi ini masih muncul kasus-kasus baru seperti Jiwasraya, kasus Asabri, kasus korupsi kondesat TPPI yang mulai mencuat tahun 2016 hingga saat ini belum juga tuntas.
Dalam penegakkan supremasi hukum juga banyak ironi yang terjadi. Ketika pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemerintah melarang masyarakat melanggar ketentuan itu dengan berbagai ancaman seperti sanksi denda maupun sanksi pidana, misalnya aparat memberikan denda terhadap panitia penutupan gerai makanan cepat saji di Sarinah, Jakarta Pusat. Aparat kembali menangkap Habib Bahar Smith yang terindikasi melakukan pelanggaran ketentuan asimilasi dengan memberikan pengajian. Bahkan MUI dengan susah payah membujuk umat Islam dengan mengeluarkan fatwa agar umat Islam tidak melakukan sholat ied di masjid, cukup di rumah saja.
Tetapi di kesempatan lain pemerintah justru menggelar konser untuk menggalang dana bantuan buat korban Covid 19. Meski konser itu bertujuan mulia, tetapi tetap saja memunculkan kesan adanya diskriminasi sekaligus standar ganda kebijakan. Berbagai realitas itulah yang membuat kita susah ngomong, (speechles).***