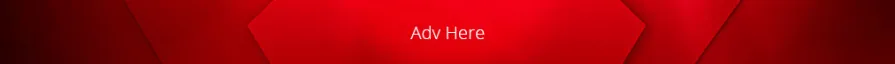Agama Dan Fatsoen Politik

Oleh : Gugus Elmo Rais
Setiap menghadapi hajatan politik, ada fenomena yang sangat menyedihkan dalam jagad politik nasional. Terjadi sikap saling hujat dan sikap saling melecehkan. Fenomena horor ini tidak terlepas buah dari proses amandemen terhadap UUD 1945 yang telah merubah banyak tatanan kenegaraan, baik dari Sistem Pemilu, Sistem Pemerintahan hingga Sistem Kepartaian. Sistem Pemilu dan menggunakan presidential threshold sebesar 20%, membuat masyarakat pemilih terfragmentasi menjadi dua kelompok yang saling berhadap-hadapan.
Maka mulailah terjadi sikap saling menghujat, black campaign, hoaxs dan seterusnya semenjak kedua pasangan ditetapkan sebagai pasangan Capres dan Cawapres. Bahkan hingga hajatan usai, ‘dendam politik’ masih sering mengendap di hati para konstituen. Sehingga Tanpa kita sadari sistem itulah yang menimbulkan sikap nyinyir dan apatisme politik yang mengubur obyektifitas. Sesuatu kebenaran yang dilakukan oleh lawan politiknya bisa dianggap sebagai hoaxs atau minimal sebagai pencitraan belaka. Intinya, setiap individu merasa hanya kelompoknyalah yang paling benar.
Yang lebih tragis, liberalisme politik melalui sistem Pilpres langsung itu ditunjang oleh sistem multipartai, yang pernah dikritik oleh Scott Mainwaring kurang cocok dengan Indonesia. Dengan UU No 2 tahun 2011 yang merupakan perubahan UU No 2 tahun 2008 tentang Parpol, siapapun bisa mendirikan partai asal memenuhi persyaratan administrasi dan ideologi. Perubahan sistem inilah yang memberi ruang tumbuh suburnya partai. Sekaligus memberikan ruang terhadap Ormas-ormas yang memiliki ideologi yang kurang sejalan dengan ideologi Pancasila, meski saat deklarasi mereka menyatakan jika Pancasila adalah ideologi yang final.
Maka sesungguhnya sistem multai partai inilah yang memberi ruang terhadap partai-partai untuk mengusung isu sektarian sekaligus sebagai upaya untuk membidik segmen konstituen yang khusus. Sehingga tak mengherankan bila jagad politik nasional akan selalu dijejali isu-isu sektarian yang akan direspon menggunakan isu sektarian juga oleh lawan politiknya yang pada akhirnya bisa menjurus SARA dan disintegrasi bangsa. Fenomena meningkatnya politik aliran itulah yang saat ini menggejala.
Meningkatnya gejala politik aliran itu menimbulkan sebuah hipotesa baru oleh sebagian orang dan tokoh yang mengatakan jika kondisi saat ini telah terjadi benturan peradaban seperti yang pernah disinggung oleh Samuel Hutington dalam bukunya, The Clash of Sivilization and The Remarking of World Order (1996). Dalam buku itu Hutington mendeskripsikan jika pasca berakhirnya perang dingin terjadi benturan peradaban yang berlandaskan pada nilai-nilai agama, suku maupun ras (SARA). Sekilas hipotesa itu seakan benar berdasarkan bukti empirik dengan munculnya kasus-kasus ujaran kebencian (hate speech) yang menguat secara siginifikan dalam beberapa waktu terakhir. Apalagi dengan munculnya beberapa teror yang berlabelkan agama.
Tetapi kalau kita kaji dan telaah lebih jauh tesis Hutington itu sangat konyol dan gegabah. Pada tataran nilai, semua keyakinan atau agama mengajarkan kedamaian. Dan terbukti hingga saat ini dialog antar agama berjalan secara intens untuk mencarikan persamaan persepsi dalam hidup berbangsa dan bernegara. Islam sebagai sebuah agama yang sering digambarkan oleh Hutington sebagai aggression and hostility (agresi dan ancaman), terutama bagi peradaban Barat pada faktanya kini justru sangat diterima di negara-negara Eropa dan Amerika Latin.
Bahkan secara akademis, saat ini banyak sarjana-sarjana Barat yang mengkaji Islam secara objektif, dengan menjadikan Al-Quran dan Hadits sebagai sumber pertama dan utama. Di Amerika Serikat misalnya, ada Prof. John L. Esposito dan Prof. Michael Fischer; di Jerman juga ada ahli sufi, Annemarie Schimmel dan Dr. Murad Hofmann; di Inggris pun ada Prof. Francis Robinson, Prof. Hastings, dan lain-lain. Ironisnya, teori keadilan yang diklaim oleh Havard Law School sebagai teori keadilan terbaik sepanjang masa justru berasal dari frasa yang sederhana dalam Al Qur’an terutama Surat An Nissa 135 yang menyatakan “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya,”.
Secara obyektif, tesis Hutington itu harus dinyatakan gagal. Karena konflik yang terjadi di beberapa negara itu sesungguhnya bukan konflik nilai tetapi semata-mata konflik kepentingan yang dibungkus dan dilabeli nilai-nilai agama. Sebutlah konflik di Jalur Gaza antara Israel dan Palestina, konflik ISIS di Suriah adalah konflik kepentingan ekonomi yang dilabeli agama, konflik di Irlandia, antara Katolik dan Protestan. Termasuk perang besar antara Irak melawan sekutu, karena Saddam tidak merepresentasikan Islam melawan Barat, tetapi lebih pada kepentingan ekonomi para pihak
Dengan adanya hipotesa Hutington itu serta munculnya fenomena radikalisme dan politik aliran mengapungkan sebuah pertanyaan, bagaimana sesungguhnya hubungan antara agama dengan politik yang dalam hal ini diwakili oleh sistem demokrasi sebagai sebuah sistem yang paling ideal seperti tesisnya Thomas Jefferson. Apalagi sebagian ulama garis keras menganggap demokrasi adalah sistem pemerintahan yang thogut karena jauh dari agama (sekuler), dan meyakini suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox dei). Di mata ulama garis keras, mengimani suara rakyat itu adalah salah satu bentuk kesesatan berpikir.
Esensi sistem pemerintahan demokrasi dalam Islam sendiri menurut hemat saya setidaknya berdasarkan tiga unsur yakni perintah untuk, 1. Beramar mar’ruf nahi munkar (perintah untuk melakukan sikap saling koreksi), 2. Fastabiqul khairat (berlomba-lomba dalam kebajikan), serta 3. Perintah bermusyawarah. Ketiga elemen itu harus dijalankan secara berkesinambungan dengan berdasarkan mekanisme yang telah disepakati bersama. Sehingga akan tercapai sebuah negeri yang balhatun thoyibatun warrobun gofur (negeri yang baik dan diampuni oleh Tuhan), atau dalam floklor Jawa dikenal dengan istilah gemah ripah loh jinawi.
Bila kita mengutip Konsep Amar Ma’ruf Nahi Munkar Al-Ghazali dalam Kitab Ihya’ ‘Ulumuddin dan Relevansinya dengan Dakwah Zaman Modern di Indonesia tulisan Mar’atus Sholihah (2019: 41), maka amar ma’ruf nahi munkar adalah ajakan untuk berbuat kebajikan dan kasih sayang dalam melaksanakan rencana-rencana perbaikan akhlak serta mencegah perbuatan-perbuatan kejahatan yang merusak akhlak. Konsep ini bisa disublimasikan dalam bentuk fungsi chek and balance yang dilakukan oleh parlemen (sesuai konsep trias politica John Locke) serta komponen masyarakat lainnya seperti pers dan NGO.
Dalam Islam perintah untuk beramar ma’ruf nahi munkar telah termakthub dalam surat Al Imran ayat 104, Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk senantiasa mencegah kemunkaran dan mengajak berbuat baik. Ini merupakan prinsip dasar agama Islam yang harus diamalkan setiap Muslim. Siapapun yang melakukannya akan menggapai surga yang penuh kenikmatan. “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang yang beruntung.” (QS Al Imran ayat 104).
Kedua adalah perintah untuk berfastabiqul khairat (berlomba-lomba dalam kebajikan). Implementasi dari konsep ini dalam kehidupan bernegara bisa dimaknai bahwa siapapun dari kelompok apapun, baik yang pro atau anti pemerintah berhak untuk berbuat baik. Selama perbuatannya itu dilandasi oleh niat baik dan tidak melanggar norma-norma kesusilaan layak untuk diberi apresiasi. Masyarakat harus kritis tetapi juga tidak boleh nyinyir terhadap semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Begitu juga sebaliknya kita juga tidak boleh apatis atas apa yang dilakukan oleh pemimpin atau tokoh-tokoh yang berbeda afiliasi politiknya dengan afiliasi politik pemerintah.
Secara eksplisit, ajakan untuk selalu berlomba dalam kebaikan atau yang juga disebut fastabiqul khairat itu telah termakthub dalam Surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi,”Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya (pada hari kiamat). Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu,”.
Sementara elemen ketiga adalah perintah untuk bermusyawarah. Dalam hukum ketata negaraan kita maka mekanisme pengambilan keputusan itu adalah musyawarah untuk mengambil mufakat. Secara normatif ketentuan yang mengatur musyawarah untuk memperoleh mufakat itu ada dalam Pasal 2 UUD 1945, meski pada prakteknya masih sangat rumit dan kompleks. Dalam Islam sendiri banyak ayat yang memerintahkan kita untuk mengambil mekanisme musyawarah dalam proses pengambilan keputusan, seperti dalam surat Al Syura 38 atau Surat Al Imran 135 yang berbunyi, “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya,”.
Sesuai dengan uraian diatas jelaslah jika Islam tidak anti sama sekali terhadap sistem demokrasi. Tetapi memang ada segelintir kelompok yang memanipulasi agama atau justru sebaliknya ada kelompok yang tidak suka dengan agama tertentu yang memanipulasi fakta untuk mendiskreditkan agama serta memunculkan sentiment anti terhadap kelompok agama tertentu. Bahkan nilai-nilai agama turut berkontribusi terhadap pembentukan adab berpolitik yang santun dan elegan.
Berdasarkan hipotesa itulah diperlukan kejernihan berpikir dan obyektifitas untuk mengambil tindakan. Karena ketika kita salah bersikap, maka kita akan terjebak dan terpapar virus proxy war. Terjadinya peperangan yang sejatinya adalah adanya kepentingan asing yang sering menggonakan istilah nabok nyilih tangan (menyerang untuk mengadu domba kelompok tertentu dengan meminjam kekuatan pihak lain).
Perang tanpa bentuk itulah yang kini menghantui Bangsa Indonesia. Proxy war merupakan perubahan evolutif atau transformasi dari sistem politik devide et impera yang muncul pada abad ke 15 yang sering digunakan oleh bangsa-bangsa kolonialis. Namun perubahan budaya politik di Semenanjung Arab membuktikan jika proxy war kini jauh lebih efektif untuk menggoyang suatu rezim atau pemerintahan. Bahkan bisa menghancurkan pondasi kebangsaan suatu negara.
Menurut Joseph Nye dalam bukunya Soft Power Foreign Policy (1990), proxy war bisa dilakukan menggunakan dua pendekatan, yaitu dengan hard power atau melalui kekuatan militer dan politik. Serta melalui soft power dengan memanfaatkan tekanan di bidang ekonomi, lembaga donor, atau melalui teknologi informasi. Fenomena seperti tesisnya Joseph Nye itulah yang saat ini terjadi di Indonesia, banyak agenda asing yang terselip dibalik proses demokratisasi maupun investasi asing. Salah satu contohnya adalah beberapa waktu kita terlibat ketegangan politik terkait adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China. Masyarakat China yang memperoleh manfaatnya, tetapi justru kita yang saling berkelahi.
Proxy War seakan memperoleh momentum apalagi ditunjang dengan kemajuan teknologi informasi. Penyebaran disinformasi menggunakan Medsos terbukti efektif untuk menggoyang semangat kesatuan dan persatuan bangsa. Apalagi disaat menghadapi event-event politik. Sering terjadi sikap saling persekusi atas dasar informasi yang salah (hoaxs). Isu-isu tentang perubahan ideologi menjadi dagangan yang paling laris untuk memancing emosi massa.
Apabila fenomena ini tidak segera dihentikan, maka disintegrasi bangsa hanya tinggal menunggu waktu. Lalu cara apakah yang paling efektif untuk melawan proxy war secara bersama-sama ?. Untuk menangkal serangan proksi itu menurut R.L. Armitage dan Nye bisa dilakukan cara membangun kekuatan cerdas (smart power) yang mampu menghalau dua pendekatan proksi tersebut. Smart power sendiri merupakan gabungan dari hard power dan soft power. Cara yang cerdas adalah dengan tidak terpancing dan terlibat sikap saling tuduh dan hujat terutama melalui media sosial. Para pihak harus menahan diri untuk tidak menuduh kelompok lain sebagai kaki tangan komunis ataupun kaki tangan kadal gurun.
Karena sejelek apapun mereka adalah anak bangsa yang perlu dirangkul sebagai doktrin nasionalisme yang sesungguhnya, seperti halnya tesis Ernest Renan dan Otto Bauer, jika suatu bangsa berdiri atas kehendak bersatu (le desire d’etre ensemble). Doktrin nasionalisme itulah yang dijadikan mantra oleh Soekarno untuk menghimpun ribuan suku dan bangsa ini menjadi satu pangkuan bumi pertiwi yakni Bangsa Indonesia.
Sangatlah memalukan jika ada orang yang mengklaim Soekarnois dan mencintai NKRI dengan harga mati, tetapi masih juga rajin menghujat kelompok lain. Ingat, Soekarno telah mengambil resiko tidak popular dengan melakukan ujicoba sinkretisme ideologi dengan menyatukan nasionalisme, agama, dan komunis (Nasakom) menjadi satu kesatuan, tetapi kini para penerusnya justru berusaha saling meniadakan.
Pancasila sebagai ideologi itu sudah final. Dan sering saya tulis bahwa Pancasila itu adalah intisari peradaban bangsa ini. Karena Pancasila lahir dari dealektika budaya yang panjang, dan merupakan konsensus bersama bangsa ini melalui wakil-wakil mereka yang ada di BPUPKI. Meski Soekarno punya peran yang sangat dominan, tetapi kita tidak bisa menafikan peran dari tokoh-tokoh lain. Maka tantangan terbesar bangsa ini bukan merumuskan falsafah baru, tetapi bagaimana cara memahami dan mengamalkan falsafah itu sendiri. Salah satunya adalah sila Persatuan Indonesia, dengan cara bersama-sama menangkal terjadinya proxy war.***
Setiap menghadapi hajatan politik, ada fenomena yang sangat menyedihkan dalam jagad politik nasional. Terjadi sikap saling hujat dan sikap saling melecehkan. Fenomena horor ini tidak terlepas buah dari proses amandemen terhadap UUD 1945 yang telah merubah banyak tatanan kenegaraan, baik dari Sistem Pemilu, Sistem Pemerintahan hingga Sistem Kepartaian. Sistem Pemilu dan menggunakan presidential threshold sebesar 20%, membuat masyarakat pemilih terfragmentasi menjadi dua kelompok yang saling berhadap-hadapan.
Maka mulailah terjadi sikap saling menghujat, black campaign, hoaxs dan seterusnya semenjak kedua pasangan ditetapkan sebagai pasangan Capres dan Cawapres. Bahkan hingga hajatan usai, ‘dendam politik’ masih sering mengendap di hati para konstituen. Sehingga Tanpa kita sadari sistem itulah yang menimbulkan sikap nyinyir dan apatisme politik yang mengubur obyektifitas. Sesuatu kebenaran yang dilakukan oleh lawan politiknya bisa dianggap sebagai hoaxs atau minimal sebagai pencitraan belaka. Intinya, setiap individu merasa hanya kelompoknyalah yang paling benar.
Yang lebih tragis, liberalisme politik melalui sistem Pilpres langsung itu ditunjang oleh sistem multipartai, yang pernah dikritik oleh Scott Mainwaring kurang cocok dengan Indonesia. Dengan UU No 2 tahun 2011 yang merupakan perubahan UU No 2 tahun 2008 tentang Parpol, siapapun bisa mendirikan partai asal memenuhi persyaratan administrasi dan ideologi. Perubahan sistem inilah yang memberi ruang tumbuh suburnya partai. Sekaligus memberikan ruang terhadap Ormas-ormas yang memiliki ideologi yang kurang sejalan dengan ideologi Pancasila, meski saat deklarasi mereka menyatakan jika Pancasila adalah ideologi yang final.
Maka sesungguhnya sistem multai partai inilah yang memberi ruang terhadap partai-partai untuk mengusung isu sektarian sekaligus sebagai upaya untuk membidik segmen konstituen yang khusus. Sehingga tak mengherankan bila jagad politik nasional akan selalu dijejali isu-isu sektarian yang akan direspon menggunakan isu sektarian juga oleh lawan politiknya yang pada akhirnya bisa menjurus SARA dan disintegrasi bangsa. Fenomena meningkatnya politik aliran itulah yang saat ini menggejala.
Meningkatnya gejala politik aliran itu menimbulkan sebuah hipotesa baru oleh sebagian orang dan tokoh yang mengatakan jika kondisi saat ini telah terjadi benturan peradaban seperti yang pernah disinggung oleh Samuel Hutington dalam bukunya, The Clash of Sivilization and The Remarking of World Order (1996). Dalam buku itu Hutington mendeskripsikan jika pasca berakhirnya perang dingin terjadi benturan peradaban yang berlandaskan pada nilai-nilai agama, suku maupun ras (SARA). Sekilas hipotesa itu seakan benar berdasarkan bukti empirik dengan munculnya kasus-kasus ujaran kebencian (hate speech) yang menguat secara siginifikan dalam beberapa waktu terakhir. Apalagi dengan munculnya beberapa teror yang berlabelkan agama.
Tetapi kalau kita kaji dan telaah lebih jauh tesis Hutington itu sangat konyol dan gegabah. Pada tataran nilai, semua keyakinan atau agama mengajarkan kedamaian. Dan terbukti hingga saat ini dialog antar agama berjalan secara intens untuk mencarikan persamaan persepsi dalam hidup berbangsa dan bernegara. Islam sebagai sebuah agama yang sering digambarkan oleh Hutington sebagai aggression and hostility (agresi dan ancaman), terutama bagi peradaban Barat pada faktanya kini justru sangat diterima di negara-negara Eropa dan Amerika Latin.
Bahkan secara akademis, saat ini banyak sarjana-sarjana Barat yang mengkaji Islam secara objektif, dengan menjadikan Al-Quran dan Hadits sebagai sumber pertama dan utama. Di Amerika Serikat misalnya, ada Prof. John L. Esposito dan Prof. Michael Fischer; di Jerman juga ada ahli sufi, Annemarie Schimmel dan Dr. Murad Hofmann; di Inggris pun ada Prof. Francis Robinson, Prof. Hastings, dan lain-lain. Ironisnya, teori keadilan yang diklaim oleh Havard Law School sebagai teori keadilan terbaik sepanjang masa justru berasal dari frasa yang sederhana dalam Al Qur’an terutama Surat An Nissa 135 yang menyatakan “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya,”.
Secara obyektif, tesis Hutington itu harus dinyatakan gagal. Karena konflik yang terjadi di beberapa negara itu sesungguhnya bukan konflik nilai tetapi semata-mata konflik kepentingan yang dibungkus dan dilabeli nilai-nilai agama. Sebutlah konflik di Jalur Gaza antara Israel dan Palestina, konflik ISIS di Suriah adalah konflik kepentingan ekonomi yang dilabeli agama, konflik di Irlandia, antara Katolik dan Protestan. Termasuk perang besar antara Irak melawan sekutu, karena Saddam tidak merepresentasikan Islam melawan Barat, tetapi lebih pada kepentingan ekonomi para pihak
Dengan adanya hipotesa Hutington itu serta munculnya fenomena radikalisme dan politik aliran mengapungkan sebuah pertanyaan, bagaimana sesungguhnya hubungan antara agama dengan politik yang dalam hal ini diwakili oleh sistem demokrasi sebagai sebuah sistem yang paling ideal seperti tesisnya Thomas Jefferson. Apalagi sebagian ulama garis keras menganggap demokrasi adalah sistem pemerintahan yang thogut karena jauh dari agama (sekuler), dan meyakini suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox dei). Di mata ulama garis keras, mengimani suara rakyat itu adalah salah satu bentuk kesesatan berpikir.
Esensi sistem pemerintahan demokrasi dalam Islam sendiri menurut hemat saya setidaknya berdasarkan tiga unsur yakni perintah untuk, 1. Beramar mar’ruf nahi munkar (perintah untuk melakukan sikap saling koreksi), 2. Fastabiqul khairat (berlomba-lomba dalam kebajikan), serta 3. Perintah bermusyawarah. Ketiga elemen itu harus dijalankan secara berkesinambungan dengan berdasarkan mekanisme yang telah disepakati bersama. Sehingga akan tercapai sebuah negeri yang balhatun thoyibatun warrobun gofur (negeri yang baik dan diampuni oleh Tuhan), atau dalam floklor Jawa dikenal dengan istilah gemah ripah loh jinawi.
Bila kita mengutip Konsep Amar Ma’ruf Nahi Munkar Al-Ghazali dalam Kitab Ihya’ ‘Ulumuddin dan Relevansinya dengan Dakwah Zaman Modern di Indonesia tulisan Mar’atus Sholihah (2019: 41), maka amar ma’ruf nahi munkar adalah ajakan untuk berbuat kebajikan dan kasih sayang dalam melaksanakan rencana-rencana perbaikan akhlak serta mencegah perbuatan-perbuatan kejahatan yang merusak akhlak. Konsep ini bisa disublimasikan dalam bentuk fungsi chek and balance yang dilakukan oleh parlemen (sesuai konsep trias politica John Locke) serta komponen masyarakat lainnya seperti pers dan NGO.
Dalam Islam perintah untuk beramar ma’ruf nahi munkar telah termakthub dalam surat Al Imran ayat 104, Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk senantiasa mencegah kemunkaran dan mengajak berbuat baik. Ini merupakan prinsip dasar agama Islam yang harus diamalkan setiap Muslim. Siapapun yang melakukannya akan menggapai surga yang penuh kenikmatan. “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang yang beruntung.” (QS Al Imran ayat 104).
Kedua adalah perintah untuk berfastabiqul khairat (berlomba-lomba dalam kebajikan). Implementasi dari konsep ini dalam kehidupan bernegara bisa dimaknai bahwa siapapun dari kelompok apapun, baik yang pro atau anti pemerintah berhak untuk berbuat baik. Selama perbuatannya itu dilandasi oleh niat baik dan tidak melanggar norma-norma kesusilaan layak untuk diberi apresiasi. Masyarakat harus kritis tetapi juga tidak boleh nyinyir terhadap semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Begitu juga sebaliknya kita juga tidak boleh apatis atas apa yang dilakukan oleh pemimpin atau tokoh-tokoh yang berbeda afiliasi politiknya dengan afiliasi politik pemerintah.
Secara eksplisit, ajakan untuk selalu berlomba dalam kebaikan atau yang juga disebut fastabiqul khairat itu telah termakthub dalam Surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi,”Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya (pada hari kiamat). Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu,”.
Sementara elemen ketiga adalah perintah untuk bermusyawarah. Dalam hukum ketata negaraan kita maka mekanisme pengambilan keputusan itu adalah musyawarah untuk mengambil mufakat. Secara normatif ketentuan yang mengatur musyawarah untuk memperoleh mufakat itu ada dalam Pasal 2 UUD 1945, meski pada prakteknya masih sangat rumit dan kompleks. Dalam Islam sendiri banyak ayat yang memerintahkan kita untuk mengambil mekanisme musyawarah dalam proses pengambilan keputusan, seperti dalam surat Al Syura 38 atau Surat Al Imran 135 yang berbunyi, “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya,”.
Sesuai dengan uraian diatas jelaslah jika Islam tidak anti sama sekali terhadap sistem demokrasi. Tetapi memang ada segelintir kelompok yang memanipulasi agama atau justru sebaliknya ada kelompok yang tidak suka dengan agama tertentu yang memanipulasi fakta untuk mendiskreditkan agama serta memunculkan sentiment anti terhadap kelompok agama tertentu. Bahkan nilai-nilai agama turut berkontribusi terhadap pembentukan adab berpolitik yang santun dan elegan.
Berdasarkan hipotesa itulah diperlukan kejernihan berpikir dan obyektifitas untuk mengambil tindakan. Karena ketika kita salah bersikap, maka kita akan terjebak dan terpapar virus proxy war. Terjadinya peperangan yang sejatinya adalah adanya kepentingan asing yang sering menggonakan istilah nabok nyilih tangan (menyerang untuk mengadu domba kelompok tertentu dengan meminjam kekuatan pihak lain).
Perang tanpa bentuk itulah yang kini menghantui Bangsa Indonesia. Proxy war merupakan perubahan evolutif atau transformasi dari sistem politik devide et impera yang muncul pada abad ke 15 yang sering digunakan oleh bangsa-bangsa kolonialis. Namun perubahan budaya politik di Semenanjung Arab membuktikan jika proxy war kini jauh lebih efektif untuk menggoyang suatu rezim atau pemerintahan. Bahkan bisa menghancurkan pondasi kebangsaan suatu negara.
Menurut Joseph Nye dalam bukunya Soft Power Foreign Policy (1990), proxy war bisa dilakukan menggunakan dua pendekatan, yaitu dengan hard power atau melalui kekuatan militer dan politik. Serta melalui soft power dengan memanfaatkan tekanan di bidang ekonomi, lembaga donor, atau melalui teknologi informasi. Fenomena seperti tesisnya Joseph Nye itulah yang saat ini terjadi di Indonesia, banyak agenda asing yang terselip dibalik proses demokratisasi maupun investasi asing. Salah satu contohnya adalah beberapa waktu kita terlibat ketegangan politik terkait adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China. Masyarakat China yang memperoleh manfaatnya, tetapi justru kita yang saling berkelahi.
Proxy War seakan memperoleh momentum apalagi ditunjang dengan kemajuan teknologi informasi. Penyebaran disinformasi menggunakan Medsos terbukti efektif untuk menggoyang semangat kesatuan dan persatuan bangsa. Apalagi disaat menghadapi event-event politik. Sering terjadi sikap saling persekusi atas dasar informasi yang salah (hoaxs). Isu-isu tentang perubahan ideologi menjadi dagangan yang paling laris untuk memancing emosi massa.
Apabila fenomena ini tidak segera dihentikan, maka disintegrasi bangsa hanya tinggal menunggu waktu. Lalu cara apakah yang paling efektif untuk melawan proxy war secara bersama-sama ?. Untuk menangkal serangan proksi itu menurut R.L. Armitage dan Nye bisa dilakukan cara membangun kekuatan cerdas (smart power) yang mampu menghalau dua pendekatan proksi tersebut. Smart power sendiri merupakan gabungan dari hard power dan soft power. Cara yang cerdas adalah dengan tidak terpancing dan terlibat sikap saling tuduh dan hujat terutama melalui media sosial. Para pihak harus menahan diri untuk tidak menuduh kelompok lain sebagai kaki tangan komunis ataupun kaki tangan kadal gurun.
Karena sejelek apapun mereka adalah anak bangsa yang perlu dirangkul sebagai doktrin nasionalisme yang sesungguhnya, seperti halnya tesis Ernest Renan dan Otto Bauer, jika suatu bangsa berdiri atas kehendak bersatu (le desire d’etre ensemble). Doktrin nasionalisme itulah yang dijadikan mantra oleh Soekarno untuk menghimpun ribuan suku dan bangsa ini menjadi satu pangkuan bumi pertiwi yakni Bangsa Indonesia.
Sangatlah memalukan jika ada orang yang mengklaim Soekarnois dan mencintai NKRI dengan harga mati, tetapi masih juga rajin menghujat kelompok lain. Ingat, Soekarno telah mengambil resiko tidak popular dengan melakukan ujicoba sinkretisme ideologi dengan menyatukan nasionalisme, agama, dan komunis (Nasakom) menjadi satu kesatuan, tetapi kini para penerusnya justru berusaha saling meniadakan.
Pancasila sebagai ideologi itu sudah final. Dan sering saya tulis bahwa Pancasila itu adalah intisari peradaban bangsa ini. Karena Pancasila lahir dari dealektika budaya yang panjang, dan merupakan konsensus bersama bangsa ini melalui wakil-wakil mereka yang ada di BPUPKI. Meski Soekarno punya peran yang sangat dominan, tetapi kita tidak bisa menafikan peran dari tokoh-tokoh lain. Maka tantangan terbesar bangsa ini bukan merumuskan falsafah baru, tetapi bagaimana cara memahami dan mengamalkan falsafah itu sendiri. Salah satunya adalah sila Persatuan Indonesia, dengan cara bersama-sama menangkal terjadinya proxy war.***