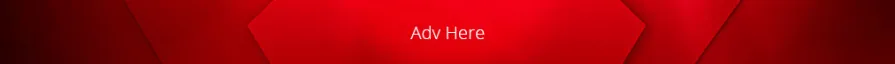Fenomena Banteng Tarung Sak Kandang

Oleh : Gugus Elmo Rais
Dinamika politik dalam beberapa waktu terakhir ada indikasi muncul episentrum politik baru yang pasti bakal seru. Dan apabila managemen konflik itu tidak dikelola dengan baik oleh para petinggi PDIP, dinamika politik itu berpotensi akan memunculkan ‘goro-goro’ yang bila kita meminjam istilah Joyoboyo sebagai ‘banteng tarung sak kandang’ (konflik sesama kader). Terutama menjelang suksesi kepemimpinan nasional 2024 nanti, mengingat Jokowi tidak mungkin mencalonkan diri lagi. Karena memang konstitusi telah membatasi hanya dua periode.
Sebagai ruling party tentu saja PDIP ingin melanjutkan kekuasaan sekaligus mempertahankan kesinambungan program sesuai dengan platform dan visi misi partai. Mereka pasti telah melakukan berbagai macam simulasi dan kalkulasi politik yang matang, kira-kira strategi apa dan siapa serta berpasangan dengan siapa kader yang akan dipasang di Pilpres 2024 nanti. Tingkat elektabilitas serta konstelasi politik mutakhir tentu saja menjadi barometer utama dalam mengusung calon dalam palagan Pilpres nanti.
Dilemanya, dalam internal PDIP saat ini belum muncul nama yang memiliki tingkat elektabilitas yang menonjol. Hanya ada dua nama yang sudah mulai masuk dalam bursa dengan tingkat elektabilitas yang memadai yakni Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo serta Ketua DPR RI, Puan Maharani. Ironisnya, kedua tokoh itu justru sempat terlibat friksi, meski eskalasinya tidak meluas. Sementara PDIP juga tidak mungkin berharap lagi munculnya rising star dan ‘kabayan saba kota’ seperti halnya Jokowi yang bisa melambung popularitasnya dalam jangka waktu yang pendek. Meski Jokowi bukanlah kader murni partai.
Untuk memberikan tongkat komando dan estafet kepemimpinan tentu saja bukan perkara mudah bagi Joko Widodo untuk mendapuk Ganjar Pranowo sebagai ‘sang penerus’. Meski keduanya memiliki kedekatan emosional sebagai sesama ‘wong ndeso’ yang tidak memiliki ‘darah biru’ dan sama-sama Soekarnois dan penganut marhaenisme. Jokowi pasti tidak bisa serta merta memberikan tongkat komando, karena ketentuan politik sekarang mengharuskan setiap calon memilki kendaraan politik dengan tingkat keterpilihan 20% (presindential tresshold). Karena tentu saja itu akan mendapat tentangan dari elit-elit PDIP yang cenderung mendukung Puan Maharani untuk maju sebagai Capres edisi yang akan datang.
Perbedaan orientasi politik itulah yang saat ini mulai menimbulkan gejala ‘banteng tarung sak kandang’. Kini semakin sering kader PDIP justru mengkritik keras kebijakan-kebijakan Jokowi. Meski sikap kritis tetapi tetap loyal adalah sebuah keniscyaan seorang politisi, tetapi tetap saja akan menimbulkan penafsiran jika jelang Pilpres 2024 banyak politisi pendukung pemerintah yang secara perlahan mulai balik kanan dan berubah haluan. Karena pasca 2024 pasti Jokowi tidak lagi menjadi icon politik.
Semua bisa saja berasumsi jika tidak ada ‘pesta yang tak usai’ untuk menggambarkan posisi Jokowi dan para pendukungnya jelang Pilpres 2024. Tetapi mengabaikan fakta politik jika kini arus bawah menghendaki Ganjar Pranowo sebagai sosok ‘sang penerus’ bisa menjadi tindakan yang gegabah. Karena secara de facto gerakan arus bawah yang kini mendukung Ganjar semakin gencar dan kuat.
Sehingga berpotensi akan membuat PDIP terpecah belah. Kondisi itu tentu akan memberikan benefit politik terhadap kubu lawan yang akan bertarung dalam Pilpres 2024. Kasus Tarmidji Soehardjo, Kader PDIP yang tersisih jelang Pilgub DKI Jakarta karena Ketum PDIP lebih memilih Sutiyoso, tentu saja tidak bisa dijadikan referensi jika mengabaikan eksistensi Ganjar akan tidak berpengaruh terhadap suara partai. Karena gerakan pendukung Ganjar kini sudah massif dan terstruktur.
Maka menjelang suksesi kepemimpinan nasional melalui Pilpres 2024, sangat menarik bila kita membaca sejarah Partai PDI Perjuangan (PDI-P). Embrio partai berlambang banteng moncong putih ini adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang berdiri pada tahun 1973 yang merupakan fusi dari sejumlah partai berbasis nasionalis seperti Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Murba. Selain fusi dari golongan nasionalis, PDI juga terdiri dari fusi partai berbasis agama yakni Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik
Kendali partai ini kembali ke tangan trah Soekarno, pada 1993 setelah Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi ketua umum hingga periode 1998. Namun, terpilihnya Megawati tak mendapat restu dari pemerintahan Orde Baru sehingga muncul konflik internal. Pada 1996, PDI menggelar kongres pemilihan ketua umum yang ditentang Megawati. Kongres tersebut lantas memilih Soerjadi sebagai ketua umum.
Setelah terjadi konflik berdarah-darah pada bulan Juli 1996 dengan peristiwa yang kita kenal Kudatuli serta konflik kepengurusan dengan Kubu Budi Harjono, PDI bermetamorfosa menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri. Metamorfose PDI menjadi PDIP pada tanggal 14 Februari 1999 itu tidak terlepas adanya disparitas antara fakta de jure dan de facto. Secara de jure memang pemerintah mengakui kubu Budi Harjono karena memang adanya hidden agenda pemerintah saat itu, tetapi secara de facto, gerakan wong cilik atau arus bawah yang mendukung PDI-P semakin membesar dan tak terbendung.
Klimaks dukungan masyarakat terhadap PDIP sebagai bagian dari romantisme masa lalu karena kebesaran PNI itu terjadi dalam Pemilu tahun 1999. Saat itu partai yang sering mempersonifikasi sebagai partai wong cilik ini berhasil meraup suara hingga 33,74 persen suara dengan 153 kursi di DPR. Ironisnya, dengan perolehan suara segede itu, PDIP tidak mampu mengantarkan Ketumnya sebagai Presiden RI yang ke 4 dan hanya menduduki kursi RI 2. Meski ‘kecelakaan sejarah’ itu tidak terlepas dari ‘telikungan maut’ dari kaukus politik poros tengah yang dikomandoi oleh Amien Rais CS.
Dalam Pemilu selanjutnya tahun 2004, perolehan suara PDIP kembali ngedrop dan hanya mendulang suara sebanyak 18,53 persen suara dengan 109 kursi di DPR. Dan lagi–lagi, sang Ketum yang berpasangan Hazim Muzadi, harus mengubur keinginannya untuk duduk di singgasana RI sekaligus mengembalikan marwah PDIP sebagai partai besar, menjadi gagal karena kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK).
Seiring dengan luruhnya hegemoni Partai Demokrat serta tertutupnya peluang SBY untuk menjadi Capres lagi pada Pemilu 2014, PDIP kembali memperoleh momentum. Meski perolehan suara PDI-P dalam Pemilu 2014 hanya sebesar 18,95 persen suara dengan raihan 109 kursi DPR, tetapi karena kehadiran cah deso yang menjadi rising star, yakni mantan Gubernur DKI Jakarta serta mantan Walikota Solo, Joko Widodo. Kehadiran Jokowi dalam kancah perpolitikan nasional ini tak ubahnya seperti ‘juru selamat’ bagi marwah PDIP. Karena dengan gemilang bersama dengan Jusuf Kalla memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014.
Meski hanya didapuk sebagai ‘petugas partai’ tetapi Jokowi kembali menjadi penyelamat muka PDIP, terbukti berdasarkan hasil polling sejumlah lembaga survey, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah masih di atas 50 %. Padahal beberapa kader partai PDIP terjerat kasus korupsi seperti mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan Gubenur Sulawesi Selatan Nurdin Abdulah, tetapi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PDIP tidak ada tanda-tanda menurun. Jadi itu menjadi realitas tak terbantahkan, jika PDIP selamat dari ‘kutukan’ sebagai partai yang gagap dan menjadi korup bila berkuasa. Karena kinerja Jokowi dalam memimpin republik ini cukup baik.
Untuk mempertahankan kemenangan sekaligus marawah PDIP sebagai ruling party menghadapi hajatan politik 2024 ini kepiawaian Ketum PDIP akan sangat diuji dalam menentukan calon jagoannya untuk kembali menyelamatkan marwah PDIP dalam jagad politik nasional. Apalagi dalam bursa Capres dan Cawapres 2024 tidak banyak figur yang memilki kualifikasi seperti itu. PDIP harus jeli dalam memilih calon kadernya yang secara kualitatif memiliki kemampuan managerial dalam mengendalikan republik ini. Sementara untuk mempersiapkan kader yang baru sangat tidak mungkin.
Selain kualifikasi secara normatif, PDIP harus benar-benar memiliki parameter tersendiri untuk menentukan figur yang layak untuk diberi komando. Dalam kondisi seperti ini melalui mekanisme Pilpres secara langsung, mau tidak mau PDIP harus menggunakan hukum pasar yakni supplay dan demand, untuk mengukur tingkat elektabilitas calon. Selain berhadapan dengan konstituennya, PDIP harus bisa menawarkan calonnya ke partai-partai lain agar mau diajak koalisi. Parameter yang bisa digunakan adalah tingkat elektabilitas yang telah dirilis oleh sejumlah lembaga survey, meski itu tidak harus menjadi ukuran utama.
Bila PDIP mengabaikan hukum pasar, maka sejatinya PDIP tidak pernah belajar dari masa lalu, yang selalu meminta para penguasa jangan mengabaikan suara arus bawah atau wong cilik sebagai mana lazimnya negara demokrasi (vox populi vox dei).
Kondisi terkini di internal PDIP sendiri, nama Ganjar Pranowo hingga saat ini masih leading dalam perolehan suara berdasarkan sejumlah survey. Maka keberadaan Ganjar Pranowo saat ini mau tidak mau, bisa dianggap menjadi sosok penyelamat bagi PDIP. Tingkat elektabilitas yang tinggi bisa menjadi faktor penyelamat PDIP dalam Pilpres yang akan datang. Sebaliknya jika PDIP mengabaikan realitas itu, Ganjar justru bisa akan faktor kejatuhan PDIP. Karena suara PDIP niscaya akan terbelah jika Ganjar ditelantarkan secara politik.***
Dinamika politik dalam beberapa waktu terakhir ada indikasi muncul episentrum politik baru yang pasti bakal seru. Dan apabila managemen konflik itu tidak dikelola dengan baik oleh para petinggi PDIP, dinamika politik itu berpotensi akan memunculkan ‘goro-goro’ yang bila kita meminjam istilah Joyoboyo sebagai ‘banteng tarung sak kandang’ (konflik sesama kader). Terutama menjelang suksesi kepemimpinan nasional 2024 nanti, mengingat Jokowi tidak mungkin mencalonkan diri lagi. Karena memang konstitusi telah membatasi hanya dua periode.
Sebagai ruling party tentu saja PDIP ingin melanjutkan kekuasaan sekaligus mempertahankan kesinambungan program sesuai dengan platform dan visi misi partai. Mereka pasti telah melakukan berbagai macam simulasi dan kalkulasi politik yang matang, kira-kira strategi apa dan siapa serta berpasangan dengan siapa kader yang akan dipasang di Pilpres 2024 nanti. Tingkat elektabilitas serta konstelasi politik mutakhir tentu saja menjadi barometer utama dalam mengusung calon dalam palagan Pilpres nanti.
Dilemanya, dalam internal PDIP saat ini belum muncul nama yang memiliki tingkat elektabilitas yang menonjol. Hanya ada dua nama yang sudah mulai masuk dalam bursa dengan tingkat elektabilitas yang memadai yakni Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo serta Ketua DPR RI, Puan Maharani. Ironisnya, kedua tokoh itu justru sempat terlibat friksi, meski eskalasinya tidak meluas. Sementara PDIP juga tidak mungkin berharap lagi munculnya rising star dan ‘kabayan saba kota’ seperti halnya Jokowi yang bisa melambung popularitasnya dalam jangka waktu yang pendek. Meski Jokowi bukanlah kader murni partai.
Untuk memberikan tongkat komando dan estafet kepemimpinan tentu saja bukan perkara mudah bagi Joko Widodo untuk mendapuk Ganjar Pranowo sebagai ‘sang penerus’. Meski keduanya memiliki kedekatan emosional sebagai sesama ‘wong ndeso’ yang tidak memiliki ‘darah biru’ dan sama-sama Soekarnois dan penganut marhaenisme. Jokowi pasti tidak bisa serta merta memberikan tongkat komando, karena ketentuan politik sekarang mengharuskan setiap calon memilki kendaraan politik dengan tingkat keterpilihan 20% (presindential tresshold). Karena tentu saja itu akan mendapat tentangan dari elit-elit PDIP yang cenderung mendukung Puan Maharani untuk maju sebagai Capres edisi yang akan datang.
Perbedaan orientasi politik itulah yang saat ini mulai menimbulkan gejala ‘banteng tarung sak kandang’. Kini semakin sering kader PDIP justru mengkritik keras kebijakan-kebijakan Jokowi. Meski sikap kritis tetapi tetap loyal adalah sebuah keniscyaan seorang politisi, tetapi tetap saja akan menimbulkan penafsiran jika jelang Pilpres 2024 banyak politisi pendukung pemerintah yang secara perlahan mulai balik kanan dan berubah haluan. Karena pasca 2024 pasti Jokowi tidak lagi menjadi icon politik.
Semua bisa saja berasumsi jika tidak ada ‘pesta yang tak usai’ untuk menggambarkan posisi Jokowi dan para pendukungnya jelang Pilpres 2024. Tetapi mengabaikan fakta politik jika kini arus bawah menghendaki Ganjar Pranowo sebagai sosok ‘sang penerus’ bisa menjadi tindakan yang gegabah. Karena secara de facto gerakan arus bawah yang kini mendukung Ganjar semakin gencar dan kuat.
Sehingga berpotensi akan membuat PDIP terpecah belah. Kondisi itu tentu akan memberikan benefit politik terhadap kubu lawan yang akan bertarung dalam Pilpres 2024. Kasus Tarmidji Soehardjo, Kader PDIP yang tersisih jelang Pilgub DKI Jakarta karena Ketum PDIP lebih memilih Sutiyoso, tentu saja tidak bisa dijadikan referensi jika mengabaikan eksistensi Ganjar akan tidak berpengaruh terhadap suara partai. Karena gerakan pendukung Ganjar kini sudah massif dan terstruktur.
Maka menjelang suksesi kepemimpinan nasional melalui Pilpres 2024, sangat menarik bila kita membaca sejarah Partai PDI Perjuangan (PDI-P). Embrio partai berlambang banteng moncong putih ini adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang berdiri pada tahun 1973 yang merupakan fusi dari sejumlah partai berbasis nasionalis seperti Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Murba. Selain fusi dari golongan nasionalis, PDI juga terdiri dari fusi partai berbasis agama yakni Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik
Kendali partai ini kembali ke tangan trah Soekarno, pada 1993 setelah Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi ketua umum hingga periode 1998. Namun, terpilihnya Megawati tak mendapat restu dari pemerintahan Orde Baru sehingga muncul konflik internal. Pada 1996, PDI menggelar kongres pemilihan ketua umum yang ditentang Megawati. Kongres tersebut lantas memilih Soerjadi sebagai ketua umum.
Setelah terjadi konflik berdarah-darah pada bulan Juli 1996 dengan peristiwa yang kita kenal Kudatuli serta konflik kepengurusan dengan Kubu Budi Harjono, PDI bermetamorfosa menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri. Metamorfose PDI menjadi PDIP pada tanggal 14 Februari 1999 itu tidak terlepas adanya disparitas antara fakta de jure dan de facto. Secara de jure memang pemerintah mengakui kubu Budi Harjono karena memang adanya hidden agenda pemerintah saat itu, tetapi secara de facto, gerakan wong cilik atau arus bawah yang mendukung PDI-P semakin membesar dan tak terbendung.
Klimaks dukungan masyarakat terhadap PDIP sebagai bagian dari romantisme masa lalu karena kebesaran PNI itu terjadi dalam Pemilu tahun 1999. Saat itu partai yang sering mempersonifikasi sebagai partai wong cilik ini berhasil meraup suara hingga 33,74 persen suara dengan 153 kursi di DPR. Ironisnya, dengan perolehan suara segede itu, PDIP tidak mampu mengantarkan Ketumnya sebagai Presiden RI yang ke 4 dan hanya menduduki kursi RI 2. Meski ‘kecelakaan sejarah’ itu tidak terlepas dari ‘telikungan maut’ dari kaukus politik poros tengah yang dikomandoi oleh Amien Rais CS.
Dalam Pemilu selanjutnya tahun 2004, perolehan suara PDIP kembali ngedrop dan hanya mendulang suara sebanyak 18,53 persen suara dengan 109 kursi di DPR. Dan lagi–lagi, sang Ketum yang berpasangan Hazim Muzadi, harus mengubur keinginannya untuk duduk di singgasana RI sekaligus mengembalikan marwah PDIP sebagai partai besar, menjadi gagal karena kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK).
Seiring dengan luruhnya hegemoni Partai Demokrat serta tertutupnya peluang SBY untuk menjadi Capres lagi pada Pemilu 2014, PDIP kembali memperoleh momentum. Meski perolehan suara PDI-P dalam Pemilu 2014 hanya sebesar 18,95 persen suara dengan raihan 109 kursi DPR, tetapi karena kehadiran cah deso yang menjadi rising star, yakni mantan Gubernur DKI Jakarta serta mantan Walikota Solo, Joko Widodo. Kehadiran Jokowi dalam kancah perpolitikan nasional ini tak ubahnya seperti ‘juru selamat’ bagi marwah PDIP. Karena dengan gemilang bersama dengan Jusuf Kalla memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014.
Meski hanya didapuk sebagai ‘petugas partai’ tetapi Jokowi kembali menjadi penyelamat muka PDIP, terbukti berdasarkan hasil polling sejumlah lembaga survey, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah masih di atas 50 %. Padahal beberapa kader partai PDIP terjerat kasus korupsi seperti mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan Gubenur Sulawesi Selatan Nurdin Abdulah, tetapi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PDIP tidak ada tanda-tanda menurun. Jadi itu menjadi realitas tak terbantahkan, jika PDIP selamat dari ‘kutukan’ sebagai partai yang gagap dan menjadi korup bila berkuasa. Karena kinerja Jokowi dalam memimpin republik ini cukup baik.
Untuk mempertahankan kemenangan sekaligus marawah PDIP sebagai ruling party menghadapi hajatan politik 2024 ini kepiawaian Ketum PDIP akan sangat diuji dalam menentukan calon jagoannya untuk kembali menyelamatkan marwah PDIP dalam jagad politik nasional. Apalagi dalam bursa Capres dan Cawapres 2024 tidak banyak figur yang memilki kualifikasi seperti itu. PDIP harus jeli dalam memilih calon kadernya yang secara kualitatif memiliki kemampuan managerial dalam mengendalikan republik ini. Sementara untuk mempersiapkan kader yang baru sangat tidak mungkin.
Selain kualifikasi secara normatif, PDIP harus benar-benar memiliki parameter tersendiri untuk menentukan figur yang layak untuk diberi komando. Dalam kondisi seperti ini melalui mekanisme Pilpres secara langsung, mau tidak mau PDIP harus menggunakan hukum pasar yakni supplay dan demand, untuk mengukur tingkat elektabilitas calon. Selain berhadapan dengan konstituennya, PDIP harus bisa menawarkan calonnya ke partai-partai lain agar mau diajak koalisi. Parameter yang bisa digunakan adalah tingkat elektabilitas yang telah dirilis oleh sejumlah lembaga survey, meski itu tidak harus menjadi ukuran utama.
Bila PDIP mengabaikan hukum pasar, maka sejatinya PDIP tidak pernah belajar dari masa lalu, yang selalu meminta para penguasa jangan mengabaikan suara arus bawah atau wong cilik sebagai mana lazimnya negara demokrasi (vox populi vox dei).
Kondisi terkini di internal PDIP sendiri, nama Ganjar Pranowo hingga saat ini masih leading dalam perolehan suara berdasarkan sejumlah survey. Maka keberadaan Ganjar Pranowo saat ini mau tidak mau, bisa dianggap menjadi sosok penyelamat bagi PDIP. Tingkat elektabilitas yang tinggi bisa menjadi faktor penyelamat PDIP dalam Pilpres yang akan datang. Sebaliknya jika PDIP mengabaikan realitas itu, Ganjar justru bisa akan faktor kejatuhan PDIP. Karena suara PDIP niscaya akan terbelah jika Ganjar ditelantarkan secara politik.***