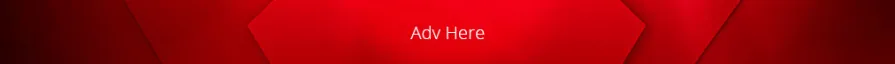High Cost Political Tengil

Oleh : Gugus Elmo Rais
Untuk menjaga eksistensi sebagai negara super power, para politisi Amerika selalu berpegang teguh pada doktrin ‘American first’ yang diupgrade oleh Donald Trump menjadi ‘American first policy’. Doktrin itu selalu dimodifikasi oleh setiap pemimpin Amerika melihat kepentingan politiknya, baik untuk kepentingan politik domestik maupun untuk politik luar negeri. Dengan doktrin itu setiap pemimpin Amerika selalu melakukan internasionalisme ekonomi dan politik. Yang sebenarnya mulai dikurangi oleh Donald Trump, meski faktanya ‘paman jambul’ itu tidak konsisten dan justru bersikap agresif terhadap beberapa negara seperti, Iran, Korea Utara yang dijuluki ‘poros setan’ dan Meksiko terkait imigran yang jumlahnya cukup signifikan.
Berangkat dari doktrin itulah Amerika selalu menjalankan politik luar negeri yang kepo dan tengil serta cenderung jahil. Amerika selalu menggunakan qonditionally (persyaratan) yang njlimet dalam menjalin kerja sama dengan negara lain menggunakan standar yang mereka inginkan sehingga cenderung mendikte. Standar umum yang dipakai adalah pelaksanaan HAM, ingat Indonesia sempat diembargo pembelian senjata dari AS karena mereka menilai ada pelanggaran HAM di Timor Timur terutama pasca terjadinya peristiwa Santa Cruz, Dilli.
Internasionalisme ekonomi dan politik Amerika itu memang bersumber dari kontitusi mereka. Interprestasi hukum internasional diterjemahkan dengan seenak udelnya. Meski komunitas dunia internasional telah memiliki norma-norma yang diakui bersama yakni Jus Cogan. Karena sesuai dengan konstitusi yang dimilikinya, Amerika menganut faham monisme primat hukum internasional yang artinya norma-norma hukum yang mereka miliki yang merupakan warisan dari Lord Denning serta William Black Stone itu menjadi norma hukum universal yang bisa diterapkan secara internasional.
Karena amanat dari kontitusi itulah Amerika Serikat sering membaiat diri sebagai global corp (polisi dunia) tentu untuk mendukung kepentingan politik dan ekonomi mereka. Salah satu bukti teraktual, bagaimana mereka dengan berbagai pembenaran mendongkel Saddam Huseein, yang sesungguhya mengusung kepentingan ekonomi mereka terutama penguasaan terhadap lading-ladang minyak yang tumpah ruah. Begitu juga halnya penggulingan pemimpin revolusioner Libya, Kolonel Muammar Khadafi.
Sehingga bukanlah hal yang aneh bila Amerika senantiasa kepo dan tengil terkait urusan dalam negeri negara lain. Bahkan Amerika selalu berusaha melibatkan diri terhadap setiap proses suksesi di negara-negara yang memiliki peran yang sangat strategis dengan kepentingan politik dan ekonomi mereka. Tak jarang Amerika berusaha mendorong politisi yang dianggap bisa menjalin kerjasama dengannya, dan terkadang juga ikut cawe-cawe untuk ikut mendongkel jika pemimpin tersebut tidak mampu mengakomodir lagi kepentingan mereka.
Sejarah telah mencatat, hal-hal yang sangat paradoks terkait politik luar negeri yang dijalankan oleh Amerika yang justru berujung tragis. Sebutlah misalnya dukungannya terhadap Raja Iran, Muhammad Reza Shah Pahlevi yang sangat dekat dengan Amerika. Monarkhi yang dikenal dengan konsep Revolusi Putih berupa pembangunan infrastruktur besar-besaran serta reformasi pertanahan itu akhirnya tumbang setelah terjadi Revolusi Islam yang dikomandoi oleh Ayatullah Ali Khamaeni, Februari 1979. Tumbangnya Reza Pahlevi itu ternyata tidak terlepas jika pemimpin binaan Amerika yang semula dinilai sebagai sosok yang visioner itu pada akhirnya cenderung korup dan otoriter. Pahlevi akhirnya lengser setelah 38 tahun berkuasa di Iran.
Pemimpin otoriter Philipina, Ferdinand Edralin Marcos semula juga disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Amerika, karena bahu membahu membendung infiltrasi paham komunis di negaranya. Pemimpin ini semula dikenal sebagai pemimpin yang visioner dengan Revolusi Bagong Lipunan (masyarakat baru) yang artinya antara orang kaya dan orang miskin harus saling bantu. Tetapi akhirnya justru dikenal otoriter dan korup, sehingga diturunkan oleh rakyatnya melalui revolusi EDSA (Revolusi Kuning) yang dipimpin istri mendiang Banigno Aquino, Corazon Aquino.
Presiden Republik Indonesia ke 2 Soeharto naik ketampuk pimpinan RI 1 juga sering disebut-sebut adanya campur tangan AS, yang diduga berada dibalik tragedi G 30 S PKI serta adanya coupe de’etat (kudeta merangkak) dalam sidang MPRS 1968 terhadap Pemimpin Besar Revolusi, Ir Soekarno. Kala itu Amerika merasa tidak happy dengan Soekarno yang menjalankan politik luar negeri yang zig zag dan flamboyan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Amerika yang berpaham liberal dan kapitalis sangat membutuhkan sekutu untuk melawan komunis, tetapi Soekarno justru menjalin kemesraan dengan China. Tetapi setelah 3 dasawarsa berkuasa, Soeharto ternyata juga sangat korup dan otoriter sehingga lengser keprabon pada 20 Mei 1998.
Bukti yang teraktuil jika politik tengil sangat merugikan bagi Amerika maupun negara yang dibinanya adalah Afghanistan. Setelah ‘membantu’ Mujahidin menggulingkan pemimpin binaan Uni Soviet, seperti Nuhammad Taraki, Hafizullah Amin serta Babrak Kamal, Amerika berusaha melakukan aneksasi dan menciptakan pemimpin Afghanistan yang bisa dibina. Semula Amerika menemukan sosok pemimpin yang moderat dalam diri Hamid Karzai. Tenyata sosok ini kurang dikenal di Afghanistan, sehingga sering diolok-olok tak ubahnya seperti Walikota Kabul, karena kecilnya pengaruh politik yang dimiliki oleh Karzai.
Seetelah upaya menciptakan koloni gagal bersama Karzai, Amerikapun memilih sosok Ashraf Gani sang mantan Wapres. Tidak tanggung-tanggung biaya ‘play group” Ashraf Gani itu mencapai angka, Rp 13.600 triliun atau sekitar 7 kali APBN Indonesia, alih-alih bisa membina negaranya menjadi penurut dan mau melimpahkan kekayaan alam berupa mineral yang melimpah ruah, Ashraf Gani justru tak berdaya mendapat tekanan dari Taliban dan harus colong playu (melarikan diri) ke Uni Emirat Arab (UEA). Ironisnya, selain telah gagal menyatukan bangsa, Ashraf Gani juga terindikasi korupsi, terbukti saat pelariannya sempat membawa uang dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan selama dalam binaan Amerika, Ashraf bersama para kroninya hidup bergelimang kemewahan meski perekonomian negerinya dalam kondisi mawut. Kondisi itulah yang membuat rakyat Afghanistan berada dalam kondisi yang dilematis.***
Untuk menjaga eksistensi sebagai negara super power, para politisi Amerika selalu berpegang teguh pada doktrin ‘American first’ yang diupgrade oleh Donald Trump menjadi ‘American first policy’. Doktrin itu selalu dimodifikasi oleh setiap pemimpin Amerika melihat kepentingan politiknya, baik untuk kepentingan politik domestik maupun untuk politik luar negeri. Dengan doktrin itu setiap pemimpin Amerika selalu melakukan internasionalisme ekonomi dan politik. Yang sebenarnya mulai dikurangi oleh Donald Trump, meski faktanya ‘paman jambul’ itu tidak konsisten dan justru bersikap agresif terhadap beberapa negara seperti, Iran, Korea Utara yang dijuluki ‘poros setan’ dan Meksiko terkait imigran yang jumlahnya cukup signifikan.
Berangkat dari doktrin itulah Amerika selalu menjalankan politik luar negeri yang kepo dan tengil serta cenderung jahil. Amerika selalu menggunakan qonditionally (persyaratan) yang njlimet dalam menjalin kerja sama dengan negara lain menggunakan standar yang mereka inginkan sehingga cenderung mendikte. Standar umum yang dipakai adalah pelaksanaan HAM, ingat Indonesia sempat diembargo pembelian senjata dari AS karena mereka menilai ada pelanggaran HAM di Timor Timur terutama pasca terjadinya peristiwa Santa Cruz, Dilli.
Internasionalisme ekonomi dan politik Amerika itu memang bersumber dari kontitusi mereka. Interprestasi hukum internasional diterjemahkan dengan seenak udelnya. Meski komunitas dunia internasional telah memiliki norma-norma yang diakui bersama yakni Jus Cogan. Karena sesuai dengan konstitusi yang dimilikinya, Amerika menganut faham monisme primat hukum internasional yang artinya norma-norma hukum yang mereka miliki yang merupakan warisan dari Lord Denning serta William Black Stone itu menjadi norma hukum universal yang bisa diterapkan secara internasional.
Karena amanat dari kontitusi itulah Amerika Serikat sering membaiat diri sebagai global corp (polisi dunia) tentu untuk mendukung kepentingan politik dan ekonomi mereka. Salah satu bukti teraktual, bagaimana mereka dengan berbagai pembenaran mendongkel Saddam Huseein, yang sesungguhya mengusung kepentingan ekonomi mereka terutama penguasaan terhadap lading-ladang minyak yang tumpah ruah. Begitu juga halnya penggulingan pemimpin revolusioner Libya, Kolonel Muammar Khadafi.
Sehingga bukanlah hal yang aneh bila Amerika senantiasa kepo dan tengil terkait urusan dalam negeri negara lain. Bahkan Amerika selalu berusaha melibatkan diri terhadap setiap proses suksesi di negara-negara yang memiliki peran yang sangat strategis dengan kepentingan politik dan ekonomi mereka. Tak jarang Amerika berusaha mendorong politisi yang dianggap bisa menjalin kerjasama dengannya, dan terkadang juga ikut cawe-cawe untuk ikut mendongkel jika pemimpin tersebut tidak mampu mengakomodir lagi kepentingan mereka.
Sejarah telah mencatat, hal-hal yang sangat paradoks terkait politik luar negeri yang dijalankan oleh Amerika yang justru berujung tragis. Sebutlah misalnya dukungannya terhadap Raja Iran, Muhammad Reza Shah Pahlevi yang sangat dekat dengan Amerika. Monarkhi yang dikenal dengan konsep Revolusi Putih berupa pembangunan infrastruktur besar-besaran serta reformasi pertanahan itu akhirnya tumbang setelah terjadi Revolusi Islam yang dikomandoi oleh Ayatullah Ali Khamaeni, Februari 1979. Tumbangnya Reza Pahlevi itu ternyata tidak terlepas jika pemimpin binaan Amerika yang semula dinilai sebagai sosok yang visioner itu pada akhirnya cenderung korup dan otoriter. Pahlevi akhirnya lengser setelah 38 tahun berkuasa di Iran.
Pemimpin otoriter Philipina, Ferdinand Edralin Marcos semula juga disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Amerika, karena bahu membahu membendung infiltrasi paham komunis di negaranya. Pemimpin ini semula dikenal sebagai pemimpin yang visioner dengan Revolusi Bagong Lipunan (masyarakat baru) yang artinya antara orang kaya dan orang miskin harus saling bantu. Tetapi akhirnya justru dikenal otoriter dan korup, sehingga diturunkan oleh rakyatnya melalui revolusi EDSA (Revolusi Kuning) yang dipimpin istri mendiang Banigno Aquino, Corazon Aquino.
Presiden Republik Indonesia ke 2 Soeharto naik ketampuk pimpinan RI 1 juga sering disebut-sebut adanya campur tangan AS, yang diduga berada dibalik tragedi G 30 S PKI serta adanya coupe de’etat (kudeta merangkak) dalam sidang MPRS 1968 terhadap Pemimpin Besar Revolusi, Ir Soekarno. Kala itu Amerika merasa tidak happy dengan Soekarno yang menjalankan politik luar negeri yang zig zag dan flamboyan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Amerika yang berpaham liberal dan kapitalis sangat membutuhkan sekutu untuk melawan komunis, tetapi Soekarno justru menjalin kemesraan dengan China. Tetapi setelah 3 dasawarsa berkuasa, Soeharto ternyata juga sangat korup dan otoriter sehingga lengser keprabon pada 20 Mei 1998.
Bukti yang teraktuil jika politik tengil sangat merugikan bagi Amerika maupun negara yang dibinanya adalah Afghanistan. Setelah ‘membantu’ Mujahidin menggulingkan pemimpin binaan Uni Soviet, seperti Nuhammad Taraki, Hafizullah Amin serta Babrak Kamal, Amerika berusaha melakukan aneksasi dan menciptakan pemimpin Afghanistan yang bisa dibina. Semula Amerika menemukan sosok pemimpin yang moderat dalam diri Hamid Karzai. Tenyata sosok ini kurang dikenal di Afghanistan, sehingga sering diolok-olok tak ubahnya seperti Walikota Kabul, karena kecilnya pengaruh politik yang dimiliki oleh Karzai.
Seetelah upaya menciptakan koloni gagal bersama Karzai, Amerikapun memilih sosok Ashraf Gani sang mantan Wapres. Tidak tanggung-tanggung biaya ‘play group” Ashraf Gani itu mencapai angka, Rp 13.600 triliun atau sekitar 7 kali APBN Indonesia, alih-alih bisa membina negaranya menjadi penurut dan mau melimpahkan kekayaan alam berupa mineral yang melimpah ruah, Ashraf Gani justru tak berdaya mendapat tekanan dari Taliban dan harus colong playu (melarikan diri) ke Uni Emirat Arab (UEA). Ironisnya, selain telah gagal menyatukan bangsa, Ashraf Gani juga terindikasi korupsi, terbukti saat pelariannya sempat membawa uang dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan selama dalam binaan Amerika, Ashraf bersama para kroninya hidup bergelimang kemewahan meski perekonomian negerinya dalam kondisi mawut. Kondisi itulah yang membuat rakyat Afghanistan berada dalam kondisi yang dilematis.***