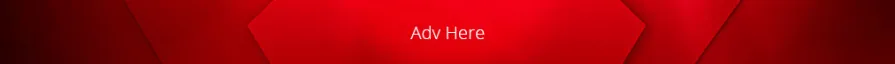Upaya Pemberantasan Korupsi Yang Tanggung

Oleh : Gugus Elmo Ra’is
Karena pernah ‘dibaiat’ sebagai negara yang paling korup di kolong jagat oleh Transparansi Internasional (TI), maka pemberantasan korupsi menjadi salah satu ‘amanah suci’ reformasi. Ironisnya, hingga usia 23 tahun reformasi, korupsi masih tetap meraja lela. Parameter keberhasilan pemberantasan korupsi bukan seberapa banyak pejabat yang bisa dikandangin, tetapi lebih seberapa takut masyarakat untuk melakukan penjarahan uang negara. Dan faktanya satu persatu pejabat dari berbagai level terus terjerat dalam ontdekking op haterdaad (OTT) KPK.
Judul diatas bukan cerminan sikap pesimis dan frustasi terhadap upaya pemberantasan korupsi serta tekad untuk menciptakan cleans and good governance, tetapi bila melihat progress pemberantasan korupsi dari aspek pencegahan terbukti masih jauh panggang dari api. Upaya pemberantasan korupsi bila tidak dilakukan secara sistemik dan lintas sektoral hanya seperti mengejar ilusi yang menguras energi. Bahkan korupsi bisa menjelma menjadi budaya nista.
Tertangkapnya, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, mantan Mensos Juliari Batubara, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo, dan lain lain secara empirik membuktikan jika strategi pemberantasan korupsi kita telah gagal total. Padahal KPK sebagai lembaga ad hoc yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan sekaligus penindakan telah dibekali kewenangan yang mewah sekaligus bekal anggaran yang memadai sekitar Rp 1,305 triliun.
Setidaknya ada tiga tataran yang harus dilakukan secara simultan dan berkesinambungan agar upaya pemberantasan itu bisa membuahkan hasil yang maksimal. Pertama adalah reformasi hukum, kedua adalah reformasi politik serta ketiga adalah revolusi kebudayaan. Reformasi hukum itu bisa dimulai dengan menata secara kelembagaan terhadap aparat penegak hukum terutama dalam upaya untuk memberantas korupsi tidak hanya dibebankan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hanya bersifat ad hoc.
Sebagai lembaga anti rasuah, KPK harus bersikap progresif, sehingga upaya yang telah dilakukan untuk memberantas korupsi tidak sia-sia. Karena faktanya meski KPK telah memenjarakan banyak pejabat toh hingga saat ini belum ada tanda-tanda korupsi akan berkurang. Hingga saat ini KPK belum pernah menerapkan asas ultimum remedium sebagai senjata pamungkas dalam pemberantasan korupsi, terbukti para penyidik KPK belum pernah menerapkan tuntutan maksimal dalam hal ini hukuman mati sebagai sanksi pidana maksimal sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat 2, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan."Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan,”.
Tugas untuk memberikan hukuman yang maksimal itu tidak hanya menjadi tanggung jawab jaksa dalam proses pembuatan legal drafting dan legal reasoning (konstruksi hukumnya) sekaligus memberikan tuntutan terhadap terdakwa (koruptor) tetapi juga harus menjadi tanggung jawab hakim untuk bersikap progresif dengan memberikan putusan yang ultra petita, seperti tesisnya Satjipto Raharjo. Kewenangan hakim untuk memberikan hukuman yang melebihi dari tuntutan jaksa itu sendiri telah diatur dalam pasal 193 KUHAP maupun hasil judicial review yang telah dikabulkan oleh MK melalui putusannya Nomor 48/PUU-IX/2011 dan 49/PUUIX/2011.11 Sehingga dengan demikian secara normatif hakim memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan yang bersifat ultra petita.
Apalagi kita telah memiliki konsensus yang kita sepakati bersama jika korupsi telah masuk kategori extra ordinary crime (kejahatan yang luar biasa). Sehingga penerapan sanksi pidana yang maksimal itu memiliki landasan secara moral maupun berdasarkan norma hukum formil seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun hingga saat ini ketentuan itu belum pernah diimplementasikan. Maka selain hakim harus bersikap progresif juga perlu adanya pengawasan internal di MA untuk mengawasi hakim-hakim yang diduga nakal dan ‘main mata’ terhadap perkara-perkara korupsi terutama yang masuk kategori mega skandal.
Bukan justru sebaliknya, hakim menggunakan asas yang sangat populer yaitu in dubio pro reo (dalam hal keragu-raguan hakim harus memutuskan sedemikian hingga menguntungkan terdakwa). Padahal majelis hakim telah memiliki hak immunitas dalam bentuk asas res judicata pro veritate habetur (apa yang diputus hakim harus dianggap benar). Asas-asas ini penerapannya disaat mengadili dan hakimlah yang menentukannya. Atas dasar asas-asas itulah independensi dan kewenangan hakim untuk berpendapat itu dilindungi dalam bentuk dissenting opoinion (hak berpendapat).
Tetapi berbagai hak eksklusif itu seharus dipergunakan secara bertanggung jawab untuk menghadirkan keadilan yang berketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono), sekaligus sebagai upaya untuk memberikan detterent efeck (efek jera) serta memenuhi rasa keadilan sekaligus kenyamanan masyarakat sesuai dengan teori utiliarnismenya Jeremy Bentham, John Stuart Mill maupun Rudolf von Jhering .
Yang kedua adalah harus dioptimalkan fungsi supervisi KPK terhadap lembaga hukum lainnya, Polri dan Kejaksaan seperti tujuan awal agar kedua lembaga tersebut lebih kapabel dan kredibel. Karena tidak mungkin membebankan semua persoalan itu mengingat jaringan KPK yang masih relative kecil dibandingkan dengan kedua lembaga itu. Karena yang tejadi saat ini sinergi antar lembaga masih kurang maksimal, justru terkesan ada rivalitas antara lembaga negara.
Langkah selanjutnya yang tak kalah penting, adalah reformasi politik. Sistem pemilihan langsung dan sistem multipartai sebagai buah dari amandemen UUD 1945 ternyata justru melahirkan kompleksitas persoalan dan menjadi biang munculnya koruptor-koruptor baru. Pemilhan Presiden (Pilpres) dan Pilkada langsung justru melahirkan high cost politic (politik biaya tinggi). Bila tidak dari kocek sendiri sang calon, biasanya akan lahir cukong-cukong politik yang mau menjadi sponsor sang calon.
Faktor inilah yang akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang oligarkis. Dan biasanya para cukong-cukong politik itu pasti meminta sejumlah konsesi baik dalam bentuk proyek maupun kebijakan yang menguntungkan dirinya dan kelompoknya. Kasus Nurdin Abdullah (NA) mungkin menjadi contoh kasus yang menarik, ketika masih menjadi Bupati Bantaeng, NA adalah sosok yang memiliki kredibilitas sangat baik serta sarat dengan prestasi. Karena saat pemilihan sebagai Bupati Bantaeng, cukup berbekal ketokohannya dengan konstelasi politik yang relativ kecil sehingga NA dapat terpilih.
Tetapi saat masuk ke palagan yang lebih luas sebagai Calon Gubernur Sulsel, mau tidak mau NA harus melakukan kompromi-kompromi politik. Karena kekuasaan politik di Indonesia secara umum dibangun berdasarkan kompromi-kompromi sekaligus menebar konsesi baik dalam bentuk materi maupun kekuasaan politik. Karena kursi kekuasaan di Indonesia bila dibreakdown (dihitung) seperti tidak masuk dalam logika ekonomi antara biaya yang dikeluarkan dengan akumulasi gaji yang akan diperoleh selama berkuasa.
Berangkat dari realitas seperti itu, maka kini sudah saatnya kedaulatan dikembalikan pada rakyat dan dilaksanakan oleh MPR sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum diamandemen. Sehingga biaya Pilpres maupun Pilkada bisa ditekan sedemikian rupa sekaligus menghindarkan bangsa ini dari fragmentasi politik yang saling berhadapan.
Rendahnya biaya itu akan membuat para politisi tidak akan mengejar setoran agar balik modal. Kemungkinan terjadinya manipulasi kedaulatan rakyat oleh para Anggota MPR untuk menerima suap dari sang calon bisa dilakukan dengan pengawasan yang ketat baik oleh aparat penegak hukum, LSM maupun pers yang telah didefinisikan oleh Thomas Jefferson sebagai pilar demokrasi ke 4.
Kedua langkah itu tak aka ada gunanya dan sia-sia dilakukan tanpa adanya revolusi kebudayaan. Fenomena yang terjadi saat ini adalah budaya borjuis dan hedonis. Padahal dari struktur gaji dan pendapatan, masyarakat kita termasuk para ASN kita tebilang sangat kecil. Kondisi inilah yang memicu terjadinya korupsi dengan berbagai variannya mulai dari tingkat briberi (uang pelicin) hingga katabelece sebagai bentuk dari penyalah gunaan wewenang (abuse of power).
Upaya untuk melakukan revolusi kebudayaan itu bisa dimulai dari pimpinan yang tertinggi (presiden) dengan memberikan keteladanan yang bersifat top down. Selain pemimpin formal, tugas yang strategis ini bisa dilakukan oleh pemimpin non formal seperti tokoh-tokoh agama dan masyarakat maupun politik untuk memberikan guidence (panduan) sesuai dengan nilai-nilai agama maupun falsafah lokal untuk hidup jujur dan sederhana.
Bukan justru menjadi contoh buruk dengan menjelma menjadi pedagang ayat sekaligus mengkomersilkan nilai-nilai agama hanyak untuk mendukung gaya hidupnya yang borjuis, seperti misalnya para pengkotbah yang memasang tarif untuk mendukung gaya hidup mereka yang mewah.Berhasilnya pemberantasan korupsi itu ditandai dengan munculnya kesadaran bahwa korupsi itu kotor dan merupakan perbuatan dosa. Bukan berhasil menangkap koruptor hanya karena apes, ketika modus korupsi mereka terungkap setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyadapan.***
Karena pernah ‘dibaiat’ sebagai negara yang paling korup di kolong jagat oleh Transparansi Internasional (TI), maka pemberantasan korupsi menjadi salah satu ‘amanah suci’ reformasi. Ironisnya, hingga usia 23 tahun reformasi, korupsi masih tetap meraja lela. Parameter keberhasilan pemberantasan korupsi bukan seberapa banyak pejabat yang bisa dikandangin, tetapi lebih seberapa takut masyarakat untuk melakukan penjarahan uang negara. Dan faktanya satu persatu pejabat dari berbagai level terus terjerat dalam ontdekking op haterdaad (OTT) KPK.
Judul diatas bukan cerminan sikap pesimis dan frustasi terhadap upaya pemberantasan korupsi serta tekad untuk menciptakan cleans and good governance, tetapi bila melihat progress pemberantasan korupsi dari aspek pencegahan terbukti masih jauh panggang dari api. Upaya pemberantasan korupsi bila tidak dilakukan secara sistemik dan lintas sektoral hanya seperti mengejar ilusi yang menguras energi. Bahkan korupsi bisa menjelma menjadi budaya nista.
Tertangkapnya, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, mantan Mensos Juliari Batubara, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo, dan lain lain secara empirik membuktikan jika strategi pemberantasan korupsi kita telah gagal total. Padahal KPK sebagai lembaga ad hoc yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan sekaligus penindakan telah dibekali kewenangan yang mewah sekaligus bekal anggaran yang memadai sekitar Rp 1,305 triliun.
Setidaknya ada tiga tataran yang harus dilakukan secara simultan dan berkesinambungan agar upaya pemberantasan itu bisa membuahkan hasil yang maksimal. Pertama adalah reformasi hukum, kedua adalah reformasi politik serta ketiga adalah revolusi kebudayaan. Reformasi hukum itu bisa dimulai dengan menata secara kelembagaan terhadap aparat penegak hukum terutama dalam upaya untuk memberantas korupsi tidak hanya dibebankan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hanya bersifat ad hoc.
Sebagai lembaga anti rasuah, KPK harus bersikap progresif, sehingga upaya yang telah dilakukan untuk memberantas korupsi tidak sia-sia. Karena faktanya meski KPK telah memenjarakan banyak pejabat toh hingga saat ini belum ada tanda-tanda korupsi akan berkurang. Hingga saat ini KPK belum pernah menerapkan asas ultimum remedium sebagai senjata pamungkas dalam pemberantasan korupsi, terbukti para penyidik KPK belum pernah menerapkan tuntutan maksimal dalam hal ini hukuman mati sebagai sanksi pidana maksimal sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat 2, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan."Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan,”.
Tugas untuk memberikan hukuman yang maksimal itu tidak hanya menjadi tanggung jawab jaksa dalam proses pembuatan legal drafting dan legal reasoning (konstruksi hukumnya) sekaligus memberikan tuntutan terhadap terdakwa (koruptor) tetapi juga harus menjadi tanggung jawab hakim untuk bersikap progresif dengan memberikan putusan yang ultra petita, seperti tesisnya Satjipto Raharjo. Kewenangan hakim untuk memberikan hukuman yang melebihi dari tuntutan jaksa itu sendiri telah diatur dalam pasal 193 KUHAP maupun hasil judicial review yang telah dikabulkan oleh MK melalui putusannya Nomor 48/PUU-IX/2011 dan 49/PUUIX/2011.11 Sehingga dengan demikian secara normatif hakim memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan yang bersifat ultra petita.
Apalagi kita telah memiliki konsensus yang kita sepakati bersama jika korupsi telah masuk kategori extra ordinary crime (kejahatan yang luar biasa). Sehingga penerapan sanksi pidana yang maksimal itu memiliki landasan secara moral maupun berdasarkan norma hukum formil seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun hingga saat ini ketentuan itu belum pernah diimplementasikan. Maka selain hakim harus bersikap progresif juga perlu adanya pengawasan internal di MA untuk mengawasi hakim-hakim yang diduga nakal dan ‘main mata’ terhadap perkara-perkara korupsi terutama yang masuk kategori mega skandal.
Bukan justru sebaliknya, hakim menggunakan asas yang sangat populer yaitu in dubio pro reo (dalam hal keragu-raguan hakim harus memutuskan sedemikian hingga menguntungkan terdakwa). Padahal majelis hakim telah memiliki hak immunitas dalam bentuk asas res judicata pro veritate habetur (apa yang diputus hakim harus dianggap benar). Asas-asas ini penerapannya disaat mengadili dan hakimlah yang menentukannya. Atas dasar asas-asas itulah independensi dan kewenangan hakim untuk berpendapat itu dilindungi dalam bentuk dissenting opoinion (hak berpendapat).
Tetapi berbagai hak eksklusif itu seharus dipergunakan secara bertanggung jawab untuk menghadirkan keadilan yang berketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono), sekaligus sebagai upaya untuk memberikan detterent efeck (efek jera) serta memenuhi rasa keadilan sekaligus kenyamanan masyarakat sesuai dengan teori utiliarnismenya Jeremy Bentham, John Stuart Mill maupun Rudolf von Jhering .
Yang kedua adalah harus dioptimalkan fungsi supervisi KPK terhadap lembaga hukum lainnya, Polri dan Kejaksaan seperti tujuan awal agar kedua lembaga tersebut lebih kapabel dan kredibel. Karena tidak mungkin membebankan semua persoalan itu mengingat jaringan KPK yang masih relative kecil dibandingkan dengan kedua lembaga itu. Karena yang tejadi saat ini sinergi antar lembaga masih kurang maksimal, justru terkesan ada rivalitas antara lembaga negara.
Langkah selanjutnya yang tak kalah penting, adalah reformasi politik. Sistem pemilihan langsung dan sistem multipartai sebagai buah dari amandemen UUD 1945 ternyata justru melahirkan kompleksitas persoalan dan menjadi biang munculnya koruptor-koruptor baru. Pemilhan Presiden (Pilpres) dan Pilkada langsung justru melahirkan high cost politic (politik biaya tinggi). Bila tidak dari kocek sendiri sang calon, biasanya akan lahir cukong-cukong politik yang mau menjadi sponsor sang calon.
Faktor inilah yang akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang oligarkis. Dan biasanya para cukong-cukong politik itu pasti meminta sejumlah konsesi baik dalam bentuk proyek maupun kebijakan yang menguntungkan dirinya dan kelompoknya. Kasus Nurdin Abdullah (NA) mungkin menjadi contoh kasus yang menarik, ketika masih menjadi Bupati Bantaeng, NA adalah sosok yang memiliki kredibilitas sangat baik serta sarat dengan prestasi. Karena saat pemilihan sebagai Bupati Bantaeng, cukup berbekal ketokohannya dengan konstelasi politik yang relativ kecil sehingga NA dapat terpilih.
Tetapi saat masuk ke palagan yang lebih luas sebagai Calon Gubernur Sulsel, mau tidak mau NA harus melakukan kompromi-kompromi politik. Karena kekuasaan politik di Indonesia secara umum dibangun berdasarkan kompromi-kompromi sekaligus menebar konsesi baik dalam bentuk materi maupun kekuasaan politik. Karena kursi kekuasaan di Indonesia bila dibreakdown (dihitung) seperti tidak masuk dalam logika ekonomi antara biaya yang dikeluarkan dengan akumulasi gaji yang akan diperoleh selama berkuasa.
Berangkat dari realitas seperti itu, maka kini sudah saatnya kedaulatan dikembalikan pada rakyat dan dilaksanakan oleh MPR sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum diamandemen. Sehingga biaya Pilpres maupun Pilkada bisa ditekan sedemikian rupa sekaligus menghindarkan bangsa ini dari fragmentasi politik yang saling berhadapan.
Rendahnya biaya itu akan membuat para politisi tidak akan mengejar setoran agar balik modal. Kemungkinan terjadinya manipulasi kedaulatan rakyat oleh para Anggota MPR untuk menerima suap dari sang calon bisa dilakukan dengan pengawasan yang ketat baik oleh aparat penegak hukum, LSM maupun pers yang telah didefinisikan oleh Thomas Jefferson sebagai pilar demokrasi ke 4.
Kedua langkah itu tak aka ada gunanya dan sia-sia dilakukan tanpa adanya revolusi kebudayaan. Fenomena yang terjadi saat ini adalah budaya borjuis dan hedonis. Padahal dari struktur gaji dan pendapatan, masyarakat kita termasuk para ASN kita tebilang sangat kecil. Kondisi inilah yang memicu terjadinya korupsi dengan berbagai variannya mulai dari tingkat briberi (uang pelicin) hingga katabelece sebagai bentuk dari penyalah gunaan wewenang (abuse of power).
Upaya untuk melakukan revolusi kebudayaan itu bisa dimulai dari pimpinan yang tertinggi (presiden) dengan memberikan keteladanan yang bersifat top down. Selain pemimpin formal, tugas yang strategis ini bisa dilakukan oleh pemimpin non formal seperti tokoh-tokoh agama dan masyarakat maupun politik untuk memberikan guidence (panduan) sesuai dengan nilai-nilai agama maupun falsafah lokal untuk hidup jujur dan sederhana.
Bukan justru menjadi contoh buruk dengan menjelma menjadi pedagang ayat sekaligus mengkomersilkan nilai-nilai agama hanyak untuk mendukung gaya hidupnya yang borjuis, seperti misalnya para pengkotbah yang memasang tarif untuk mendukung gaya hidup mereka yang mewah.Berhasilnya pemberantasan korupsi itu ditandai dengan munculnya kesadaran bahwa korupsi itu kotor dan merupakan perbuatan dosa. Bukan berhasil menangkap koruptor hanya karena apes, ketika modus korupsi mereka terungkap setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyadapan.***