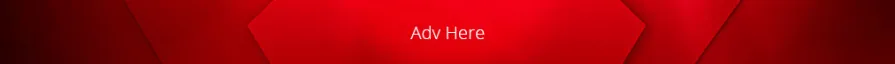Negeri Para Makelar

Ilustrasi
Oleh : Gugus Elmo Ra’is
Budaya hedonis (budaya hidup mewah) dalam struktur masyarakat yang feodal dan kapitalis menentukan nilai kebahagiaan, kehormatan secara artifisial. Kebahagian dan kehormatan seseorang bisa dilihat secara profan berdasarkan materi yang dimiliki. Paradigma seperti itu membuat setiap individu cenderung teraleniasi antara kesadaran ilahiyah dengan implikasi sosialnya. Artinya, banyak individu yang paham jika korupsi atau kolusi itu adalah perbuatan yang haram karena melanggar nilai-nilai agama, tetapi tetap dilakukan demi untuk memenuhi hasrat duniawinya. Sementara dalam masyarakat sekuler, nilai-nilai agama hanya dimaknai sebatas himbauan dan ilmu pengetahuan karena tidak memiliki daya afirmasi (memaksa) karena hanya bersifat sebagai hukum negatif.
Berdasarkan hipotesa seperti itu maka banyak individu yang keluar dari Tupoksinya sesuai dengan profesi masing-masing hanya untuk mendapat keuntungan lebih guna menunjang gaya hidupnya yang hedonis. Apalagi struktur gaji yang diperoleh terutama untuk level pegawai rendahan masih tidak cukup bila dikonversikan dengan tingkat kebutuhan mereka. Kondisi itulah yang memunculkan fenomena banyaknya makelar dalam struktur sosial masyarakat kita. Sebagai bagian dari upaya untuk mencari pendapatan tambahan guna menunjang gaya hidup.
Kata makelar berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bisa bermakna sebagai broker (perantara). Profesi makelar adalah profesi yang menjembatani para pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Tentu dengan berbagai macam kompensasi yang diperoleh oleh makelar. Meski tidak ada parameter yang digunakan untuk menentukan besaran kompensasi yang akan diperoleh oleh makelar.
Fenomena yang saat ini marak adalah adanya makelar politik yang dilakukan oleh para politisi terutama kalangan elit partai. Goal atau target yang ingin dicapai adalah kursi kekuasaan, maka marak terjadinya praktek trading horse (dagang sapi) untuk memuluskan salah satu pihak yang dijagokan untuk duduk di kursi kekuasaan. Ketika target sudah diraih, maka turunan selanjutnya adalah makelar jabatan sekaligus makelar proyek. Sehingga tak mengherankan bila ada ketua umum partai yang tertangkap karena diduga sebagai makelar jabatan. Dan yang paling halus berbentuk trading influense (memperdagangkan pengaruh) yang dilakukan oleh para pejabat. Dengan menguntungkan pihak tertentu dengan harapan untuk memperoleh fee. Maka bisa dimaklumi jika proses perebutan kekuasaan selalu berlangsung sengit.
Makelar politik itu biasanya melakukan sindikasi dengan makelar informasi yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang penulis atau wartawan dengan malakukan kapitalisasi isu demi melakukan penggiringan opini yang bisa menguntungkan salah satu pihak. Sehingga independensi adalah kata yang aneh dan langka dalam konteks kekinian. Maka tak mengherankan bila muncul fenomena hoaks sebagai produk dari makelar informasi.
Untuk menjustifikasi argumentasi politiknya tak jarang, mereka menggunakan jasa pemuka agama. Para pemuka agama yang terbiasa menggunakan tarif dalam memberikan ceramah sekaligus memberikan himbauan itu bisa ‘didakwa’ sebagai makelar ayat. Padahal fungsi kelompok ini memberikan tausiyah kepada masyarakat yang bisa melahirkan karomah serta hidayah bila dilakukan secara lilllahita’ala. Namun faktanya, sering terdengar adanya pemuka agama yang memasang tarif karena budaya hedonis juga menyasar kelompok ini.
Setali tiga uang, tak hanya dalam jagad politik dalam dunia hukum juga tak kalah menyedihkan. Banyak oknum catur wangsa penegakkan hukum seperti polisi, jaksa, hakim serta pengacara yang menjelma menjadi makelar kasus (markus) dengan modus menambah atau mengurangi posita bahkan bila mungkin membebaskan para tersangka yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmmatige daad).
Beberapa profesi yang memiliki tugas yang luhur seperti dokter dan guru juga terkadang dikotori perilaku oknum yang bisa masuk kategori sebagai makelar obat dan makelar bangku. Modus yang dilakukan juga beragam misalnya dalam proses tindakan medis maupun proses menjual bangku dalam proses penerimaan murid.
Dengan realitas sosial seperti itu, maka proses pemberantasan korupsi akan menjadi sia-sia selama tidak ada perubahan secara kosmos. Reformasi hukum dan reformasi struktural akan sia-sia jika kebudayaan kita tidak memberi ruang terhadap setiap individu untuk berubah. Gagasan revolusi mental tak ubahnya seperti gagasan menggarami air laut jika tidak ada revolusi kebudayaan. Karena budaya itu bisa merubah perilaku dan mental setiap individu, bukan sebaliknya. ***
Budaya hedonis (budaya hidup mewah) dalam struktur masyarakat yang feodal dan kapitalis menentukan nilai kebahagiaan, kehormatan secara artifisial. Kebahagian dan kehormatan seseorang bisa dilihat secara profan berdasarkan materi yang dimiliki. Paradigma seperti itu membuat setiap individu cenderung teraleniasi antara kesadaran ilahiyah dengan implikasi sosialnya. Artinya, banyak individu yang paham jika korupsi atau kolusi itu adalah perbuatan yang haram karena melanggar nilai-nilai agama, tetapi tetap dilakukan demi untuk memenuhi hasrat duniawinya. Sementara dalam masyarakat sekuler, nilai-nilai agama hanya dimaknai sebatas himbauan dan ilmu pengetahuan karena tidak memiliki daya afirmasi (memaksa) karena hanya bersifat sebagai hukum negatif.
Berdasarkan hipotesa seperti itu maka banyak individu yang keluar dari Tupoksinya sesuai dengan profesi masing-masing hanya untuk mendapat keuntungan lebih guna menunjang gaya hidupnya yang hedonis. Apalagi struktur gaji yang diperoleh terutama untuk level pegawai rendahan masih tidak cukup bila dikonversikan dengan tingkat kebutuhan mereka. Kondisi itulah yang memunculkan fenomena banyaknya makelar dalam struktur sosial masyarakat kita. Sebagai bagian dari upaya untuk mencari pendapatan tambahan guna menunjang gaya hidup.
Kata makelar berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bisa bermakna sebagai broker (perantara). Profesi makelar adalah profesi yang menjembatani para pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Tentu dengan berbagai macam kompensasi yang diperoleh oleh makelar. Meski tidak ada parameter yang digunakan untuk menentukan besaran kompensasi yang akan diperoleh oleh makelar.
Fenomena yang saat ini marak adalah adanya makelar politik yang dilakukan oleh para politisi terutama kalangan elit partai. Goal atau target yang ingin dicapai adalah kursi kekuasaan, maka marak terjadinya praktek trading horse (dagang sapi) untuk memuluskan salah satu pihak yang dijagokan untuk duduk di kursi kekuasaan. Ketika target sudah diraih, maka turunan selanjutnya adalah makelar jabatan sekaligus makelar proyek. Sehingga tak mengherankan bila ada ketua umum partai yang tertangkap karena diduga sebagai makelar jabatan. Dan yang paling halus berbentuk trading influense (memperdagangkan pengaruh) yang dilakukan oleh para pejabat. Dengan menguntungkan pihak tertentu dengan harapan untuk memperoleh fee. Maka bisa dimaklumi jika proses perebutan kekuasaan selalu berlangsung sengit.
Makelar politik itu biasanya melakukan sindikasi dengan makelar informasi yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang penulis atau wartawan dengan malakukan kapitalisasi isu demi melakukan penggiringan opini yang bisa menguntungkan salah satu pihak. Sehingga independensi adalah kata yang aneh dan langka dalam konteks kekinian. Maka tak mengherankan bila muncul fenomena hoaks sebagai produk dari makelar informasi.
Untuk menjustifikasi argumentasi politiknya tak jarang, mereka menggunakan jasa pemuka agama. Para pemuka agama yang terbiasa menggunakan tarif dalam memberikan ceramah sekaligus memberikan himbauan itu bisa ‘didakwa’ sebagai makelar ayat. Padahal fungsi kelompok ini memberikan tausiyah kepada masyarakat yang bisa melahirkan karomah serta hidayah bila dilakukan secara lilllahita’ala. Namun faktanya, sering terdengar adanya pemuka agama yang memasang tarif karena budaya hedonis juga menyasar kelompok ini.
Setali tiga uang, tak hanya dalam jagad politik dalam dunia hukum juga tak kalah menyedihkan. Banyak oknum catur wangsa penegakkan hukum seperti polisi, jaksa, hakim serta pengacara yang menjelma menjadi makelar kasus (markus) dengan modus menambah atau mengurangi posita bahkan bila mungkin membebaskan para tersangka yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmmatige daad).
Beberapa profesi yang memiliki tugas yang luhur seperti dokter dan guru juga terkadang dikotori perilaku oknum yang bisa masuk kategori sebagai makelar obat dan makelar bangku. Modus yang dilakukan juga beragam misalnya dalam proses tindakan medis maupun proses menjual bangku dalam proses penerimaan murid.
Dengan realitas sosial seperti itu, maka proses pemberantasan korupsi akan menjadi sia-sia selama tidak ada perubahan secara kosmos. Reformasi hukum dan reformasi struktural akan sia-sia jika kebudayaan kita tidak memberi ruang terhadap setiap individu untuk berubah. Gagasan revolusi mental tak ubahnya seperti gagasan menggarami air laut jika tidak ada revolusi kebudayaan. Karena budaya itu bisa merubah perilaku dan mental setiap individu, bukan sebaliknya. ***